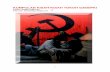Wacana Rekonsiliasi Antara Korban dan Pelaku Pembantaian Pascagerakan 30 September 1965 (Analisis Wacana Kritis Majalah Tempo edisi khusus Pengakuan Algojo 1965 1-7 Oktober 2012) SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S. I. Kom.) Daniel Luke 10120110136 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI MULTIMEDIA JOURNALISM FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA TANGERANG 2014

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Wacana Rekonsiliasi Antara Korban dan Pelaku Pembantaian Pascagerakan 30 September 1965
(Analisis Wacana Kritis Majalah Tempo edisi khusus Pengakuan Algojo 1965 1-7 Oktober 2012)
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S. I. Kom.)
Daniel Luke
10120110136
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KONSENTRASI MULTIMEDIA JOURNALISM
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG
2014
ii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya ilmiah saya sendiri,
bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain, dan
semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah
disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ penyimpangan, baik
dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan laporan skripsi, saya bersedia
menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah Skripsi yang
telah saya tempuh.
Tangerang, 14 Februari 2014
(Daniel Luke)
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi dengan judul
“Wacana Rekonsiliasi Antara Korban dan Pelaku Pembantaian Pascagerakan 30 September 1965 (Analisis Wacana Kritis Majalah Tempo edisi khusus Pengakuan
Algojo 1965 1-7 Oktober 2012)”
oleh
Daniel Luke
telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2014, pukul 08.30 s.d. pukul 10.00 dan dinyatakan lulus dengan susunan penguji sebagai berikut.
Ketua Sidang
Rony Agustino Siahaan, M.Si
Penguji Ahli
Ignatius Haryanto, M.Hum
Dosen Pembimbing
F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A.
Disahkan oleh
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi - UMN
Dr. Bertha Sri Eko M., M.Si.
iv
KATA PENGANTAR
Penulis menyadari bahwa tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini seorang diri.
Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada
beberapa pihak yang telah memberi dukungan baik tenaga maupun moril kepada
penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan praktik kerja magang dan laporannya
dengan baik.
Terima kasih ingin penulis sampaikan kepada :
1. Mas Krisna, pencetus gagasan tentang tema skripsi ini.
2. Pak Lilik, selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Randy Hernando dan Gloria Fransiska yang sudah mengizinkan penulis
menjadikan skripsi mereka menjadi rujukan dan acuan.
4. Bapak Seno Joko Suyono dan Bapak Kurniawan, serta Bapak Asvi Warman
Adam yang telah bersedia menjadi narasumber skripsi ini.
5. Monica Aprilda yang tak pernah putus memberi semangat dan dukungan.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca jika
skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis akan dengan senang hati
menerima segala kritik, saran, serta masukan yang bermanfaat baik bagi penulis sendiri
maupun bagi pembaca yang lain.
Tangerang, 14 Februari 2014
Daniel Luke
v
Wacana Rekonsiliasi Antara Korban dan Pelaku Pembantaian Pascagerakan 30 September 1965
(Analisis Wacana Kritis Majalah Tempo edisi khusus Pengakuan Algojo 1965 1-7 Oktober 2012)
ABSTRAK
Oleh: Daniel Luke
Tragedi pembantaian massal pascagerakan 30 September 1965 masih menyisakan luka bagi Bangsa Indonesia hinga saat ini. Kerugian yang diderita para korban, baik harta benda, trauma fisik maupun mental, hingga dicabutnya hak-hak mereka sebagai warga negara, masih belum dipulihkan seutuhnya oleh Negara.
Untuk menyelesaikan masalah ini hingga tuntas, diperlukan adanya rekonsiliasi antara korban dan pelaku dari peristiwa berdarah tersebut. Rekonsiliasi yang dimaksud tentu saja secara keseluruhan, baik di tingkat masyarakat kecil (mikro) hingga tingkat yang paling tinggi (makro) yaitu pemerintahan. Tanpa adanya rekonsiliasi di semua tingkat, masalah ini tidak akan selesai dengan tuntas.
Penelitian ini melakukan pendekatan secara kualitatif dengan paradigma kritis dan bersifat deskriptif. Data berupa empat artikel dalam Majalah Tempo Edisi Khusus 1-7 Oktober 2012, hasil wawancara dengan Seno Joko Suyono dan Kurniawan dari pihak Majalah Tempo, serta hasil wawancara dengan seorang Sejarawan Indonesia, Asvi Warman Adam, dianalisis menggunakan metode penelitian analisis wacana kritis milik Teun A. van Dijk.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Majalah Tempo memang mewacanakan rekonsiliasi dalam edisi khususnya ini. Bagi Majalah Tempo, rekonsiliasi adalah hal terpenting saat ini, karena dengan adanya rekonsiliasi, Bangsa Indonesia dapat menutup lubang-lubang sejarah yang selama ini ditutup-tutupi serta memulihkan para korban, keluarganya beserta generasi penerusnya dari kerugian yang sudah mereka derita selama ini.
Kata kunci: rekonsiliasi korban dan pelaku, PKI, pembantaian massal pascagerakan 30 September 1965, analisis wacana kritis, Teun A. Van Dijk.
vi
Reconciliation Discourse Between Victims and Perpetrators of September 30th 1965 Post-Movement
Massacre
( Critical Discourse Analysis of Tempo magazine special edition Pengakuan Algojo 1965 1-7 October 2012)
ABSTRACT
By: Daniel Luke
The September 30th 1965 Post-Movement Massacre tragedy still leave a wound for the Indonesian until now. Losses suffered by victims, either of property, physical and mental trauma, and the revocation of their rights as citizens , still not fully recovered by the State.
To resolve this issue to its conclusion , it is necessary to reconciliation between victims and perpetrators of that bloody tragedy. A Whole reconciliation is needed indeed, from the smallest community level (micro) to the highest level (macro) that means the government. Without reconciliation at all levels , this problem will not be resolved completely.
This study is using qualitative approach with a critical paradigm and descriptive characteristic. Data in the form of four articles in Tempo Magazine Special Edition 1-7 October 2012, the results of interviews with Seno Joko Suyono and Kurniawan of the Tempo Magazine, as well as an interview with an Indonesian historian, Asvi Warman Adam, were analyzed by using Teun A. van Dijk's critical discourse analysis research methods.
The results of this study concluded that there is reconciliation discourse by Tempo Magazine in this edition. For Tempo Magazine, reconciliation is the most important thing at this time, due to the presence of reconciliation, Indonesian people can close the holes of history that had been covered up all this time. Furthermore for the victims, their families, and their future generations can recover from the losses that they have suffered over the years.
Keywords : reconciliation of victims and perpetrators, PKI, September 30th 1965 Post-Movement Massacre, critical discourse analysis, Teun A. Van Dijk.
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.........................................................................................................i
HALAMAN PERNYATAAN…………………………..................................................ii
HALAMAN PENGESAHAN.........................................................................................iii
KATA PENGANTAR.....................................................................................................iv
ABSTRAK........................................................................................................................v
ABSTRACT....................................................................................................................vi
DAFTAR ISI..................................................................................................................vii
DAFTAR TABEL............................................................................................................x
DAFTAR BAGAN..........................................................................................................xi
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................1
1.1 LATAR BELAKANG....................................................................................1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.........................................................................15
1.3 TUJUAN PENELITIAN...............................................................................15
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.......................................................................16
1.4.1 MANFAAT TEORITIS.................................................................16
1.4.2 MANFAAT PRAKTIS..................................................................16
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN..............................................................................17
2.1 PENELITIAN TERDAHULU......................................................................17
2.2 TEORI DAN KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN.........................19
2.2.1 WACANA.....................................................................................19
2.2.2 ANALISIS WACANA..................................................................20
2.2.3 ANALISIS WACANA KRITIS....................................................21
viii
2.2.4 IDEOLOGI....................................................................................23
2.2.5 KOMUNISME...............................................................................24
2.2.6 REKONSILIASI............................................................................26
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN.........................................................................29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.......................................................................30
3.1 JENIS DAN SIFAT PENELITIAN..............................................................30
3.2 METODE PENELITIAN.............................................................................32
3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA............................................................33
3.4 UNIT ANALISIS DATA.............................................................................36
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA........................................................................38
3.5.1 ANALISIS TEKS..........................................................................38
3.5.2 KOGNISI SOSIAL........................................................................45
3.5.3 ANALISIS SOSIAL......................................................................46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................................48
4.1 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN..........................................48
4.2 HASIL PENELITIAN..................................................................................50
4.2.1 ANALISIS TEKS ARTIKEL DARI PENGAKUAN ALGOJO 1965...............................................................................................50
4.2.2 ANALISIS TEKS ARTIKEL SEBUAH PENGAKUAN DARI KERUMUNAN POHON KAPUK..................................................56
4.2.3 ANALISIS TEKS ARTIKEL JOSHUA OPPENHEIMER: MEMBUNUH, BAGI ANWAR, ADALAH SEBUAH AKTING......62
4.2.4 ANALISIS TEKS ARTIKEL JALAN LAIN PENYELESAIAN TRAGEDI 1965..............................................................................73
ix
4.3 PEMBAHASAN...........................................................................................89
4.3.1 REKONSILIASI MIKRO...........................................................100
4.3.2 REKONSILIASI MAKRO..........................................................103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.......................................................................108
5.1 KESIMPULAN...........................................................................................108
5.2 SARAN.......................................................................................................112
5.2.1 SARAN AKADEMIS..................................................................112
5.2.2 SARAN PRAKTIS......................................................................112
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................113
LAMPIRAN.................................................................................................................119
ARTIKEL DARI PENGAKUAN ALGOJO 1965..........................................................120
ARTIKEL SEBUAH PENGAKUAN DARI KERUMUNAN POHON KAPUK............121
ARTIKEL JOSHUA OPPENHEIMER: MEMBUNUH, BAGI ANWAR,ADALAH SEBUAH AKTING............................................................................................123
ARTIKEL JALAN LAIN PENYELESAIAN TRAGEDI 1965........................................125
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN MAJALAH TEMPO...............................127
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ASVI WARMAN ADAM.......................133
x
DAFTAR TABEL
TABEL 3.1 PERBEDAAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF..............................30
TABEL 3.2 ELEMEN WACANA VAN DIJK..............................................................39
TABEL 4.1 ARTIKEL 1................................................................................................50
TABEL 4.2 ARTIKEL 2................................................................................................56
TABEL 4.3 ARTIKEL 3................................................................................................62
TABEL 4.4 ARTIKEL 4................................................................................................73
TABEL 4.5 KESIMPULAN.........................................................................................85
xi
DAFTAR BAGAN
BAGAN 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN.....................................................................29
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu sejarah dari Bangsa Indonesia yang masih menyisakan luka yang
begitu mendalam adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di
mana terjadi penculikan 7 jenderal yaitu, Ahmad Yani, Donald Ifak Panjaitan, M.T.
Haryono, Piere Tendean (yang mengaku sebagai Abdul Haris Nasution), Siswondo
Parman, Suprapto, dan Sutoyo Siswomiharjo. Mereka dituduh sebagai "Dewan
Jenderal". Samsudin (2004: 224) menyebutkan bahwa dewan jenderal adalah jenderal-
jenderal yang memiliki pemikiran tidak sejalan dengan pemimpin (Soekarno), mereka
menganut paham anti komunis, sedangkan Soekarno mengizinkan berkembangnya
paham komunis.
Soekarno memang mengizinkan ideologi komunis berkembang dalam negara
Indonesia, seperti yang tertulis dalam Geerken (2011: 58), "untuk tiga ideologi yang
diizinkan di dalam negeri, yaitu partai nasional, partai berbasis agama, dan partai
komunis, Soekarno membuat istilah Nasakom." Nasakom adalah akronim dari
nasionalis, agama, dan komunis.
Para dewan jenderal ini dituduh berencana merebut kekuasaan Soekarno karena
mereka memiliki sikap anti komunis yang fanatik (Fic, 2005: 66). Namun, menurut
Luhulima (2006: 8), dewan jenderal ini adalah bagian dari skenario yang diciptakan
Soeharto untuk merebut kekuasaan Soekarno. Lebih lengkap, Luhulima memaparkan,
2
"Panglima Kostrad Mayjen Soeharto, sejak tanggal 1 Oktober 1965, secara perlahan-lahan menggeser Soekarno dari kedudukannya orang yang paling berkuasa di negeri ini. Langkah itu diawali dengan secara sepihak mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat, menyusul aksi penjemputan paksa para jenderal Angkatan Darat yang berakhir dengan kematian mereka."
Dalam buku Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto terlibat G 30 S, Kolonel Abdul
Latief (2000) memaparkan kesaksiannya. Ia menyatakan bahwa sebenarnya Soeharto
pada saat itu sudah mengetahui akan terjadinya penjemputan paksa ketujuh jenderal
tersebut. Ketika itu Soeharto mengatakan bahwa ia akan segera mengambil tindakan
untuk menyelidi tentang kebenaran dari akan adanya pergerakan itu, namun ternyata
Soeharto tidak melakukan apa-apa, bahkan terkesan membiarkan agar pergerakan itu
terjadi.
Pembiaran tragedi itu terjadi sepertinya memang merupakan bagian dari
rencana Soeharto. Sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat
(PANGKOSTRAD), Mayor Jenderal (Mayjen) Seoharto memiliki posisi yang strategis
untuk menentukan siapa yang dituduh bertanggung jawab atas peristiwa G30S ini
(Luhulima, 2006: 106).
Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang dari peristiwa ini.
Namun Sersan Kepala (Serka) Bungkus dalam Lesmana (2005: 38) menegaskan, "PKI
hanya kambing hitam." Dalam penculikan tersebut, pasukan Pasopati dari Cakrabirawa
dibantu oleh pihak sipil seperti Pemuda Rakyat-yang pro terhadap komunis, untuk
menjaga daerah rumah sekitar penculikan. Sebelum penculikan, mereka di-briefing
oleh Letan Satu Dul Arif yang mengatakan bahwa jenderal-jenderal yang akan diculik
ini merupakan jenderal-jenderal yang ingin membahayakan Soekarno, oleh karena itu
mereka harus melakukan apapun, termasuk membunuh jenderal-jenderal tersebut, demi
3
keselamatan Soekarno. Dengan berpaham melindungi Soekarno inilah, PKI membantu
aksi penculikan tersebut (Matanasi, 2011: 90-91).
Fakta itu diperkuat dengan pernyataan Asvi Warman Adam (2009: 183) yang
mengatakan bahwa Letjen Soeharto membubarkan PKI bukan karena PKI dalang
Gerakan 30 September 1965, tetapi karena ia ingin menghancurkan partai yang
merupakan saingan terberat dalam mencapai puncak kekuasaan.
Sampai sekarang, masih terdapat simpang-siur fakta di masyarakat tentang apa
yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dari istilah yang digunakan saja sudah terdapat
perdebatan di dalamnya. Adam (2009) menyebutkan,
"Pertama, Gestok yang diucapkan dalam pidato-pidato Presiden Soekarno, singkatan dari Gerakan Satu Oktober. Alasannya, peristiwa itu terjadi dini hari tanggal 1 Oktober. Sebaliknya pers militer menyebutnya Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Istilah ini menyalahi kaidah Bahasa Indonesia, namun sengaja dipakai untuk mengasosiasikannya dengan Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman yang kejam itu."
Versi yang paling umum yang diketahui masyarakat adalah Partai Komunis
Indonesia (PKI) lah yang mendalangi semua ini. Hal itu disebabkan karena selama 32
tahun rezim orde baru, Presiden Soeharto memakai istilah G30S/PKI, di mana istilah
itu menuduh PKI sebagai dalang dari peristiwa berdarah itu. Soeharto melarang
terbitnya segala jenis versi/bentuk tulisan lain tentang PKI (Adam, 2009: 140). "Selama
orde baru hanya dikenal dan diperbolehkan satu versi: Partai Komunis Indonesia (PKI)
adalah dalang G30S" (Adam, 2009: 142).
Setelah Presiden Soeharto berhenti sebagai Presiden RI tahun 1998, banyak
buku-buku tentang peristiwa 30 September 1965 yang bermunculan, yang sebelumnya
dilarang terbit selama rezim orde baru. Kata PKI dihilangkan dari istilah G30S/PKI,
terutama dalam buku-buku pelajaran sekolah. Kurikulum yang baru itu disusun
4
berdasarkan masukan dari para ahli (sejarawan, pakar psikologi dan pendidikan serta
kurikulum) dengan mempertimbangkan temuan-temuan baru dalam bidang sejarah,
berupa terbitnya banyak buku-buku tentang G30S yang dilarang terbit selama masa
pemerintahan orde baru (Adam, 2009: 141).
Versi lain tentang G30S disampaikan Anderson (2009) yang mengatakan bahwa
peristiwa 30 September 1965 itu berawal dari persoalan intern TNI Angkatan Darat
(AD). Ada beberapa perwira TNI AD dari Kodam IV/Diponegoro (Jawa Tengah) kesal
melihat para jenderal yang hidup berfoya-foya di Jakarta. Para perwira dari Jawa
Tengah itu kemudian mengajak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan PKI
dalam menjalankan operasinya.
Versi itu tidak dibenarkan oleh Harold Crouch (dalam Roosa, 2008: 106), ia
mengatakan bahwa sebenarnya inisiatif awal gerakan ini muncul dari tubuh TNI-AD
sendiri, sedangkan PKI juga berperan dan bertindak sebagai "pemain kedua". Maksud
dari PKI sebagai pemain kedua adalah sebenarnya yang merencanakan dan
melaksanaan pergerakan penculikan ketujuh jenderal tersebut adalah Angkatan Darat,
namun orang-orang di Angkatan Darat tersebut merupakan orang-orang yang dekat
dengan PKI (Roosa, 2008: 107).
Versi lain yang juga beredar di masyarakat adalah campur tangan Amerika
melalui Central Intelligence Agency (CIA). Dalam artikel berjudul LIPI: CIA Diduga
Dalangi Tragedi PKI, Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam mengatakan, "banyak versi
mengenai terjadinya pemberontakan G30S/PKI, menurut pemerintah dalangnya adalah
PKI. Namun, versi lain mencuat CIA muncul di belakang peristiwa itu. Amerika ikut
berperan dalam kejadian tahun 65." Amerika dituduh ikut terlibat dalam tragedi
5
tersebut karena Amerika ingin menjatuhkan Presiden Soekarno yang pro terhadap
komunis. Sophiaan (2008: 95) membenarkan versi tersebut,
"Ketidaksenangan Amerika terhadap Bung Karno dan Republik Indonesia yang dipimpunnya, sudah muncul ketika kunjungannya yang pertama ke Negara Uncle Sam pada bulan Mei 1956. Waktu itu Bung Karno menjelaskan kepada Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles, dasar politik Indonesia. "Kami tidak mempunyai hasrat untuk meniru Uni Sovyet, juga tidak mau mengikuti dengan membabi buta jalan yang direntangkan oleh Amerika untuk kami. Kami tidak akan menjadi satelit dari salah satu blok," kata Bung Karno kepada Menlu Dulles."
Tragedi yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 - 1 Oktober 1965 itu tidak
selesai begitu saja. Penangkapan dan pembantaian orang-orang yang dituduh PKI
terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Jakarta, Kediri, Jombang, Lumajang,
Tuban, Tulungagung, Banyuwangi, Purwodadi, Bali, Maumere, Medan, Sulawesi, Palu,
dan lain-lain. Pembantaian dilakukan baik oleh angkatan bersenjata / militer, maupun
organisasi masa seperti Barisan Serba Guna (Banser) NU (Susanto, 2003:74).
Selain Banser, Pemuda Pancasila juga ikut serta dalam tragedi tersebut. Bresnan
(2005: 120) mengatakan,
"Military officials in Medan and Jakarta in 1965 organized hoodlums into what was to become one of Indonesia's most powerful paramilitaries, the Pancasila Youth (Pemuda Pancasila). In Medan and Jakarta during late 1965, the Pancasila Youth were mobilized to strike at the Communist Party."
"Para pejabat militer di Medan dan Jakarta pada 1965 mengumpulkan para preman dan memasukkannya ke dalam sebuah organisasi yang akan menjadi paramiliter terkuat di Indonesia, yaitu Pemuda Pancasila. Di Medan dan Jakarta selama akhir 1965, Pemuda Pancasila dikerahkan untuk menyerang Partai Komunis."
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 1965, badan militer yang
resmi di Medan dan Jakarta merekrut preman-preman untuk menjadi pasukan yang
kemudian dinamakan Pemuda Pancasila. Mereka ditugaskan untuk menyerang Partai
Komunis Indonesia.
6
Pada tanggal 4 Oktober 1965, wakil ketua Nahdlatul Ulama (NU), Subchan ZE,
membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh (KAP-
Gestapu). Kesatuan Aksi tersebut mendapat banyak dukungan dari berbagai organisasi
pemuda dan mahasiswa, salah satunya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
(KAMI) yang berdiri tanggal 25 Oktober 1965. Tujuan dibentuknya kesatuan-kesatuan
aksi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberantas orang-orang yang dituduh
PKI (Aritonang, 2004: 342).
Pada 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), didukung
oleh organisasi kesatuan aksi lain seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia
(KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia
(KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) mengajukan tiga tuntutan rakyat
yang dikenal dengan sebutan Tritura. Isi ketiga tuntutan rakyat tersebut adalah
membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-
unsur PKI, dan menurunkan harga bahan pokok (Poesponegoro, 2008: 545).
Tritura tidak berjalan mulus. Masyarakat kecewa karena Soekarno justru
menyingkirkan tokoh-tokoh yang gigih menentang PKI, seperti A. H. Nasution,
Menteri Koordinator Hankam / Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sebaliknya,
Soekarno justru mengangkat sejumlah orang yang diragukan iktikad baiknya, bahkan
orang-orang yang diindikasikan terlibat dalam G30S, seperti Ir. Surachman dan Oei
Tjoe Tat, S.H. (Poesponegoro, 2008: 545).
Di ibukota, rakyat yang tidak puas dengan hasil reshuffle kabinet baru itu pun
menggelar aksi demonstrasi. Tewasnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI),
7
Arief Rachman hakim karena terkena peluru Resimen Cakrabirawa, membuat
demonstran semakin geram (Poesponegoro, 2008: 547).
Puncaknya, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan
Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Meski inti dari isi surat tersebut sebenarnya
adalah Presiden Soekarno memberi perintah kepada Letjen Soeharto untuk
mengembalikan keamanan dan ketertiban Negara Indonesia, namun hingga saat ini,
belum ada kepastian dan kejelasan, apa isi surat perintah tersebut yang sebenarnya
(Wardaya, 2009: 120).
Berbekal surat perintah yang diberikan Soekarno, Soeharto melakukan beberapa
tindakan. Pertama, membubarkan PKI dan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret
1966, sesuai dengan salah satu tunturan rakyat dalam tritura. Kedua, dikeluarkannya
Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri
yang dinilai terlibat di dalam pemberontakan G-30-S / PKI atau memperlihatkan
iktikad tidak baik dalam rangka penyelesaian masalah itu. Ketiga, mengangkat lima
Menteri Koordinator (Menko) ad interim (sementara) yang bersama-sama menjadi
Presidium Kabinet (Poesponegoro, 2008: 551).
Wardaya (2009: 121-122) mengemukakan,
"Tampak sekali bahwa Soeharto menggunakan Supersemar yang sebenarnya adalah perintah presiden (executive order) itu sebagai sebuah 'transfer of authority'. Seolah-olah Bung Karno menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Soeharto sehingga Soeharto boleh melakukan apa saja untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban seakan-akan negara sedang dalam keadaan perang."
Hal itu dibenarkan oleh Soebandrio (dalam Djarot, 2006a: 14-15), "Supersemar
itu bukan pelimpahan kekuasaan. Supersemar itu diserahkan ke Pak Harto. Kalo sudah
8
aman, diserahkan kembali ke Bung Karno. Jadi, Supersemar itu bukan penyerahan
kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto."
Menurut Subandrio (dalam Adam, 2010: 144), Penculikan dan pembunuhan
ketujuh jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari adalah tahap pertama dari empat
tahap kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Disebut kudeta merangkak
karena biasanya sebuah kudeta dilakukan dengan cepat dan tidak terduga, namun
berbeda dengan yang dilakukan Soeharto, ia melakukan kudeta dengan perlahan dan
penuh perencanaan yang matang. Pembunuhan ketujuh jenderal tersebut dilakukan
Soeharto dengan maksud untuk menghabisi pesaing-pesaingnya di Angkatan Darat.
Tahap kedua dari kudeta merangkak Soeharto adalah dengan mendapatkan
Supersemar dari Soekarno dan kemudian membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret
1966. Pembubaran PKI ini dimaksudkan Soeharto untuk melumpuhkan partai dengan
pendukung lebih dari tiga juta orang yang menjadi rival terberat tentara saat itu (Adam,
2010: 144).
Langkah ketiga dalam kudeta merangkak-nya, 18 Maret 1966 Soeharto
menangkap 15 menteri yang loyal kepada Soekarno. Dengan bermodalkan Supersemar,
Soeharto melakukan penangkapan ini tanpa sepengetahuan dan seizin Soekarno
(Pambudi, 2009: 57).
Terakhir, pada tanggal 7 Maret 1967, dengan ditetapkannya TAP MPRS
XXXIII/1967 yang memberhentikan Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden, dan
diangkatnya Soeharto menjadi pejabat presiden.
SI-MPRS kemudian tetap memutuskan antara lain TAP MPRS XXXIII/1967 tentang pencabutan kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno (mulai berlaku surut sejak 20 Februari 1967) karena mulai tanggal tersebut Soekarno telah mengundurkan diri menghindari pemakzulan MPRS. Dengan TAP MPRS ini pula Jenderal Soeharto
9
diangkat sebagai pejabat presiden. Ini setelah 17 tahun jabatan presiden hanya dipegang seseorang tanpa pemilihan, kecuali malahan diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS bentukannya. Demikian pula gelar Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dicabut oleh TAP MPRS NO. XXXV/MPRS/1967. Termasuk meluruskan pengertian mandataris yang banyak disalahgunakan presiden itu (Fatwa, 2009:220).
Setelah melalui empat tahap kudeta merangkak tersebut, pada Sidang Umum
MPRS ke-5 tahun 1968, Soeharto berhasil terpilih sebagai Presiden RI yang kedua.
Soeharto dilantik menjadi Presiden RI yang kedua pada tanggal 27 Maret 1968
(Pambudi, 2009: 168).
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa selama masa pemerintahan
Presiden Soeharto hanya diperbolehkan beredar satu versi cerita tentang PKI, yaitu PKI
sebagai dalang G30S. Hal serupa juga dipaparkan oleh Eros Djarot (2006b: 107) yang
mengatakan,
"Sepanjang pemerintahannya, Soeharto berusaha terus meneriakkan bahaya laten PKI. Orang menuntut soal tanah dituding PKI. Tengok saja ketika warga Kedung Ombo memprotes harga ganti rugi tanah, Soeharto langsung menanggapinya dengan mengatakan bahwa di antara mereka terdapat oknum-oknum PKI."
Lewat berbagai kuasa yang dimilikinya sebagai seorang Presiden, Soeharto
mendoktrin seluruh masyarakat Indonesia bahwa PKI itu kejam. Ditambah lagi,
masyarakat juga diancam dengan adanya dwifungsi ABRI yang diberi kuasa dan
wewenang untuk menumpas siapa saja yang dianggap PKI atau mengancam kedudukan
Soeharto sebagai Presiden. Tak heran jika selama rezim orde baru, kasus G30S yang
mengkambinghitamkan PKI ini tidak bisa terselesaikan (Djarot, 2006b: 107-108).
Setidaknya, ada dua istilah yang terkenal dan sangat ditakuti masyarakat saat
kepemimpinan Soeharto, yaitu petrus (penembak misterius) dan penghilangan paksa
(involuntary disappearance). Petrus ini terjadi sekitar tahun 1980-an, di mana orang-
10
orang yang diindikasikan sebagai penjahat / kriminal (memiliki tato di badannya), akan
ditembak (entah dari mana tembakan itu, sehingga penembaknya tidak diketahui, atau
misterius) di tengah-tengah keramaian dan jasadnya dibiarkan begitu saja sehingga
dilihat oleh orang banyak. Soeharto menyebutnya sebagai shock therapy agar
masyarakat takut dan tidak berani berbuat macam-macam (Abdulgani-Knapp, 2007).
Sedangkan penghilangan paksa adalah menculik orang-orang yang dianggap
dapat menghalangi, menghambat, atau mengancam kekuasaan Soeharto. Kasus
penghilangan paksa ini dimulai dari kasus G30S 1965 sendiri, di mana menghilangkan
secara paksa tujuh jenderal yang dianggap saingan Soeharto di Angkatan Darat,
kemudian dilanjutkan dengan beberapa kasus seperti di Tanjung Priok (1984), di
Talangsari, Lampung (1989), dan penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-
1998 (Hamid, 2007).
Dalam wawancara pada tanggal 19 Desember 2013, Asvi Warman Adam,
sejarawan Indonesia, menuturkan,
"Kekuasaan itu kan diberikan secara penuh kepada Soeharto kan tahun 68, tetapi stigma itu kan diawetkan. Saya menganggap PKI ini bukan hanya dianggap sebagai lawan atau musuh politik, tetapi juga untuk kepentingan lain, sebagai alat pemukul politik. Ini dipelihara sehingga orang yang bukan PKI, yang kritis terhadap pemerintah, itu nanti kan gampang, di cap PKI gitu. Yang kedua ini untuk keperluan praktis, untuk membeli tanah dengan harga murah, kalau mereka tidak mau, nanti di cap PKI gitu.
Jadi kan digunakan sepanjang kekuasaannya, bukan hanya tahun 65 saja, bahkan sampai tahun 98. Jadi untuk dua keperluan tadi, yaitu memukul lawan politik, dan keperluan praktis membeli tanah dengan murah.
Dan itu diawetkan stigma itu dengan monumen-monumen yang dibangun selama orde baru. Monumen Pancasila Sakti itu dibangun pada awal, tapi kita tahu Museum Penghianatan PKI itu baru dibangun tahun 93 di Lubang Buaya juga. Di Gatot Soebroto ini dibangun museum Waspada Purwawisesa namanya, itu museum yang dibangun untuk mengingatkan tentang bahaya dari kelompok Islam radikal. Jadi sepanjang orde baru diciptakan terus itu monumen-monumen, jadi tidak berhenti tahun 66, tapi sepanjang itu ada saja monumen, buku yang dikeluarkan gitu, buku putih setneg (Sekretariat Negara) itu kan tidak dikeluarkan tahun 65-66, 90-an malah itu, jadi artinya sepanjang kekuasaannya selalu dilestarikan stigma itu."
11
Meski Soeharto sudah turun dari jabatannya sebagai presiden sejak 21 Mei 1998
dan sudah banyak pula buku-buku dan tulisan-tulisan yang menceritakan versi lain dari
peristiwa G30S, kasus itu tidak selesai begitu saja. Masih banyak kelompok masyarakat
dan pemuka agama yang masih menganggap PKI berbahaya (Adam, 2009: 159).
Beberapa contoh dari buku dan tulisan yang menceritakan versi lain dari
peristiwa pembantaian massal pasca-G30S 1965 antara lain adalah Palu Arit di Ladang
Tebu tulisan Hermawan Sulistyo, Gangsters and Revolutionaries oleh Robert Cribb,
dan The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali buatan Geoffrey Robinson.
Pada tahun 2000, Majalah Tempo sendiri mengeluarkan artikel berjudul,
ISLAM, MAAF, DAN PKI, di situ tertulis, "MENGAPA kalangan Islam menolak usul
Gus Dur untuk mencabut Ketetapan MPRS XXV/66? Mengapa mereka menyesalkan
usulan Gus Dur untuk minta maaf kepada PKI?" TAP MPRS XXV/66 sendiri berisi
tentang pelarangan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya.
Dengan dicabutnya TAP MPRS XXV/66 ini, berarti PKI boleh berorganisasi lagi di
Indonesia. Artikel tersebut membuktikan bahwa upaya rekonsiliasi antara pihak korban
dan pelaku tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965 belum tercapai.
Upaya dari para aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia untuk
mengungkap kebenaran masa lalu, termasuk kasus G30S ini sudah dimulai sejak tahun
1999. Mereka meminta pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR) beserta undang-undangnya. Namun gagasan mereka tidak berjalan mulus,
banyak pihak yang menolak gagasan tersebut dengan berbagai alasan, demi
kepentingannya masing-masing. Terutama fraksi TNI/Polri yang tidak ingin aib
perbuatan mereka di masa lampau terungkap. Akhirnya, pembentukan KKR baru dapat
12
terwujud pada 7 September 2004, dengan disahkannya UU No.27 Tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh DPR (Sumarwan, 2007: 215-218).
Dibentuknya Komisis Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia ini tidak
terlepas dari berhasilnya beberapa penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang ada
di luar negeri. Misalnya di Chile, dengan kasus hilangnya 600 orang pada masa
pemerintahan Jenderal Pinochet. Selain itu, ada pula penyelesaian kasus pelanggaran
berat hak asasis manusia di Argentina yang diselesaikan dengan membentuk Komisi
Nasional untuk Orang Hilang (Sujatmoko, 2005: 8).
Penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia lain yang dapat
dijadikan panutan adalah dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional untuk
menyelesaikan kasus pembantaian dan penghilangan etnis muslim di Bosnia dan
tragedi Rwanda. Perangkat hukum acaranya menggunakan Statuta Roma. Statuta Roma
adalah adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional
(International Criminal Court). Perjanjian ini diadopsi pada konferensi diplomatik di
Roma pada tanggal 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. Statuta
Roma dibuat untuk melakukan pengadilan bertaraf internasional yang bertujuan untuk
mengadili semua pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat dari negara mana saja
yang menandatangani atau meratifikasi Statuta Roma tersebut (Lubis, 2005: 3-4).
Kembali ke Indonesia, belum sempat menyelesaikan tugasnya, kewenangan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
dengan Putusan MK No.006/PUU-IV/2006 yang mencabut UU No. 27 Tahun 2004
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Gultom, 2010: 308). Ketua Mahkamah
Konstitusi saat itu, Jimly Asshiddiqie (dalam laman Tempo, 2006: Undang-Undang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dibatalkan) mengatakan, "Kewenangan Komisi
13
Kebenaran dan Rekonsiliasi terkesan tidak pasti karena tidak memiliki daya ikat."
Dengan dibatalkannya UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi ini, Asmara Nababan (dalam laman Tempo, 2006: Undang-Undang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dibatalkan) berpendapat, "keputusan ini
mengembalikan posisi pengungkapan masalah HAM berat di masa lalu ke titik nol."
Oleh pihak yang berkuasa (dalam hal ini pemerintah) sengaja memberikan
diskriminasi berupa pemberian kode-kode khusus dalam kartu tanda penduduk (KTP)
seperti ET (eks-tapol) dan OT (organisasi terlarang) pada orang-orang yang terlibat
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PKI (Sumarwan, 2007: 100 dan
151). Diskriminasi tersebut akhirnya dihapuskan oleh Putusan MK,
"Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengabulkan permohonan pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang oleh pemohon dianggap mengandung unsur diskriminasi. Dalam putusan yang dibacakan 24 Februari 2004, eks anggota PKI mendapatkan kembali hak politiknya sebagai warga negara untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Oleh banyak kalangan putusan MK itu dipahami sebagai pemulihan hak-hak politik eks PKI yang selama rezim Orde Baru diperlakukan secara diskriminatif."
Dari artikel Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM yang tertulis dalam
situs resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), diakui bahwa
pemerintah dan DPR memang dirasa kurang serius dalam menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus G30S 1965 silam. DPR
pun bahkan terkesan dijadikan benteng perlindungan bagi para pelanggar HAM masa
lalu. Ditambahkan, "Peran Komnas HAM pun kini semakin penting semenjak
dibatalkannya UU KKR oleh MK tersebut." Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat
disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki kuasa di negeri ini, justru memakai
kekuasaannya untuk melindungi diri mereka atau kelompoknya sendiri, bukan untuk
kepentingan rakyat.
14
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif (dalam
Kasemin, 2004: 114) membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa rekonsiliasi
sulit diwujudkan karena ada masalah intern elite, yaitu perbedaan kepentingan dari para
elite politik di Indonesia, yang membela kepentingannya masing-masing.
Untuk mengenang peristiwa G30S 1965, tahun 2012 lalu Majalah Tempo
mengeluarkan edisi khusus seputar G30S berjudul, Pengakuan Algojo 1965. Selain
menyajikan berbagai pengakuan dari para pembunuh orang-orang yang dituduh PKI,
edisi ini juga mengulas tentang film dokumenter buatan sutradara Joshua Oppenheimer
yang berjudul, Jagal, atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan judul, The Act of
Killing.
Pada tahun 2012 lalu pula, Majalah Tempo mendapatkan penghargaan Yap
Thiam Hien Award 2012. Yayasan Yap Thiam Hien sendiri dikenal sebagai yayasan
yang memang memfokuskan diri untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM). Dari
situs resmi Yayasan Yap Thiam Hien, terdapat artikel berjudul, Majalah Tempo Raih
Yap Thiam Hien Award 2012 (http://tinyurl.com/m6b9bf2). Dari artikel tersebut, ketua
Yayasan Yap Thiam Hien, Todung Mulya Lubis menjelaskan, "karena Tempo tampil
sebagai majalah yang memiliki komitmen lebih dalam isu-isu penegakan keadilan dan
Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia."
Tempo juga sempat mengalami pembredelan oleh pemerintah sebanyak dua
kali, yaitu pada tahun 1982 dan tahun 1994. Alasan kedua pembredelan itu karena
Majalah Tempo dianggap terlalu tajam mengkritik pemerintahan Soeharto.
Penulis melihat, melalui edisi khusus ini, Majalah Tempo ingin menawarkan
rekonsiliasi antara pelaku dan korban dari tragedi G30S. Meski sudah terbit setahun
15
lalu, penulis berpendapat bahwa topik ini masih layak diangkat karena hingga sekarang
belum ada pihak yang berhasil mewujudkan rekonsiliasi tersebut dan kasus
pembantaian massal pasca-G30S ini pun juga belum tuntas hingga saat ini.
1.2 Perumusan Masalah
Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya
adalah:
a. Bagaimana Majalah Tempo mewacanakan rekonsiliasi dalam edisi khususnya
kali ini?
b. Mengapa Majalah Tempo mewacanakan rekonsiliasi dalam edisi khususnya kali
ini?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai
tujuan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana Majalah Tempo mewacanakan rekonsiliasi dalam
edisi khususnya kali ini.
b. Untuk mengetahui mengapa Majalah Tempo mewacanakan rekonsiliasi dalam
edisi khususnya kali ini.
16
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Manfaat teoritis:
Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, serta
lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses
perkuliahan dimana berhubungan dengan komunikasi. Selain itu, diharapkan
penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap teori-teori yang
sudah ada, agar dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial masyarakat
yang terus berubah secara dinamis karena perkembangan teknologi komunikasi
yang sangat pesat saat ini.
1.4.2 Manfaat praktis:
Untuk para akademisi, terutama praktisi jurnalistik, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana cara mewacanakan
suatu hal dalam media massa. Untuk masyarakat, dengan adanya penelitian ini
diharapkan dapat melihat wacana apa yang dituliskan oleh media massa dalam
setiap pemberitaannya.
17
BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Penelitian Terdahulu
Sebuah penelitian yang baik akan merujuk pada hasil dari penelitian-penelitian
sebelumnya yang memiliki fokus penelitian yang sama. Maka dari itu, akan
dicantumkan beberapa tinjauan pustaka dari penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti-peneliti terdahulu.
Penelitian terdahulu pertama, penulis ambil dari skripsi yang dibuat oleh kakak
kelas penulis di Universitas Multimedia Nusantara, Randy Hernando, berjudul,
Konstruksi Realitas Peranan Tentara dalam Pembantaian Massal Pascagerakan 30
September 1965. Penulis mengambil skripsi tersebut sebagai rujukan penulis karena
sama-sama meneliti dari sumber yang sama, yaitu dari Majalah Tempo edisi khusus 1-7
Oktober 2012.
Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Randy dan penulis adalah,
Randy menggunakan metode framing, sedangkan penulis akan menggunakan metode
analisis wacana kritis. Penelitian yang dilakukan oleh Randy juga sangat detail dan
mendalam, ada 12 berita yang dijadikan unit analisisnya.
Dalam penelitiannya Randy menyimpulkan bahwa, Majalah Tempo
menggambarkan tentara sebagai representasi negara menjadi pihak yang memiliki
peranan besar dalam pembantaian massal pascagerakan G-30-S. Pihak tentara
18
melakukan propaganda dan pemanfaatan isu agama serta ancaman terhadap negara
menjadi cara ampuh menggerakan massa untuk bersama menumpas PKI.
Penelitian lain yang penulis ambil adalah, Analisis Wacana Van Dijk Terhadap
Berita "Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft" di Majalah Pantau yang dibuat oleh Tia
Agnes Astuti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penulis mengambil
skripsi tersebut karena menggunakan metode yang sama dengan penulis, yaitu Analisis
Wacana Van Dijk. Penelitian tersebut memang bukan membahas tragedi G30S 1965,
namun membahas peristiwa yang serupa, yaitu tragedi yang terjadi di Simpang Kraft,
Aceh. Peristiwa tersebut juga merupakan tragedi berdarah di mana para tentara
menembaki rakyat sipil yang tidak bersalah. Pembahasan yang dilakukan oleh Tia juga
cukup mendalam dan memenuhi tiga tingkat analisis wacana kritis, sehingga penulis
berpendapat bahwa skripsi ini dapat penulis jadikan acuan bagi penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
Meski topiknya berbeda, penulis dapat menggunakan skripsi ini sebagai rujukan
dan bahan referensi, seperti apa menganalisis dengan metode analisis wacana kritis
milik Teun A. van Dijk ini. Dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui lebih jelas
tentang bagaimana melihat atau mengetahui sebuah leksikon, metafora, dan lainnya,
unsur-unsur yang terdapat dalam analisis teks metode analisis wacana kritis van Dijk.
Dalam skripsi yang penulis buat ini, terdapat persamaan dan perbedaan dengan
penelitian terdahulu yang penulis rujuk di atas. Persamaan dengan penelitian Randy
Hernando adalah penulis dan Randy sama-sama meneliti isi dari Majalah Tempo Edisi
Khusus 1-7 Oktober 2012, sedangkan dengan Tia, penulis sama-sama menggunakan
metode analisis wacana Van Dijk.
19
Namun tentunya juga terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan
penelitian mereka. Penulis meneliti unit analisis yang berbeda dengan Randy, meski
berasal dari majalah yang sama, dan penulis juga meneliti topik yang berbeda dengan
Tia, sekali pun metode yang digunakan sama.
Penelitian yang penulis kerjakan ini menyajikan hal yang berbeda dari kedua
penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas. Penulis menggunakan metode
analisis wacana Van Dijk yang digunakan oleh Tia, untuk menganalisis wacana yang
ada dalam Majalah Tempo Edisi Khusus 1-7 Oktober 2012 yang digunakan oleh
Randy.
2.2 Teori dan Konsep-Konsep yang Digunakan
2.2.1 Wacana
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wacana berarti satuan bahasa
terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, seperti
novel, buku, artikel, pidato, atau khotbah.
Menurut Hasan Alwi (1993) wacana adalah rentetan kalimat yang
berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat
itu. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wacana berarti
kumpulan atau kesatuan dari kalimat-kalimat yang membentuk atau memiliki
suatu makna atau arti tertentu.
Dalam buku The Archaeology of Knowledge (L'Archéologie du savoir)
Michel Foucault (2002) menyatakan bahwa,
20
"discourse describes an entity of sequences, of signs, in that they are enouncements. An enouncement is not a unit of semiotic signs, but an abstract construct that allows the signs to assign and communicate specific, repeatable relations to, between, and among objects, subjects, and statements. Hence, a discourse is composed of semiotic sequences (relations among signs) between and among objects, subjects, and statements."
"wacana menggambarkan suatu entitas urutan, entitas tanda-tanda dalam sebuah pernyataan. Pernyataan yang dimaksud bukanlah unit tanda-tanda semiotik, tetapi sebuah konstruk abstrak yang memungkinkan tanda-tanda untuk menetapkan dan berkomunikasi secara spesifik, hubungan berulang untuk, antara, dan di tengah obyek, subyek, dan pernyataan. Oleh karena itu, wacana terdiri dari urutan semiotik (hubungan antara tanda-tanda) antara dan di tengah obyek, subyek, dan pernyataan."
Jadi, wacana adalah sebuah pernyataan baik berupa lisan maupun tulisan
yang terdiri dari tanda-tanda, simbol-simbol, serta makna-makna tertentu yang
dirangkai sedemikian rupa dan dibuat karena memiliki tujuan tertentu sesuai
dengan kehendak pembuatnya. Dan biasanya tujuannya tersebut cenderung
ke arah untuk memperoleh, mempertahankan atau menentang kekuasaan.
2.2.2 Analisis Wacana
Dikutip dari buku Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of
Natural Language karangan Michael Stubbs (1983:1),
"Roughly speaking, it (discourse analysis) refers to attempts to study the organization of language above the sentence or above the clause, and therefore to study larger linguistic units, such as conversational exchanges or written texts."
"Secara kasar, itu (analisis wacana) merujuk pada upaya untuk mempelajari organisasi dari bahasa di atas kalimat atau di atas klausa, dan karena itu untuk mempelajari unit linguistik yang lebih besar, seperti pertukaran percakapan atau teks tertulis."
21
Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis wacana
mengacu pada upaya untuk mempelajari organisasi bahasa di atas kalimat atau
di atas klausa, itu berguna untuk mempelajari unit linguistik yang lebih besar,
seperti pada percakapan langsung maupun teks tertulis.
Sedangkan menurut Sarwiji Suwandi (2008: 146) analisis wacana adalah
kajian tentang aneka fungsi bahasa atau penggunaan bahasa sebagai sarana
komunikasi. Kita menggunakan bahasa dalam kesinambungan wacana. Dari
keduanya, dapat kita simpulkan bahwa analisis wacana berarti mempelajari
penggunaan bahasa dari unit yang terkecil (penggunaan kata, klausa, dan
seterusnya) untuk menemukan makna keseluruhannya (wacananya).
Jadi ringkasnya, analisis wacana memperhatikan pemakaian bahasa
dalam konteks sosial, terutama interaksi di antara para penutur (Stubbs dalam
Arifin, 2010: 106).
2.2.3 Analisis Wacana Kritis
"Instead of focusing on purely academic or theoretical problems, it
starts from prevailing social problems, and thereby chooses the prespective of
those who suffer most" (Van Dijk dalam Wodak, 2001). Terjemahan: daripada
berfokus pada akademik murni atau masalah teoritis, itu berawal dari
mengungkapkan masalah sosial, dan untuk itu memilih perspektif dari yang
paling menderita.
Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa analisis wacana kritis tidak
berangkat dari teori akademis murni, melainkan dari masalah sosial yang
22
terjadi di masyarakat, diawali dengan pihak yang paling menderita. Melihat
siapa yang sedang berkuasa, bagaimana ia menggunakan kekuasaannya, dan
siapa yang bertanggung jawab atau yang bisa mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada.
Dalam artikel berjudul AWK untuk Menemukan Ideologi yang
Tersembunyi yang terdapat di situs Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Mulyadi
Eko Purnomo, M.Pd. menyatakan pentingnya analisis wacana kritis (AWK)
untuk mengetahui ideologi suatu media, "Tujuan AWK adalah untuk
menemukan ideologi yang tersembunyi di balik suatu wacana, teks, atau
pemakaian bahasa secara publik."
Dalam penerapanya, kata Purnomo, AWK dapat diterapkan untuk
analisis wacana media massa, analisis wacana politik, dan analisis wacana
pembelajaran. Lebih lanjut Purnomo mengatakan, dalam media massa terdapat
ideologi tersembunyi dari pemilik media itu. Pemilik mengusai seluruh kegiatan
produksi, distribusi sampai konsumsi media. Media massa sebagai saluran
komunikasi politik dan sosial masyarakat menjadi produsen informasi politik
dan sosial yang harus setia kepada 'pemilik' informasi. Media massa tidak ada
yang benar-benar netral.
Purnomo menguraikan, bahwa media massa berada di bawah
kepemilikan perorangan atau organisasi, dikelola oleh sekelompok pengelola,
dan akhirnya dibaca oleh kelompok pembaca tertentu pula. Dalam setiap
kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi, terdapat kepentingan
yang harus dipenuhi oleh media massa. Dalam rangka pemenuhan kepentingan
inilah yang membuat media massa menjadi tidak benar-benar netral, tetapi
23
berpihak. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa isi media massa memang
tidaklah netral.
2.2.4 Ideologi
Ideologi adalah seperangkat gagasan yang merupakan tujuan, harapan,
dan tindakan seseorang atau kelompok. Ideologi adalah visi yang komprehensif,
cara melihat berbagai hal dalam kecenderungan filosofis, atau seperangkat ide-
ide yang diusulkan oleh kelas dominan masyarakat untuk semua anggota
masyarakatnya (Kennedy, 1979).
Salah seorang pengikut Marx, Louis Althusser (dalam Zizeg, 2012: 123)
mengungkapkan dua tesis mengenai ideologi. Pertama, “Ideology represents
the imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence.”
Terjemahan dari tesis pertama ini adalah ideologi merepresentasikan relasi
imajiner seorang individu pada kondisi eksistensi riil mereka. Jadi, tesis ini
menawarkan anggapan familiar di kalangan pengikut Marxis bahwa ideologi
memiliki fungsi untuk menutupi susunan eksploitatif yang didasarkan pada
kelas sosial.
Tesis kedua, “Ideology has a material existence.” Terjemahannya adalah
ideologi memiliki eksistensi material. Tesis kedua ini memposisikan bahwa
ideologi tidak berada dalam bentuk ide atau representasi kesadaran dalam
”pikiran” seorang individu, melainkan nyata dalam perilaku.
Selain itu, Althusser juga mengakui peranan dari apa yang disebutnya
sebagai Repressive State Apparatus (Laughey, 2007: 60). Ketika individu dan
24
kelompok menjadi ancaman bagi penguasa dominan, negara akan melibatkan
Repressive State Apparatus. Yang dimaksudkan Althusser dengan Repressive
State Apparatus adalah penguasa yang melibatkan aparat militer yang
melakukan tindakan tindakan represif untuk mengekalkan hegemoni kekuasaan.
Althusser berpendapat bahwa individu dalam masyarakat kapital
dikuasai oleh ideological state apparatuses (ISAs), termasuk sekolah, sistem
hukum, institusi agama, media komunikasi dan seterusnya. ISAs mendukung
ideologi lembaga politik yang kuat seperti pemerintah dan militer, baik dengan
cara implisit maupun eksplisit, dan terkadang tanpa diketahui. Dengan
demikian, individu menginternalisasi ideologi kekuasaan kapitalis, tidak
menyadari bahwa hidup mereka ditindas oleh lembaga yang melayani atau
mempekerjakan mereka.
Jadi intinya, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah nilai-nilai
mendasar yang dianut oleh seseorang atau pihak tertentu, yang akan menjadi
dasar atas segala pola pikir, perasaan dan tindakan yang akan dilakukannya.
2.2.5 Komunisme
Komunis adalah penghapusan segala kepemilikan pribadi. Bahkan,
dalam praktik selanjutnya, kepemilikan pribadi ini bukan hanya yang berupa
harta, melainkan juga berupa kebebasan (Zazuli, 2009)
Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo (2008: 139)
menceritakan bahwa munculnya paham komunisme ini adalah pada abad ke-19,
di mana kondisi sosial yang merugikan kaum buruh di Eropa Barat, seperti upah
25
murah, jam kerja panjang, keselamatan dan kesehatan buruh tidak diperhatikan,
dan sebagainya.
Komunisme sebenarnya berbeda dengan Marxisme. Ajaran asli Karl
Marx yang dibakukan menjadi Marxisme, lebih menekankan kepada perbaikan
sistem sosial masyarakat, sedangkan komunisme lebih cenderung kepada
gerakan dan kekuatan partai-partai komunis dalam bidang politik (Suseno,
2005: 5).
Jadi, paham komunisme sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian
banyak paham yang ada, seperti liberalisme, demokratis, dan sebagainya.
Paham ini muncul karena untuk memberi rasa keadilan bagi kaum buruh di
Eropa Barat yang nasibnya tidak diperhatikan oleh kaum borjuis pada masanya.
Di Indonesia sendiri, paham komunisme sudah ada dan berkembang
sejak awal abad ke-20. Pada tahun 9 Mei 1914, Hendricus Josephus Franciscus
Marie Sneevliet atau Henk Sneevliet mendirikan Indische Sociaal
Democratische Vereniging (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia
Belanda. ISDV menjalin hubungan yang cukup erat dengan Serikat Islam (SI),
yang sama-sama bertujuan untuk membela rakyat kecil (McVey, 2006: 14-15).
Pada Oktober 1915, ISDV menerbitkan surat kabarnya, Het Vrije
Woord, yang berisikan tentang pandangan-pandangan ISDV. Bersama dengan
Sneevliet, Adolf Baars menjadi editor surat kabar tersebut. Untuk
memperbanyak pembacanya, pada tahun 1917 Baars membuat surat kabar
berbahasa Indonesia, Soeara Merdika (Suara Merdeka). Meski Soeara Merdika
26
ditutup setahun setelah terbit, Baars tidak putus asa. Ia menerbitkan surat kabar
baru pada Maret 1918, Soeara Ra'jat (Suara Rakyat) (McVey, 2006: 17).
Seiring berjalannya waktu, terjadi ketidaksepahaman tentang antara
ISDV dan SI tentang apa itu sosialisme. Perpecahan itu membuat ISDV pada
tanggal 23 Mei 1920 mengganti namanya menjadi Partai Komunis Indonesia
(PKI), yang merupakan partai komunis pertama di Asia, di luar kendali
kerajaan Rusia. (McVey, 2006: 47)
2.2.6 Rekonsiliasi
Syamsul Hadi (2007: 37) mengatakan, "Rekonsiliasi perlu dilakukan
jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah
rapuhnya kohesi sosial karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam
dinamika sejarah komunitas tersebut." Salah satu cara untuk mewujudkan
tercapainya rekonsiliasi adalah dengan mencari kata sepakat tentang masa
depan kedua belah pihak yang bertikai tersebut.
Dalam makalah berjudul Hak Asasi Manusia dan Kehidupan Berbangsa
yang ditulis oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI), Sidarto Danusubroto di situs resmi ELSAM (Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat) (http://tinyurl.com/lof5xcv), disebutkan bahwa
rekonsiliasi dapat ditempuh melalui langkah-langkah seperti pengungkapan
kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan
hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk
27
menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan dalam masyarakat (Danusubroto, 2013: 3).
Dalam Makalahnya, Danusubroto juga mengatakan,
"Sesungguhnya bangsa yang besar dan bergerak maju adalah bangsa yang berdamai dengan masa lalu. Agar dapat berdamai dengan masa lalu, kita harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada para korban HAM demi terwujudnya rekonsiliasi."
Ia menyimpulkan, bahwa rekonsiliasi penting diwujudkan guna
membawa Bangsa Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik dengan
meninggalkan dendam politik dan trauma masa lalu (Danusubroto, 2013: 4-6).
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif
(dalam Kasemin, 2004: 114) menyimpulkan bahwa ada dua penyebab mengapa
rekonsiliasi sulit diwujudkan. Yang pertama adalah masalah elite politik yang
saling membela kepentingannya sendiri. Kedua, kualitas masyarakat yang masih
rendah atau menunjukkan sikap ketidakdewasaan, sehingga di antara
masyarakat sendiri tidak mau saling memaafkan dan mau saling menang
sendiri.
2.2.6.1 Rekonsiliasi Mikro
Rekonsiliasi mikro adalah rekonsiliasi antara sesama
masyarakat (secara horizontal). Sesama masyarakat di sini berarti antara
masyarakat yang andil sebagai pelaku pembantaian massal pasca-G30S
1965, dengan mereka yang menjadi korban (atau keluarga korban) dari
tragedi pembunuhan massal pasca-G30S 1965. Rekonsiliasi ini berguna
untuk memulihkan trauma psikologis dan mental korban.
28
Rekonsiliasi mirko secara horizontal ini dapat terjadi jika para
pelaku mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada para
keluarga korban, lalu jika dibutuhkan, pelaku tersebut dapat
memberitahukan nasib terakhir anggota keluarga mereka yang menjadi
korban, seperti kapan dibunuh dan di mana jasadnya berada.
Diharapkan, dengan diketahuinya nasib anggota keluarga mereka
yang hilang, keluarga korban kini dapat ikhlas memaafkan para pelaku,
dan pulih dari trauma yang menghantui mereka selama ini.
2.2.6.2 Rekonsiliasi Makro
Rekonsiliasi makro adalah rekonsiliasi antara pemerintah dan
masyarakat (secara vertikal). Pemerintah yang dimaksud adalah semua
pihak yang terkait dalam kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965
tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain Angkatan Darat yang terlibat
langsung sebagai pelaku pembantaian massal pasca-G30S 1965,
Presiden sebagai kepala negara yang seharusnya bisa menggunakan
kekuasaannya untuk menyelesaikan kasus ini, Mahkamah Konstitusi
yang telah membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta
Mahkamah Agung yang menelantarkan berkas hasil investigasi Tim
Pengkaji Pelanggaran HAM Berat Soeharto (sumber: wawancara dengan
Asvi Warman Adam).
Rekonsiliasi makro ini berguna untuk dan menutupi lubang-
lubang sejarah sekaligus meluruskan sejarah Bangsa Indonesia yang
29
masih gelap dan belum terungkap kebenarannya sampai saat ini. Selain
itu, oleh negara pula, hak-hak para korban dan keluarganya sebagai
Warga Negara Indonesia dapat dipulihkan secara utuh, sehingga mereka
dapat merasakan kesempatan yang sama dalam bidang politik, ekonomi,
dan lainnya, tidak ada lagi diskriminasi atau perbedaan perlakuan.
2.3 Kerangka Pemikiran
Berikut kerangka pemikiran penulis menggunakan analisis wacana kritis Teun
A. van Dijk mengenai wacana rekonsiliasi dalam Majalah Tempo Edisi Khusus 1-7
Oktober 2012.
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran
Tulisan-tulisan dalam Majalah Tempo Edisi Khusus
1-7 Oktober 2012 mewacanakan rekonsiliasi
Analisis Sosial Kognisi Sosial
Analisis Teks
Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk
Analisis Wacana Kritis
Wacana sebagai relasi sosial, praktik sosial, dan produksi gagasan atau pandangan tertentu
Wacana rekonsiliasi disampaikan Majalah Tempo Edisi Khusus 1-7 Oktober 2012
Isu rekonsiliasi antara pelaku dan korban dalam tragedi pasca-G30S 1965
30
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif
deskriptif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitatif berarti berdasarkan mutu
atau kualitas. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan
penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan
prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Strauss,
1997).
Newman (dalam Semiawan, 2010: 80) memaparkan perbedaan antara
perbedaan kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:
Kuantitatif Kualitatif
Mengukur fakta obyektif Mengkonstruksi realitas sosial
Fokus pada variabel Fokus pada proses interaktif
Kuncinya reliabilitas Kuncinya autentisitas
Bebas nilai Perkuat nilai
Bebas dari konteks Tergantung pada konteks
Banyak subyek dan kasus Sedikit subyek dan kasus
Analisis statistik Tematis
Peneliti agak terpisah Peneliti terlibat
Tabel 3.1 Perbedaan kuantitatif dan kualitatif
31
Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau kontrol
terhadap variabel-variabel penelitian tertentu, tetapi mamperlakukan apa adanya dan
memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh (Pawito, 2007: 101).
Lebih lengkap, Pawoto (2007: 103) menjelaskan,
"di sini, peneliti menangkap gejala (mengumpulkan data), mengupayakan validitas dan reliabilitas, kemudian menganalisisnya dengan memilah-milah dan membuat kategori-kategori atau tema-tema tertentu, melakukan reduksi data, memberikan makna-makna atau mengemukakan interpretasi-interpretasi tertentu dengan mengacu pada pandangan-pandangan teoritik tertentu, dan baru kemudian peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan. Dalam hal ini peneliti disarankan untuk membandingkan, menghubung-hubungkan, mempertentangkan, "kesan subyektif" yang diperoleh dari data yang dikumpulkan di satu pihak dengan temuan atau pandangan teoritik dari peneliti lain yang dimunculkan dalam telaah pustaka dengan tetap mempertimbangkan konteks (seting dan akar sejarah) dari temuan atau teori yang dirujuk."
Dapat disimpulkan, hasil penelitian kualitatif memang merupakan hasil
penilaian dari sang peneliti sendiri, namun hasil itu bukanlah hasil yang subyektif.
Hasil penelitian kualitatif diolah sedemikian rupa agar data tersebut valid dan dapat
dipercaya.
Kemudian, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pula, kata deskripsi sendiri
berarti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci;
uraian. Dengan ditambah imbuhan -if, berarti menjadi kata sifat. Sedangkan kata
deskriptif itu adalah bersifat deskripsi; bersifat menggambarkan apa adanya.
Deskriptif berarti menggambarkan suatu hal / fenomena secara rinci dan detail,
berbeda dengan eksplanatif yang umumnya berusaha untuk menjelaskan bagaimana
dan mengapa suatu hal / fenomena tersebut terjadi (Bailey, 2008: 40). Selain itu,
Creswell (2007: 286) menyatakan bahwa deskriptif berarti mendeskripsikan fenomena
atau gejala yang diteliti apa adanya.
32
Penelitian kualitatif deskriptif ini berfokus pada hubungan sosial, hubungan
timbal balik, fenomena sosial, dan hal-hal lain yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial
(Parse, 2001: 58). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini
adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan apa
adanya, tentang pola dan tema dari suatu fenomena sosial yang terjadi (Parse, 2001:
57). Dalam penelitian ini berarti penulis akan menggambarkan secara mendalam hasil
analisis wacananya, baik dari tingkat analisis teks, kognisi sosial, dan analisis sosial.
3.2 Metode Penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis.Van
Dijk (1988: 24) menyatakan, analisis wacana merupakan proses analisis terhadap
bahasa dan penggunaan bahasa dengan tujuan memperoleh deskripsi yang lebik
eksplisit dan sistematis mengenai apa yang disampaikan.
Paradigma kritis berangkat dari cara melihat realitas dengan mengasumsikan
bahwa selalu saja ada struktur sosial yang tidak adil. Dengan begitu dari setiap fakta
dan data yang ditemukan, tidak akan dipercaya begitu saja namun akan diteliti dan
ditelusuri secara mendalam dari mana dan dari siapakah fakta dan data itu berasal dan
adakah bukti atau argumen yang cukup kuat untuk mempercayai informasi tersebut
(Fiske, 2010).
Dari bukunya Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language,
Norman Fairclough (1995) menyatakan bahwa, "Critical discourse analysis (CDA) is
an interdisciplinary approach to the study of discourse that views language as a form
33
of social practice and focuses on the ways social and political domination are
reproduced in text and talk."
Terjemahan: analisis wacana kritis adalah pendekatan interdisipliner untuk
mempelajari wacana yang memandang bahasa sebagai bentuk praktek sosial dan
berfokus pada cara dominasi sosial dan politik yang direproduksi dalam teks dan
pembicaraan.
Deborah Schiffrin, dkk (2001) menyatakan bahwa fungsi utama dari analisis
wacana kritis sendiri adalah menguraikan relasi kuasa, dominasi, dan ketimpangan
yang diproduksi dalam wacana. Sejalan dengan itu, dalam buku berjudul Introduction
to Discourse Studies karangan Renkema (2004: 284), disebutkan bahwa wacana
merupakan refleksi relasi kuasa yang terdapat dalam masyarakat. Analisis wacana kritis
dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi masalah-masalah sosial, terutama masalah
diskriminasi. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting sebagai
perwujudan kuasa pihak tertentu. Suatu teks diproduksi dengan ideologi tertentu yang
ingin disampaikan kepada khalayak pembacanya.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Penulis akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.
Pertama adalah teknik purposive sampling. Proses pengambilan sampel ini dilakukan
dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian
sampel dipilih sesuai keinginan peneliti berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan
sampel tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan (Sugiyono, 2008: 85).
34
Situasi, kondisi, dan berbagai faktor lain biasanya juga mempengaruhi hasil dari
suatu penelitian kualitatif, oleh karena itu peneliti harus menciptakan kondisi dan
situasi yang mendukung, agar data yang diperoleh dapat tepat dan akurat. Oleh karena
itu purposive sampling digunakan untuk memudahkan peneliti mendapatkan sampel
yang cocok dengan situasi dan kondisi yang diinginkan. Selain itu juga, peneliti
terkadang kesulitan mendapatkan data yang diperlukan jika menggunakan random
sampling atau pengambilan sampel secara acak (Babbie, 2008: 204-205).
Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah
bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung
dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik
responden merupakan pola media yang dilengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu,
wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap
perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan
(Gulo, 2000: 119).
Metode wawancara ini memiliki beberapa kekurangan dan keunggulan.
Kekurangannya adalah wawancara memerlukan kesediaan narasumber untuk
diwawancara, jika tidak bersedia, wawancara tidak dapat dilakukan. Selain itu, faktor
bahasa juga terkadang membuat salah pengertian atau pemahaman antara peneliti dan
narasumber. Dibalik kekurangannya, metode wawancara juga memiliki keunggulan
seperti, peneliti mendapatkan data dari narasumber yang diinginkan secara langsung,
tidak seperti angket atau kuisioner yang bisa saja diisi oleh orang lain. Selain itu,
peneliti juga bisa mendapatkan penjelasan yang mendalam dari narasumber tentang hal
yang ingin diketahuinya. Peneliti juga dapat menjalin relasi yang lebih dekat dengan
narasumber (Mohamad Ali dalam Gulo, 2000: 120).
35
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode wawancara semi
terstruktur. Wawancara jenis ini merupakan gabungan / campuran antara wawancara
terstruktur dan tidak terstruktur. Jika wawancara terstruktur dilakukan dengan cara
mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu, dan
wawancara tidak terstruktur hanya mengandalkan intuisi spontan untuk bertanya,
wawancara semi terstruktur (semi-structured interview) ini membuat garis besar hal-hal
yang akan ditanyakan terlebih dahulu, lalu tidak menutup kemungkinan pertanyaan
akan ditambah, diubah, atau dikurangi, sesuai dengan jawaban narasumber pada saat
proses wawancara berlangsung (Wengraf, 2001: 5).
Terakhir, data-data untuk melengkapi penelitian ini penulis dapatkan dengan
metode dokumentasi. Kelebihan dari pengambilan data melalui dokumen adalah karena
dokumen terdiri dari kata-kata dan gambar yang telah direkam tanpa campur tangan
pihak peneliti. Dokumen juga mampu memberikan pemahaman historis yang dapat
bertahan sepanjang waktu. Dokumen tersedia dalam bentuk tulisan, catatan, suara,
gambar, dan digital (Daymon, 2008: 344).
Menurut Bungin (2013: 155), dokumen dibagi menjadi dua jenis, yaitu
dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan seseorang
secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen pribadi
dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Dokumen resmi terbagi lagi
menjadi dua. Pertama adalah dokumen resmi intern, yaitu memo, pengumuman,
instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan,
dan konvensi. Yang kedua adalah dokumen resmi ekstern, yaitu majalah, buletin, berita
yang disiarkan ke media massa, dan pemberitahuan.
36
3.4 Unit Analisis Data
Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yakni analisis wacana kritis
Van Dijk, data yang dianalisis harus mencakup tiga tingkat, yaitu tingkat analisis teks,
tingkat kognisi sosial, dan analisis sosial.
Untuk tingkat analisis teks, penulis akan mengambil beberapa tulisan dengan
metode purposive sampling yang terdapat dalam majalah Tempo Edisi Khusus 1-7
Oktober 2012. Pertama adalah tulisan Dari Pengakuan Algojo 1965 pada halaman 29.
Tulisan ini penulis pilih karena tulisan ini merupakan opini dari redaksi Majalah Tempo
sendiri. Opini yang ditulis oleh redaksi Majalah Tempo ini penulis anggap dapat
mencerminkan bagaimana sikap Majalah Tempo sendiri dalam menyikapi masalah
kasus tragedi G30S dan komunisme.
Kedua, artikel Sebuah Pengakuan dari Kerumunan Pohon Kapuk pada halaman
106-107. Artikel ini merupakan salah satu laporan utama Majalah Tempo dalam edisi
ini, jadi artikel ini penulis pilih karena penulis ingin melihat bagaimana Majalah Tempo
mewacanakan rekonsiliasi dalam laporan utamanya.
Selanjutnya yang ketiga adalah artikel di halaman 122-123 berjudul, Joshua
Oppenheimer: Membunuh, Bagi Anwar, Adalah Sebuah Akting. Topik yang dibahas
dalam Majalah Tempo edisi khusus ini juga tidak terlepas dari film Act of Killing atau
Jagal yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Untuk itu penulis ingin mengetahui
bagaimana Tempo mengulas tentang Joshua Oppenheimer dan filmnya dalam tulisan
ini.
Terakhir, artikel yang penulis ambil ada di halaman 124-125, artikel tersebut
berjudul Jalan Lain Penyelesaian Tragedi 1965. Artikel ini merupakan tulisan
37
pendapat dari seorang M. Imam Aziz, anggota Majelis Syarikat Indonesia, Yogyakarta.
Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengapa salah satu tulisan yang dimuat dalam
Majalah Tempo edisi khusus ini adalah tulisan dari seorang M. Imam Aziz, yang
dituliskan oleh Majalah Tempo sebagai seorang yang aktif dalam upaya rekonsiliasi
tragedi politik 1965.
Keempat artikel ini penulis pilih karena penulis menanggap keempat artikel ini
cukup untuk mewakili empat sudut pandang yang berbeda. Artikel Dari Pengakuan
Algojo 1965 merupakan sudut pandang dari Majalah Tempo sendiri, artikel Sebuah
Pengakuan dari Kerumunan Pohon Kapuk mewakili sudut pandang dari pelaku yang
bersedia mengaku dan meninta maaf atas perbuatan jahatnya. Ketiga, artikel Joshua
Oppenheimer: Membunuh, Bagi Anwar, Adalah Sebuah Akting mewakili sudut
pandang dari pembuat film Jagal atau The Act of Killing yang merupakan gagasan awal
pembuatan edisi khusus ini, dan terakhir, artikel Jalan Lain Penyelesaian Tragedi 1965
merepresentasikan sudut pandang dari salah satu aktivis yang memperjuangkan
rekonsiliasi dari tragedi 1965 tersebut.
Selanjutnya, untuk menganalisis tingkat kognisi sosial, penulis akan melakukan
wawancara dengan Pihak Majalah Tempo, dan yang penulis wawancarai adalah
penanggung jawab dari tim laporan khusus 1965, Seno Joko Suyono dan Kurniawan
selaku Kepala Proyek dari tim laporan khusus 1965. Penulis melakukan wawancara
pada tanggal 20 Desember 2013 pukul 18.40 di Kantor Redaksi Majalah Tempo, Jl.
Kebayoran Baru, Mayestik, Jakarta 12240.
Untuk tingkat analisis sosial, ada dua sumber yang akan penulis gunakan.
Pertama dari studi literatur dan dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan untuk
mendukung penelitian yang penulis lakukan. Kedua, penulis akan melakukan
38
wawancara dengan salah satu sejarawan Indonesia, yaitu Asvi Warman Adam, yang
cukup banyak menulis buku dan membahas tentang kasus tragedi G30S ini. Beliau
penulis pilih karena merupakan salah satu anggota tim Pengkaji Pelanggaran HAM
Berat Soeharto yang dibentuk Komnas HAM tahun 2003. Penulis melakukan
wawancara pada tanggal 19 Desember 2013 pukul 09.10 di Kantor Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gedung Sasana Widya Sarwono, Jl. Jend. Gatot Subroto
10, Jakarta 12710.
3.5 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dari metode
analisis wacana kritis Van Dijk. Van Dijk mengklasifikasikan elemen wacana menjadi
3, yakni teks, kognisi sosial dan konteks sosial.
3.5.1 Analisis Teks
Pada elemen teks, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu struktur makro,
superstruktur dan mikro. Tingkat makro merupakan makna global / umum dari
suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang
dikedepankan dalam suatu berita. Kemudian tingkat superstruktur yang
merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks,
bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga,
tingkat mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari
suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrasa, dan gambar
(Eriyanto, 2001: 226). Pada tingkat kognisi sosial dipelajari proses produksi
berita yang melibatkan kognisi individu penulis berita, sedangkan konteks sosial
39
adalah mempelajari bangunan wacana yang berkembang di masyarakat
(Kuntoro, 2008: 46).
STRUKTUR
WACANA
HAL YANG DIAMATI ELEMEN
Struktur Makro
Makna global dari suatu
teks yang dapat diamati dari
topik/tema yang diangkat
oleh suatu teks
Tematik
Tema/Topik yang
dikedepankan dalam suatu
berita
Topik
Superstruktur
Kerangka suatu teks,
seperti bagian pendahuluan,
isi, penutup, dan kesimpulan
Skematik
Bagaimana bagian dan urutan
berita diskemakan dalam teks
utuh
Skema
Struktur Mikro
Makna lokal dari suatu
teks yang dapat diamati dari
pilihan kata, kalimat, dan
gaya yang dipakai suatu teks
Semantik
Makna yang ingin ditekankan
dalam teks berita, missal
dengan memberi detail pada
satu sisi atau membuat
eksplisit satu sisi dan
mengurangi detail sisi lain.
Latar, detail,
maksud, pra-
anggapan,
nominalisasi
40
Sintaksis
Bagaimana kalimat (bentuk,
susunan) yang dipilih.
Stilistik
Bagaimana pilihan kata yang
dipakai dalam teks berita.
Retoris
Bagaimana dan dengan cara
penekanan dilakukan.
Bentuk
kalimat,
Koherensi,
Kata ganti.
Leksikon
Grafis,
Metafora,
Ekspresi.
Tabel 3.2 Elemen Wacana Van Dijk
3.5.1.1 Tematik
Kata lain dari tema adalah topik, yaitu gambaran umum atau inti
dari suatu berita. Dari tema / topik ini juga dapat dilihat apa yang
sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis berita tersebut. Tema ini juga
mencerminkan pandangan umum yang koheren (koherensi global), yaitu
bagian-bagian teks dalam satu berita, yang jika dirunut akan saling
mendukung satu sama lain dan mencerminkan gambaran umum dari
berita tersebut (Sobur, 2009: 75).
41
3.5.1.2 Skematik
Skema berarti alur atau urutan penyajian tulisan dalam suatu
berita. Ada bagian yang didahulukan, bagian yang mengikuti, dan
bagian yang dihilangkan atau disembunyikan. Secara umum, skema ini
dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah bagian summary (ringkasan),
yang terdiri dari judul dan lead (teras berita) atau paragraf pertama, dan
yang kedua adalah story (cerita), yaitu isi berita secara keseluruhan
(Kuntoro, 2008: 47).
3.5.1.3 Semantik
Dalam semantik ada latar, detail, maksud, praanggapan, dan
nominalisasi. Latar adalah bagian teks yang dapat mempengaruhi arti
dari berita tersebut. Latar yang dipilih dapat menentukan ke mana arah
pandangan khalayak akan dibawa. Biasanya, latar ditulis di awal,
sebelum pendapat penulis yang sebenarnya muncul dengan maksud
mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat penulis sangat
beralasan (Eriyanto, 2001: 235-236).
Detail ialah informasi mengenai suatu hal dalam pemberitaan
tersebut. Jika hal tersebut dirasa penting atau memang adalah tujuan
penulis berita tersebut, maka informasi / detail tentang hal tersebut akan
disebutkan secara lengkap atau bahkan berlebihan, sebaliknya jika hal
tersebut dirasa tidak menguntungkan atau tidak penting bagi penulis,
42
informasi / detail tentang hal tersebut akan dikurangi atau ditulis
seminimal mungkin (Kuntoro, 2008: 48).
Elemen maksud adalah melihat apakah informasi yang
disampaikan dalam suatu berita, disampaikan secara langsung atau tidak,
eksplisit atau implisit. Biasanya, informasi yang penting /
menguntungkan penulis akan disampaikan secara langsung, tegas, dan
eksplisit, sedangkan informasi yang tidak penting atau tidak
menguntungkan bagi penulis akan disampaikan dengan berbelit-belit,
tersamarkan, dan implisit. Tujuannya jelas agar pembaca terfokus pada
hal-hal yang diinginkan / menguntungkan bagi penulis berita tersebut
(Eriyanto, 2001: 240).
Praanggapan adalah pernyataan yang digunakan untuk
mendukung makna suatu teks dengan menggunakan premis yang
dipercaya atau tidak perlu diragukan kebenarannya. Pernyataan tersebut
dimaksudkan untuk mendukung penulis, agar pembaca semakin percaya
kepada apa yang dituliskan oleh penulis dalam berita tersebut (Eriyanto,
2001: 256).
Nominalisasi adalah perubahan dari kata kerja menjadi kata
benda, biasanya dengan menambahkan imbuhan "pe-an". Perubahan
kata itu dimaksudkan untuk merubah kalimat, dari kalimat yang
bermakna pekerjaan / tindakan, menjadi kalimat yang bermakna
peristiwa. Jika kalimat kerja / tindakan membutuhkan dua aktor, yaitu
siapa yang melakukan pekerjaan dan siapa yang terkena dampak dari
pekerjaan itu, kalimat benda tidak membutuhkan dua aktor tersebut,
43
namun lebih menekankan kepada peristiwa yang dialami oleh aktor yang
terkena dampak dari peristiwa tersebut (Eriyanto, 2001: 155).
3.5.1.4 Sintaksis
Dalam sintaksis, yang diperhatikan adalah bentuk kalimat,
koherensi, dan kata ganti. Bentuk kalimat bisa berupa kalimat aktif-
pasif, maupun deduktif-induktif. Kedua bentuk kalimat ini sering
digunakan untuk menonjolkan objek (pelaku peristiwa atau kejadian).
Bentuk kalimat aktif dan pasif ini sering digunakan untuk menonjolkan
atau menyembunyikan pelaku peristiwa yang diberitakan (Kuntoro,
2008: 48).
Koherensi adalah hubungan antarkata, proposisi atau kalimat.
Koherensi digunakan untuk menghubungkan dua buah kalimat atau
paragraf sehingga keduanya saling berhubungan. Sekalipun yang
dihubungkan tersebut adalah dua kalimat yang berbeda gagasannya,
tetap dapat menjadi selaras dan mendukung gagasan utama yang
disampaikan, jika disambung dengan kata sambung yang tepat (Sobur,
2009: 81).
Selanjutnya adalah kata ganti, elemen ini digunakan penulis
untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam suatu teks. Kata
ganti dalam suatu berita digunakan untuk memanipulasi bahasa dan
menciptakan suatu komunitas imajinatif. Dengan menggunakan kata
ganti yang tepat, sulit dipisahkan antara penulis berita dengan khalayak,
44
karena tanggapan yang disampaikan oleh penulis seakan juga menjadi
tanggapan khalayak (Eriyanto, 2001: 253-254).
3.5.1.5 Stilistik
Stilistik dapat diartikan juga sebagai diksi atau pemilihan kata.
Stilistik digunakan untuk menggambarkan citra makna tertentu pada
suatu hal. Stilistik berkaitan erat dengan penulis berita tersebut, karena
bagaimana ia bersikap dan berpihak pada suatu hal dapat dilihat dari
pemilihan kata yang ia lakukan (Kuntoro, 2008: 48).
3.5.1.6 Retoris
Grafis, metafora, dan ekspresi adalah hal yang harus diperhatikan
dalam retoris. Grafis dimaksudkan untuk melihat bagaimana penulis
menuliskan suatu hal dalam berita, tercakup di dalamnya penggunaan
huruf besar, kecil, miring, tebal, garis bawah, warna, serta bentuk
tulisan. Dari situ dapat dilihat mana bagian yang diutamakan /
ditonjolkan, dan mana bagian yang ingin dikesampingkan (Kuntoro,
2008: 49).
Metafora adalah "penyedap" dari pesan pokok yang ingin
disampaikan. Penulis bisa memperkuat pokok pesan yang ingin
disampaikan dengan mempertegas pesan tersebut menggunakan kiasan,
45
peribahasa, pepatah, ungkapan, petuah, dan sebagainya yang sudah
dikenal atau familiar di kalangan khalayak (Eriyanto, 2001: 259).
Terakhir, ekspresi, adalah gaya penulisan yang menonjolkan atau
menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan. Sobur
(2009: 84) menyatakan, "Elemen ini merupakan bagian untuk
memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap
penting) oleh seseorang yang dapat diamati dari teks."
3.5.2 Kognisi Sosial
Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001: 221) mengatakan, "Penelitian atas
wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena
teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati." Dalam
tingkat ini, yang diteliti adalah siapa pembuat teks tersebut, dan hal apa saja
yang mempengaruhinya dalam membuat teks tersebut.
Untuk menjembatani antara analisis teks dan analisis sosial, Van Dijk
membuat dimensi kognisi sosial. Van Dijk membagi kognisi sosial ini menjadi
dua, pertama adalah bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh wartawan /
media, dan yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang ada di masyarakat
menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan dan akhirnya digunakan untuk
membuat teks berita tersebut (Eriyanto, 2001: 222).
Untuk melihat kognisi sosial ini, kita harus mengenali lebih dekat si
penulis berita itu, untuk mengetahui dari mana sumber-sumber yang digunakan
oleh penulis berita, latar belakang si penulis berita sendiri atau medianya, dan
46
kepentingan-kepentingan lain yang ada dibalik penulis berita itu sendiri
(Eriyanto, 2001: 266).
3.5.3 Analisis Sosial
3.5.3.1 Kekuasaan (Power)
Van Dijk mendefinisikan kekuasaan tersebut sebagai
kepemilikan dari suatu kelompok untuk mengontrol kelompok lain.
Kekuasaan ini biasanya didasarkan pada kepemilikan atas barang atau
sumber daya yang bernilai, seperti uang, status, dan pengetahuan. Selain
kekuasaan berupa kontrol yang bersifat langsung, bentuk lain dari
kekuasaan itu juga dapat berupa persuasif, di mana tidakan seseorang
secara tidak langsung mengontrol dan dapat mempengaruhi jalan pikiran
atau kondisi mental seseorang, seperti kepercayaan, sikap, dan
pengetahuan. Kontrol secara tidak langsung tersebut nantinya dapat
berpengaruh pada pemahaman seseorang terhadap sebuah wacana
tertentu (Eriyanto, 2001: 272).
3.5.3.2 Akses (Access)
Akses ini menjadi salah satu perhatian besar bagi Van Dijk,
karena kelompok masyarakat elit mempunyai akses lebih besar
dibandingkan kelompok masyarakat yang tidak berkuasa. Oleh karena
itu, mereka yang lebih berkuasa memiliki kesempatan yang lebih besar
untuk mempunyai akses pada media, sehingga mereka punya
kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak.
47
Akses yang lebih besar tidak sekadar hanya memberi kesempatan
untuk mengkontrol kesadaran khalayak lebih besar, namun juga
membentuk topik dan isi wacana apa yang dapat disebarkan dan
didiskusikan pada khalayak. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki
akses tidak hanya menjadi konsumen dari wacana yang telah ditentukan
oleh kelompok yang memiliki akses, namun kelompok yang tidak
memiliki akses tersebut juga berperan besar lewat reproduksi, karena
wacana yang mereka terima dari kelompok yang memiliki akses
tersebut, disebarkan lewat pembicaraan dengan keluarga, teman sebaya,
dan sebagainya. Lalu akhirnya merujuk pada sebuah manipulasi bahasa
untuk mendapat massa dan dukungan (Eriyanto, 2001: 274).
48
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
Majalah Tempo didirikan oleh Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Usamah, dan
Christianto Wibisono. Edisi perdana Majalah Tempo terbit pada tanggal 6 Maret 1971.
Pada sampul depan edisi perdana ini bertuliskan judul Tragedi Minarni dan Kongres
PBSI, dengan foto Minarni Soedaryanto, seorang pemain bulu tangkis Indonesia
sebagai gambarnya.
Goenawan Mohamad sebagai pemimpin redaksi Majalah Tempo saat itu,
memilih nama Tempo karena menurutnya karena kata ini mudah diucapkan, terutama
oleh para pengecer. Cocok pula dengan sifat sebuah media berkala yang jarak terbitnya
longgar, yakni mingguan. Mungkin juga karena dekat dengan nama majalah berita
terbitan Amerika Serikat, Time (http://korporat.tempo.co/tentang/sejarah).
Goenawan Mohamad (dalam Steele, 2005: 19) mengatakan bahwa tugas
seorang wartawan Tempo adalah mencari kebenaran, seorang wartawan Tempo harus
selalu skeptis. Dalam Majalah Tempo sendiri, ada dua hal yang sama sekali tidak boleh
dilanggar, yaitu menerima amplop (sogokan) dan berita bohong.
Karena keberanian dan ketajamannya dalam memberitakan serta mengkritik
pemerintah, Majalah Tempo sempat dua kali dibredel. Pertama pada tahun 1982, di
mana Majalah Tempo dicabut Surat Izin Terbit (SIT)-nya oleh Ali Moertopo, Menteri
49
Penerangan saat itu, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan
Republik Indonesia, no. 7.6/Kep/Men-pen/1982 tentang pembekuan untuk sementara
waktu Surat Izin Terbit Majalah Mingguan Berita Tempo (Steele, 2005: 106). Menurut
Ali Moertopo sebagai Menteri Penerangan saat itu, Tempo telah melanggar melanggar
kode etik pers "bebas dan bertanggung jawab". Namun sebagian besar masyarakat
yakin bahwa alasan dibredelnya Majalah Tempo saat itu adalah karena terlalu berani
dan tajam dalam memberitakan tentang konflik-konflik yang terjadi seputar pemilu
pada saat itu (Steele, 2005: 107).
Tanggal 11 Juni 1994, Majalah Tempo menerbitkan edisinya yang berjudul
Habibie dan Kapal Itu. Dalam edisi tersebut, Majalah Tempo menuliskan berita tentang
sengketa dalam pemerintahan atas kesepakatan untuk membeli 39 kapal perang bekas
dari Jerman timur. Pemberitaan Majalah Tempo berfokus pada masalah harga
pembelian, serta pada konflik antara Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie
teknologi dengan menteri Keuangan Ma'rie Muhammad. Beberapa hari setelah berita
itu beredar, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Majalah Tempo dicabut oleh
Menteri Penerangan saat itu, Harmoko (Steele, 2005: 234).
Setelah rezim orde baru runtuh, orang-orang yang dahulu bekerja di Majalah
Tempo, berkumpul dan berdiskusi kembali, apakah Majalah Tempo perlu terbit
kembali atau tidak. Alhasil, Majalah Tempo lahir kembali pada tanggal 12 Oktober
1998.
Majalah Tempo dikenal sebagai majalah yang peduli dengan kasus-kasus
pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu kepedulian Majalah Tempo
diwujudkan dalam pemberitaannya yang selalu memberitakan tentang kasus-kasus
pelanggaran HAM di Indonesia serta mewacanakan rekonsiliasi atau solusi-solusi lain
50
yang mungkin dilakukan. Hal tersebut terbukti dengan diraihnya Yap Thiam Hien
Award 2012 oleh Majalah Tempo.
4.2 Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini mencakup tiga tingkat, yang pertama adalah tingkat analisis
teks yang dilakukan penulis terhadap empat artikel dalam Majalah Tempo Edisi Khusus
Pengakuan Algojo 1965, 1-7 Oktober 2012 dengan menggunakan model Teun A. van
Dijk. Kedua adalah hasil dari analisis kognisi sosial yang berupa hasil wawancara
dengan Majalah Tempo, dan yang ketiga adalah hasil analisis sosial berupa studi
literatur dan wawancara dengan sejarawan Indonesia, Asvi Warman Adam.
4.2.1 Analisis Teks Artikel Dari Pengakuan Algojo 1965
Tabel 4.1 Artikel 1
STRUKTUR WACANA
HAL YANG DIAMATI ELEMEN
Struktur Makro
Tematik Judul: Dari Pengakuan
Algojo 1965
Topik Rekonsiliasi harus diawali dengan pengakuan dari para pelaku pembantaian massal 1965.
Superstruktur
Skematik
Dari Pengakuan Algojo 1965
Skema Ringkasan (summary)
Judul Judul tersebut
merupakan kesimpulan dari Artikel tersebut, di mana rekonsiliasi harus dimulai dari pengakuan para algojo (pelaku)
51
REKONSILIASI tidak bisa dimulai dari ingkar; ia harus diawali oleh pengakuan. Itulah yang seharusnya dilakukan para pelaku pembunuhan massal 1965 dan mereka yang menyokong kejadian itu.
Dalam frasa truth and
reconciliation, ....
tragedi 1965. Teras berita (lead)
Artikel ini menggunakan piramida terbalik atau deduktif, di mana kesimpulan dari artikel tersebut berada di awal artikel.
Cerita (story)
Setelah teras berita atau lead, selebihnya adalah penjabaran isi berita secara keseluruhan.
Struktur Mikro
Semantik
Kini, 47 tahun berlalu sejak pembunuhan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengannya.
Para pelaku-juga organisasi serta aparatur negara yang menyokong aksi sadistis itu.
Komisi itu menyimpulkan 78
ribu orang terbunuh-angka yang dipercaya terlalu kecil.
Para pelaku-juga organisasi
serta aparatur negara yang menyokong aksi sadistis itu.
REKONSILIASI tidak bisa
Latar
Artikel ini mengambil latar waktu 47 tahun berlalu untuk mengesankan waktu yang begitu lama.
Detail Memberi penjelasan
lebih tentang siapa para pelaku itu
Memberi penyangkalan terhadap fakta yang diutarakan oleh Komisi Pencari Fakta.
Maksud
Memaparkan secara eksplisit siapa saja yang dimaksud dengan para pelaku itu. Pra-anggapan
Premis bahwa
52
dimulai dari ingkar.
Yang abadi hingga kini: para pelaku-juga organisasi serta aparatur negara yang menyokong aksi sadistis itu- sibuk menyangkal atau membela diri seraya mengingatkan tentang "bahaya laten" komunisme.
Patut disayangkan, 13
tahun setelahnya segelintir ulama NU justru menolak meminta maaf kepada para korban dan meminta Presiden Yudhoyono mengikuti jejak mereka.
Dari Pengakuan Algojo
1965 Itulah yang seharusnya
dilakukan para pelaku pembunuhan massal 1965 dan mereka yang menyokong kejadian itu.
Kini, 47 tahun berlalu sejak
pembunuhan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengannya.
Betapapun penolakan tak
surut, langkah untuk
rekonsiliasi tidak bisa dimulai dari ingkar.
Premis bahwa para
pelaku yang menyangkal atau membela diri itu tidak bisa diubah (abadi).
Premis bahwa ada
kekecewaan terhadap apa yang dilakukan oleh segelintir ulama NU tersebut.
Nominalisasi Terdapat imbuhan "pe-
an" dalam kata "pengakuan" yang berarti adanya penekanan makna dalam kata itu, di mana pengakuan merupakan syarat utama rekonsiliasi.
Terdapat imbuhan "pe-
an" dalam kata "pembunuhan" yang berarti adanya penekanan makna dalam peristiwa pembunuhan itu.
Terdapat imbuhan "pe-
an" dalam kata "pembunuhan" yang berarti adanya penekanan makna dalam peristiwa pembunuhan itu.
Terdapat imbuhan "pe-
an" dalam kata "penolakan"
53
menyembuhkan luka 1965 harus terus dilakukan.
Sintaksis
REKONSILIASI tidak bisa dimulai dari ingkar.
Itulah yang seharusnya
dilakukan para pelaku pembunuhan massal 1965 dan mereka yang menyokong kejadian itu.
Rekonsiliasi masih jauh dari
angan-angan. Permintaan maaf pemerintah
mungkin jadi solusi jangka pendek.
Sebagai kepala negara dan
kiai Nahdlatul Ulama, Gus Dur secara terbuka menyatakan penyesalan. Patut disayangkan, 13 tahun setelahnya segelintir ulama NU justru menolak meminta maaf kepada para korban dan meminta Presiden Yudhoyono mengikuti jejak mereka.
Betapapun penolakan tak
surut, langkah untuk
yang berarti adanya penekanan makna dalam peristiwa penolakan rekonsiliasi itu.
Bentuk kalimat
Kalimat deduktif pada awal artikel, menunjukkan hal utama yang ingin disampaikan dari artikel ini adalah rekonsiliasi.
Kalimat pasif, di mana
kata "itulah" merujuk pada rekonsiliasi yang merupakan inti dari artikel ini.
Kalimat deduktif, di
mana pada awal kalimat disebut kata rekonsiliasi yang merupakan inti dari artikel ini.
Kalimat deduktif,
menyampaikan solusi yang ditawarkan oleh artikel ini secara eksplisit.
Koherensi
Konjungsi "patut disayangkan" menghubung-kan antara reaksi yang timbul terhadap tindakan yang dilakukan oleh Gus Dur.
Konjungsi "betapapun"
menghubungkan antara reaksi
54
menyembuhkan luka 1965 harus terus dilakukan.
Aksi pemerintah ini
diharapkan diduplikasi oleh masyarakat di level yang lebih mikro.
Ide masyarakat tanpa kelas
adalah utopia yang usang dan sia-sia.
Stilistik
Dibuat selama tujuh tahun,
film itu memuat kesaksian terbuka seorang bergajul yang pernah membunuh ratusan orang PKI di Medan.
Kini, 47 tahun berlalu sejak
pembunuhan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengannya.
Retoris Sejumlah algojo lain
menyampaikan apologia yang tak baru: mereka membunuh untuk menyelamatkan negara dari bahaya komunis.
penolakan yang dijabarkan pada paragraf sebelumnya dengan inti dari paragraf ini yang menyampaikan bahwa langkah untuk menyembuh-kan luka 1965 harus terus dilakukan.
Kata ganti
"Masyarakat di level yang lebih mikro" merujuk pada para pelaku pembantaian massal 1965.
"Ide masyarakat tanpa
kelas" menggantikan kata komunisme. Leksikon
Kata "bergajul" mengartikan orang yang buruk kelakuannya atau jahat, dalam hal ini merujuk pada Anwar Congo.
Kata "besar-besaran"
bertujuan untuk menekankan bahwa peristiwa pembunuhan 1965 itu sangat berdampak luas.
Grafis Tidak ada.
Metafora Kata "apologia" berarti
pengakuan kesalahan sekaligus pembelaan terhadap apa yang telah mereka lakukan.
55
Dalam alam pikir Orde Baru yang belum sepenuhnya pupus di masyarakat, permohonan maaf yang diajukan Presiden Abdurrahman Wahid pada awal reformasi dulu layak diapresiasi.
Sebagai pegiat Majelis Syuro
Muslimin, ia mengaku organisasinya terlibat dalam aksi mengganyang PKI.
Ide masyarakat tanpa kelas
adalah utopia yang usang dan sia-sia.
Dalam semangat
mengungkap "truth" itulah film The Act of Killing karya sutradara Joshua Oppenheimer layak mendapat perhatian.
Diksi yang dipakai adalah kata "pupus" yang berarti hilang atau lenyap.
Kata "mengganyang"
dipakai untuk menggantikan kata menghabisi, memberan-tas, atau membunuh. Selain itu, kata ini juga dipakai karena kata "mengganyang" ini juga sedang populer saat itu, dipakai oleh Soekarno untuk mengobarkan semangat nasionalisme Bangsa Indonesia, dengan menyerukan, "Ganyang Malaysia."
"Utopia" berarti sistem
sosial politik yang sempurna yang hanya ada dalam bayangan atau khayalan.
Ekspresi
Menonjolkan ekspresi dengan kata "semangat", yang berarti bagian ini penting bagi penulisnya.
Dari analisis teks artikel Dari Pengakuan Algojo 1965, dapat disimpulkan
bahwa wacana rekonsiliasi memang diangkat oleh Majalah Tempo dalam artikel
tersebut. Wacana rekonsiliasi pada artikel tersebut tersaji dalam beberapa wujud
seperti, pra-anggapan bahwa rekonsiliasi tidak bisa dimulai dari ingkar, teras (lead)
56
yang menuliskan kata "rekonsiliasi" pada kata pertamanya, dan bentuk kalimat deduktif
dan pasif yang merujuk pada rekonsiliasi.
Selain mengemas wacana rekonsiliasi, dalam artikel ini Majalah Tempo juga
mengesankan bahwa peristiwa G30S tersebut adalah tragedi yang begitu mengenaskan.
Hal tersebut terbukti dari beberapa penulisan, seperti leksikon "bergajul", metafora
"mengganyang", serta semantik (detail, maksud, nominalisasi, pra-anggapan) yang
menjabarkan sisi-sisi negatif dari peristiwa G30S tersebut.
Dalam bagian cerita (story) pada artikel ini, dipaparkan tentang pro dan kontra
terhadap proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban dari peristiwa G30S ini. Hal
tersebut dapat terlihat dari pemaparan tentang tindakan Joshua Oppenheimer yang
membuat film The Act of Killing, Presiden Gus Dur yang meminta maaf kepada para
korban, para ulama NU yang meminta Presiden SBY menolak untuk meminta maaf
kepada para korban, dan Wali Kota Palu, Rusdi Mastura yang meminta maaf serta
menjanjikan kesehatan gratis dan beasiswa kepada para korban.
4.2.2 Analisis Teks Artikel Sebuah Pengakuan dari Kerumunan Pohon
Kapuk
Tabel 4.2 Artikel 2
STRUKTUR WACANA
HAL YANG DIAMATI ELEMEN
Struktur Makro
Tematik Judul: Sebuah Pengakuan
dari Kerumunan Pohon Kapuk
Topik Memberi contoh seorang pelaku yang bersedia melakukan pengakuan.
57
Superstruktur
Skematik Sebuah Pengakuan dari Kerumunan Pohon Kapuk
Beberapa pelaku pembunuhan anggota PKI di Palu mengaku dan meminta maaf kepada korban. Rekonsiliasi sedang dirajut di kota itu.
Tak ada penanda apa pun di
kerumunan pohon kapuk tak jauh dari jalan besar....
Skema Ringkasan (summary)
Judul Judul tersebut
merupakan kesimpulan dari Artikel tersebut, di mana rekonsiliasi harus dimulai dari pengakuan. Teras berita (lead)
Teras dari artikel ini memang bukan merupakan kesimpulan, namun merupakan peristiwa inti yang ingin disampaikan dalam artikel ini.
Cerita (story)
Setelah teras berita atau lead, selebihnya adalah penjabaran isi berita secara keseluruhan.
Struktur Mikro
Semantik
Tak ada penanda apa pun di kerumunan pohon kapuk tak jauh dari jalan besar yang menghubungkan dua kelurahan, Loli dan Watusampu, di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Mobil kemudian melaju cepat kembali ke Palu dan Ahmad melihat ada bekas darah segar menempel di sekop di mobil itu.
Tak ada yang tersisa dari
kejayaan suaminya sebagai tokoh partai, termasuk rumah
Latar
Artikel ini mengambil latar tempat di kerumunan pohon kapuk yang ada di Kota Palu, tempat dikuburkannya jasad korban pembunuhan.
Detail
Memberi penjelasan dan penekanan bahwa baru saja terjadi peristiwa pembunuhan dan penguburan jasad.
Memberi penjelasan mendalam tentang harta benda yang habis sehabis-
58
besarnya di Jalan Jenderal Sudirman pun dilego orang.
Sebenarnya, pada 1977, saat
diperiksa Detasemen Polisi Militer Palu, ia sudah menuturkan dengan jelas soal laporan hilangnya petinggi PKI itu, tapi laporan tersebut hanya terkunci di arsip militer.
Pengakuan para pelaku itu
telah menyemai benih rekonsiliasi di Palu.
Pengakuan Ahmad ini
seperti pentil dilepas dari ban bagi keluarga korban.
Pelan-pelan rekonsiliasi mulai bergulir di kota itu. Setiap bulan, para korban dan pelaku bertemu.
Pengakuan Ahmad ini
seperti pentil dilepas dari ban bagi keluarga korban
Sintaksis
Beberapa pelaku pembunuhan anggota PKI di Palu mengaku dan meminta maaf kepada korban. Rekonsiliasi
habisnya.
Maksud Memaparkan secara
implisit bahwa ada indikasi penyembunyian fakta oleh pihak militer.
Memaparkan secara eksplisit bahwa rekonsiliasi sudah mulai terjadi di Palu. Pra-anggapan
Premis bahwa pengakuan sangat penting dan dibutuhkan agar terjadi rekonsiliasi.
Premis bahwa
rekonsiliasi sudah mulai terjadi, terbukti dengan bertemunya korban dan pelaku setiap bulan.
Nominalisasi
Terdapat imbuhan "pe-an" dalam kata "pengakuan" yang berarti adanya penekanan makna dalam kata itu, di mana pengakuan merupakan syarat utama rekonsiliasi.
Bentuk kalimat Kalimat induktif pada
teras (lead) artikel, menunjukkan hal utama yang ingin disampaikan dari artikel
59
sedang dirajut di kota itu. Pengakuan para pelaku itu
telah menyemai benih rekonsiliasi di Palu.
Ahmad memegang erat-erat
rahasia itu selama puluhan tahun. Namun, makin tua usianya, beban itu makin menyesakkan dada. Apalagi dia dikambinghitamkan sebagai pembunuh para petinggi itu.
Pelan-pelan rekonsiliasi
mulai bergulir di kota itu.
Mobil kemudian melaju cepat kembali ke Palu dan Ahmad melihat ada bekas darah segar menempel di sekop di mobil itu.
Stilistik
Empat di antaranya belum
kembali, yakni tiga petinggi PKI yang dihabisi di Watusampu dan Zamrud, pemimpin PKI di Donggala.
Retoris
Ahmad Bantam: "SAYA
BERI TAHU BAHWA
ini adalah rekonsiliasi.
Artikel ini menggunakan penulisan piramida tegak (induktif), karena inti dari tulisan ini ada di akhir artikel.
Koherensi
Konjungsi "namun" dan "apalagi" menghubungkan pertentangan antara memegang erat rahasia tersebut dengan beban batin yang ditanggung.
Konjungsi "pelan-pelan"
menghubungkan antara apa saja yang sudah dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya dengan proses reskonsiliasi yang sudah mulai muncul.
Kata ganti
"bekas darah segar" merujuk pada kejadian pembunuhan yang baru saja terjadi.
Leksikon
Kata "dihabisi" menggantikan kata dibunuh, dan sekaligus mengiaskan bahwa peristiwa itu begitu sadis.
Grafis Kutipan langsung dari
Ahmad Bantam yang
60
KELUARGAMU BUKAN HILANG, TAPI SUDAH DITEMBAK MATI. SAYA YANG MENGGALI KUBURANNYA. SEBENTAR LAGI SAYA MENINGGAL. SAYA TIDAK MAU RAHASIA INI TIDAK DIBUKA. KASIHAN KELUARGA KORBAN."
Rekonsiliasi sedang dirajut
di kota itu. Pengakuan Ahmad ini
seperti pentil dilepas dari ban bagi keluarga korban.
Tak ada yang tersisa dari kejayaan suaminya sebagai tokoh partai, termasuk rumah besarnya di Jalan Jenderal Sudirman pun dilego orang.
Pengakuan para pelaku itu
telah menyemai benih rekonsiliasi di Palu.
"Lega, plong di hati ini.
Selama ini saya sudah ke mana-mana menanyakan keberadaan Bapak, ke Manado, Makassar, Jakarta, bahkan ke Cina dan Rusia,"
namanya diwarnai merah, dan ditulis dengan huruf kapital semua menandakan betapa pentingnya hal tersebut, yaitu pengakuan.
Metafora Kata "dirajut"
menunjukkan sebuah proses yang terlaksana dengan perlahan.
Pengandaian "seperti
pentil dilepas dari ban" ini mengunggapkan sebuah kepuasan karena sebuah fakta yang akhirnya terungkap.
Diksi yang dipakai
adalah kata "dilego" yang berarti dijual atau dipindahtangankan.
Diksi "menyemai benih"
mengiaskan proses rekonsiliasi yang sudah mulai timbul, walau baru kecil atau sedikit.
Ekspresi
Menonjolkan ekspresi dengan kata "lega" dan "plong", yang berarti secara implisit mengatakan bahwa dengan adanya pengakuan, para keluarga korban akan merasakan lega.
61
Dari artikel Pengakuan dari Kerumunan Pohon Kapuk ini, terlihat Majalah
Tempo menjabarkan betapa pentingnya pengakuan dari para pelaku secara eksplisit.
Pengakuan tersebut selain untuk mengawali terjadinya rekonsiliasi, juga bertujuan
untuk melegakan para keluarga korban yang sampai sekarang masih belum tahu nasib
keluarganya yang hilang saat peristiwa G30S.
Terlihat dari judul artikel tersebut, di mana kata pertamanya adalah
"Pengakuan", yang menunjukkan betapa pentingnya sebuah pengakuan, diikuti dengan
teras (lead) yang menuliskan, "Beberapa pelaku pembunuhan anggota PKI di Palu
mengaku dan meminta maaf kepada korban. Rekonsiliasi sedang dirajut di kota itu,"
terdapat lagi kata "mengaku" yang sekali lagi menekankan pentingnya sebuah
pengakuan dalam upaya rekonsiliasi.
Pada artikel ini juga masih digambarkan tentang betapa kelamnya peristiwa
G30S tersebut dengan kata ganti "bekas darah segar", dan leksikon "dihabisi". Kedua
kata tersebut merujuk pada peristiwa pembunuhan yang sadis dan memilukan.
Selanjutnya, dalam story artikel ini juga dijabarkan secara eksplisit tentang
pengakuan yang dilakukan oleh Ahmad Bantam, sebagai salah satu orang yang
menggali kuburan bagi para korban yang dibunuh dalam peristiwa G30S tersebut.
Selain itu, dipaparkan juga pengakuan serta permintaan maaf Rusdi Mastura, Wali Kota
Palu, yang pernah ikut menangkap dan menjaga tempat-tempat tahanan juga
menyaksikan para korban-korban itu disiksa sebelum akhirnya dibunuh.
62
Artikel ini menggunakan gaya paragraf induktif, di mana kesimpulan atau inti
dari artikel ini berada di akhir artikel. Pada akhir artikel tertulis kesimpulan,
"Pengakuan para pelaku itu telah menyemai benih rekonsiliasi di Palu." Kesimpulan itu
menegaskan bahwa Majalah Tempo memang mewacanakan rekonsiliasi dalam edisi
khusus ini, dan cara untuk memulai rekonsiliasi adalah dengan adanya pengakuan dari
para pelaku.
4.2.3 Analisis Teks Artikel Joshua Oppenheimer: Membunuh, Bagi Anwar,
Adalah Sebuah Akting
Tabel 4.3 Artikel 3
STRUKTUR WACANA
HAL YANG DIAMATI ELEMEN
Struktur Makro
Tematik Judul: Joshua Oppenheimer:
Membunuh, Bagi Anwar, Adalah Sebuah Akting
Topik Pendapat Joshua
Oppenheimer sebagai pembuat film Jagal atau The Act of Killing tentang rekonsiliasi.
Superstruktur
Skematik Joshua Oppenheimer: Membunuh, Bagi Anwar, Adalah Sebuah Akting
Bagi Joshua oppenheimer,
Anwar hanyalah simbol dari kekerasan yang terjadi di Indonesia pada 1965. Menurut
Skema Ringkasan (summary)
Judul Judul tersebut
merupakan kesimpulan dari pendapat Joshua Oppenheimer terhadap Anwar Congo, narasumber utamanya dalam film tersebut. Teras berita (lead)
Artikel ini menggunakan gaya piramida terbalik atau deduktif, di mana
63
taksirannya, ada 10 ribu, bahkan mungkin 100 ribu, "Anwar" lain selama pembantaian pasca-1965 itu. Lelaki kelahiran Texas, Amerika Serikat, 1974, ini mengaku, selama pembuatan film, ia melakukan perjalanan yang amat sangat menyakitkan. Selama tujuh tahun ia bergaul dengan Anwar. Kepadanya, Anwar secara jujur dan berani bercerita mengenai pembunuhan yang dilakukannya. Anwar mungkin kecewa terhgadap hasil film yang dibuat Oppenheimer.
Joshua Oppenheimer belajar
film di Havard University dan meraih PhD di Central Saint Martins College of Art and Design, ....
Setelah melihat bagaimana bangganya para jagal atas tindakan mereka dulu itu, apakah ada kemungkinan rekonsiliasi antara pelaku dan korban?
Persoalan utama rekonsiliasi pada dasarnya bukan terletak pada sisi korban atau masalah prosedural, ....
kesimpulan berada pada awal artikel, yaitu menyimpulkan bahwa Anwar Congo hanyalah satu dari sekian banyak pelaku pembunuhan pasca-G30S 1965, dan proses pembuatan film itu begitu menyakitkan bagi semua pihak.
Cerita (story) Dalam artikel ini,
menjelaskan secara singkat biografi dari Joshua Oppenheimer, pembuat film Jagal atau The Act of Killing yang menjadi pemicu lahirnya edisi khusus ini.
Selanjutnya, dipaparkan hasil wawancara Tempo dengan Joshua mengenai proses pembuatan film tersebut.
Pertanyaan terakhir adalah Tempo menayakan pendapat Joshua tentang kemungkinan terjadinya rekonsiliasi, sesuai dengan tujuan utama dibuatnya edisi ini, mewacanakan rekonsiliasi.
Struktur Mikro
Semantik
Selama tujuh tahun ia bergaul dengan Anwar.
Latar
Latar yang diambil ialah latar waktu selama tujuh tahun proses pembuatan film
64
Ketika dia berdansa cha-cha
di lantai atas bekas kantornya, hal itu kelihatannya menjadi simbol impunitas yang dinikmatinya. Dia menari di tempat ratusan orang yang dibunuhnya sendiri.
Awalnya, Anwar ingin
membuat film yang mengagungkan pembunuhan massal-sesuatu yang tak mungkin jadi tujuan saya.
Sering, dalam proses
pembuatan film, saya tidak bisa tidur. Kalaupun bisa, saya bermimpi buruk. Kru saya harus melakukan hal yang sama, dan pasti lebih berat, karena mereka orang Indonesia. Ini negeri mereka.
Persoalan rekonsiliasi ada
pada para pelaku yang tak mau mengakui kesalahan dan kejahatannya akibat upaya pembenaran yang sedemikian gencar, baik yang mereka tanamkan kepada diri sendiri maupun yang dicangkok dari propaganda rezim yang turut mereka bangun.
Killing is always an act. Bila
dimaknakan memang mengerikan. Peragaan itu bukan hanya
itu, menggambarkan sebuah proses yang panjang untuk pembuatan sebuah film.
Detail Memberi penjelasan dan
penekanan tentang tempat Anwar menari, di tempat ia pernah membunuh ratusan orang puluhan tahun yang lalu.
Memberi penjelasan
akan adanya pertentangan antara narasumber dan sutradara saat proses awal pembuatan film.
Reka ulang adegan
pembunuhan yang dilakukan Anwar selama proses pembuatan film begitu sadis, sehingga terbayangkan saat kejadian aslinya. Kesadisan itu membebani pikiran Joshua dan terlebih kru nya.
Menjelaskan bahwa
rekonsiliasi tidak mungkin terjadi bila para pelaku masih tidak mau mengakui kesalahannya dan berusaha untuk mencari pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan.
Maksud Memaparkan secara
implisit bahwa peristiwa pembunuhan massal pasca-
65
peragaan ulang, melainkan juga asli....
Betapapun demikian, sebuah
kesalahan besar jika Anwar kemudian dijadikan kambing hitam, sebagai maskot para pembunuh tahun 1965, karena perannya dalam film.
Sering, dalam proses
pembuatan film, saya tidak bisa tidur. Kalaupun bisa, saya bermimpi buruk. Kru saya harus melakukan hal yang sama, dan pasti lebih berat, karena mereka orang Indonesia. Ini negeri mereka.
Kebanggaan itu bercerita
tentang jiwa rapuh yang kerdil dan tak berani mengakui perbuatannya sebagai sesuatu yang salah dan jahat; dan karenanya diberi kedok narasi perjuangan heroik. Kebanggaan itu akan runtuh dengan sendirinya jika semua tiang penyangga dan fungsinya dirontokkan. Dari situlah terbuka sebuah kemungkinan rekonsiliasi yang sejati. Tidak ketika rezim para pembantai ini masih menjadi pemenang dan berkuasa.
Menurut taksirannya, ada 10
ribu, bahkan mungkin 100 ribu, "Anwar" lain selama pembantaian pasca-1965 itu.
G30S itu benar-benar sadis.
Pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa Joshua sama sekali tidak menganggap Anwar sebagai tokoh utama atau orang yang paling bertanggung jawab atas tragedi pembunuhan massal pasca-G30S tersebut.
Memaparkan secara implisit bahwa peristiwa pembunuhan massal pasca-G30S itu benar-benar sadis.
Paragraf ini bermaksud untuk menjelaskan syarat terjadinya rekonsiliasi, yaitu pengakuan dari pelaku, terutama dari pihak yang berkuasa (pemerintah). Pra-anggapan
Mengiaskan bahwa ada begitu banyak pelaku pembunuhan pasca-G30S yang sama seperti Anwar.
66
Dari awal saya meyakinkan diri saya bahwa semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, Hitler sekalipun, bukanlah seorang monster, melainkan mausia biasa yang sama seperti kita dan bisa mengambil keputusan yang salah.
Kebanggaan yang mereka
tunjukkan memiliki banyak lapisan makna.
Menurut taksirannya, ada 10
ribu, bahkan mungkin 100 ribu, "Anwar" lain selama pembantaian pasca-1965 itu.
Sering, dalam proses
pembuatan film, saya tidak bisa tidur.
Sintaksis
Bagi Joshua oppenheimer, Anwar hanyalah simbol dari kekerasan yang terjadi di Indonesia pada 1965. Menurut
Perkataan Joshua yang menyatakan bahwa dirinya tidak memandang sebelah mata para pelaku pembunuhan massal itu, mereka hanya orang biasa yang mengambil keputusan yang salah.
Anggapan bahwa para
pelaku itu sebenarnya tahu dan sadar bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang salah dan jahat, namun mereka tidak mau mengakuinya dan menutupinya dengan berbagai alasan.
Nominalisasi
Terdapat imbuhan "pe-an" dalam kata "pembantaian" yang berarti adanya penekanan makna pada banyaknya jumlah pelaku yang terlibat dalam peristiwa berdarah itu.
Penekanan pada
peristiwa saat dibuatnya film tersebut, di mana Joshua tidak bisa tidur karena terbayang-bayang oleh reka ulang adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Anwar.
Bentuk kalimat Kalimat deduktif pada
teras (lead) artikel, menunjukkan ringkasan dari apa yang akan dijelaskan
67
taksirannya, ada 10 ribu, bahkan mungkin 100 ribu, "Anwar" lain selama pembantaian pasca-1965 itu. Lelaki kelahiran Texas, Amerika Serikat, 1974, ini mengaku, selama pembuatan film, ia melakukan perjalanan yang amat sangat menyakitkan. Selama tujuh tahun ia bergaul dengan Anwar. Kepadanya, Anwar secara jujur dan berani bercerita mengenai pembunuhan yang dilakukannya. Anwar mungkin kecewa terhgadap hasil film yang dibuat Oppenheimer.
Mereka disanjung sebagai
pahlawan, jadi tokoh masyarakat dan panutan, serta ditakuti sekaligus dihormati sebagai pelindung bangsa dari sebuah teror berupa fantasi yang mereka ciptakan sendiri.
Ketika dia berdansa cha-cha di lantai atas bekas kantornya, hal itu kelihatannya menjadi simbol impunitas yang dinikmatinya. Dia menari di tempat ratusan orang yang dibunuhnya sendiri.
Killing is always an act. Bila
dimaknakan memang mengerikan. Peragaan itu bukan hanya peragaan ulang, melainkan juga asli....
Mereka tidak merasa ada
yang salah jika publik menilai
pada bagian isi (body) artikel pada paragraf-paragraf berikutnya.
Kalimat pasif ini menggunakan kata "mereka" yang merujuk pada para pelaku pembunuhan massal pasca-G30S yang justru mendapatkan berbagai keuntungan dari perbuatan jahat yang mereka lakukan.
Koherensi
Kata "dia" yang merujuk kepada Anwar, menjadi konjungsi kedua kalimat ini dengan memberi penjelasan tambahan tentang tempat di mana ia menari.
Konjungsi "bila" dan
"melainkan", memberi penekanan makna bahwa peristiwa pembunuhan itu begitu sadis.
Konjungsi "bukan
hanya" memberikan makna
68
bahwa mereka lebih kejam daripada PKI. Bukan hanya merasa, mereka memang betul-betul berada di atas angin.
Ia memilih menunjukkan
kepada kami sebuah cara yang sangat otentik sekaligus sangat menyakitkan yang memaparkan betapa tindakan pembunuhan itu adalah sebagian dari jiwa dan kemanusiaannya. Menyelami relung-relung gelap itu bersama Anwar sungguh menyeramkan.
Dari situlah terbuka sebuah
kemungkinan rekonsiliasi yang sejati. Tidak ketika rezim para pembantai ini masih menjadi pemenang dan berkuasa.
Menurut taksirannya, ada 10
ribu, bahkan mungkin 100 ribu, "Anwar" lain selama pembantaian pasca-1965 itu.
Mereka disanjung sebagai
pahlawan, jadi tokoh masyarakat dan panutan, serta ditakuti sekaligus dihormati sebagai pelindung bangsa dari sebuah teror berupa fantasi yang mereka ciptakan sendiri.
Menyelami relung-relung
gelap itu bersama Anwar sungguh menyeramkan.
bahwa para pelaku pembunuhan itu sebenarnya sudah menyadari bahwa mereka lebih kejam daripada PKI.
"Menyelami" menjadi
kata penghubung kedua kalimat ini. Kata "menyelami" itu bermakna bahwa bagi Joshua, mengetahui perbuatan masa lalu Anwar secara detail sebagai tukang jagal adalah sesuatu yang menyeramkan.
Kata hubung "tidak" ini
menyampaikan bahwa rekonsiliasi tidak bisa terjadi jika para pelaku masih menjadi pemenang dan berkuasa.
Kata ganti
Kata "Anwar" menggantikan para pelaku pembunuhan dan pembantaian massal pasca-G30S di seluruh Indonesia.
Kata "mereka" juga
menggantikan para pelaku pembunuhan dan pembantaian massal pasca-G30S di seluruh Indonesia.
"Relung-relung gelap"
merujuk kepada reka ulang adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Anwar.
69
Para algojo itu juga menghadapi persoalan psikologis untuk mengatasi trauma yang mereka alami, mungkin tanpa disadari atau disadari tapi kemudian dengan sengaja disembunyikan.
Stilistik
Menurut taksirannya, ada 10
ribu, bahkan mungkin 100 ribu, "Anwar" lain selama pembantaian pasca-1965 itu.
Mereka disanjung sebagai
pahlawan, jadi tokoh masyarakat dan panutan, serta ditakuti sekaligus dihormati sebagai pelindung bangsa dari sebuah teror berupa fantasi yang mereka ciptakan sendiri.
Ketika dia berdansa cha-cha
di lantai atas bekas kantornya, hal itu kelihatannya menjadi simbol impunitas yang dinikmatinya
Menyelami relung-relung
gelap itu bersama Anwar sungguh menyeramkan.
Dari awal saya meyakinkan
diri saya bahwa semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, Hitler sekalipun, bukanlah seorang monster, melainkan mausia biasa
Kata "algojo" juga menggantikan para pelaku pembunuhan dan pembantaian massal pasca-G30S di seluruh Indonesia. Leksikon
Kata "Anwar" menggantikan para pelaku pembunuhan dan pembantaian massal pasca-G30S di seluruh Indonesia.
Kata "fantasi" dipakai
untuk menggambarkan bahwa hal tersebut tidak nyata, hanya berupa khayalan saja.
"Impunitas" berarti
kebal terhadap hukum, bebas dari hukuman yang seharusnya diterima karena sudah melakukan kesalahan atau kejahatan.
Dipilih kata "relung-
relung gelap" karena melihat reka ulang adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Anwar itu sangatlah membebani pikiran.
Kata "monster"
menggambarkan sebuah makhluk yang sadis, brutal, dan tidak memiliki perasaan.
70
yang sama seperti kita dan bisa mengambil keputusan yang salah.
Kebanggaan itu bercerita
tentang jiwa rapuh yang kerdil dan tak berani mengakui perbuatannya sebagai sesuatu yang salah dan jahat; dan karenanya diberi kedok narasi perjuangan heroik.
Retoris
Peragaan itu bukan hanya peragaan ulang, melainkan juga asli....
Killing is always an act. Menyelami relung-relung
gelap itu bersama Anwar sungguh menyeramkan.
Diksi "heroik" dipilih
untuk menyampaikan bahwa bagi para pelaku pembunuhan massal tersebut, mereka merasa seolah-olah tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan kepahlawanan yang membela dan menyelamatkan orang banyak.
Grafis Tiga titik di akhir
kalimat tersebut mengisyaratkan pembaca untuk membayangkan sendiri, betapa sadis dan menyeramkannya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Anwar dan para algojo lain saat itu.
Metafora Kutipan berbahasa
Inggris tersebut dapat diterjemahkan, "membunuh selalu merupakan sebuah tindakan." Kutipan tersebut disampaikan untuk menegaskan bahwa bagaimanapun juga, membunuh adalah tindakan yang salah.
"Relung-relung gelap"
mengiaskan suatu hal yang buruk dan kelam pada masa lalu, dalam hal ini merujuk pada pembunuhan yang
71
Kebanggaan itu bercerita
tentang jiwa rapuh yang kerdil dan tak berani mengakui perbuatannya sebagai sesuatu yang salah dan jahat; dan karenanya diberi kedok narasi perjuangan heroik.
Lelaki kelahiran Texas,
Amerika Serikat, 1974, ini mengaku, selama pembuatan film, ia melakukan perjalanan yang amat sangat menyakitkan.
Sering, dalam proses
pembuatan film, saya tidak bisa tidur. Kalaupun bisa, saya bermimpi buruk.
dilakukan oleh Anwar. Diksi "jiwa rapuh yang
kerdil" merujuk kepada para pelaku pembunuhan dan pembantaian massal pasca-G30S yang tidak berani mengakui perbuatannya, bahkan mencari pembenaran atas kesalahannya.
Ekspresi
Premis "amat sangat menyakitkan" tersebut mengungkapkan betapa beratnya perjuangan Joshua selama pembuatan film tersebut. Perjuangan tersebut dapat diartikan sebagai beban mental, di mana melihat langsung reka ulang adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Anwar.
"Bermimpi buruk"
sering diasosiasikan dengan peristiwa yang menjadi beban pikiran dan terus terbayang hingga akhirnya terbawa sampai mimpi. Dalam hal ini, yang menjadi beban pikiran Joshua dan para kru nya adalah reka adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Anwar yang begitu sadis dan kejam.
72
Berdasarkan hasil wawancara dengan Majalah Tempo, Penanggung jawab edisi
khusus ini, Seno Joko Suyono mengatakan,
"Ide itu pertama-tama datang secara tidak langsung, waktu itu Ariel Heryanto di Melbourne mengirim resensi film Act of Killing, dia selama ini telah banyak meneliti film-film Indonesia yang berkaitan dengan G30S dan PKI, menurut dia ini film yang paling kontroversial, karena bukan dari sisi korban tapi dari sisi pelaku. Setelah saya baca, loh ini menarik, kenapa tidak kita kembangkan menjadi edisi khusus, film ini hanya menjadi satu bagian tertentu, sementara kita mencari pelaku-pelaku dari daerah-daerah lain, itu ide awalnya dari resensi film Ariel yang kita kembangkan."
Sekilas tentang Ariel Heryanto, ia adalah Profesor dan Wakil Direktur
(Pendidikan), sekolah budaya, sejarah, dan bahasa Universitas Nasional Australia. Dia
bergabung dengan Australia's National University (ANU) pada tahun 2009 dan
memegang posisi sebagai Kepala bagian Asia Tenggara, Fakultas Studi Asia sebelum
berubah menjadi Sekolah Budaya, Sejarah dan Bahasa. Sebelumnya dia adalah wakil
pembicara Program Indonesia dari Asia Institute, The University of Melbourne. Dua
gelar pertamanya (Sarjana Muda dan doktorandus) adalah di bidang pendidikan dari
Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia. Ia memperoleh gelar MA dalam Studi
Asia dari University of Michigan (USA), dan gelar PhD di bidang antropologi budaya
dari Monash University. (https://researchers.anu.edu.au/researchers/heryanto-
a/#biography)
Artikel ini secara garis besar adalah hasil wawancara Majalah Tempo dengan
Joshua Oppenheimer, sutradara film Jagal atau The Act of Killing, film yang menjadi
inspirasi bagi Majalah Tempo untuk membuat edisi khusus ini.
Film Jagal atau The Act of Killing sendiri adalah film yang menampilkan
Anwar, seorang pelaku pembantaian pasca-G30S 1965. Film itu menunjukkan Anwar
yang memperagakan ulang cara-cara pembunuhan yang ia lakukan kepada para korban
pembantaian massal pasca-G30S. Film ini menjadi menarik karena para pelaku tersebut
73
justru bangga untuk mengakui tindak pembunuhan sadis yang mereka lakukan dengan
dalih membela negara dari bahaya komunisme.
Pertanyaan yang diajukan oleh Majalah Tempo sebagian besar adalah seputar
proses pembuatan film itu sendiri dan tokoh utamanya, Anwar Congo. Namun
pertanyaan terakhir yang diajukan oleh Majalah Tempo adalah mengenai pendapat
Joshua tentang kemungkinan terjadinya rekonsiliasi, hal itu mengindikasikan bahwa
Majalah Tempo memang mewacanakan rekonsiliasi dalam edisi khusus ini.
Dalam artikel ini kental kesan bahwa peristiwa pembunuhan massal pasca-
G30S 1965 itu memang sangat sadis, kejam, dan menyeramkan. Hal tersebut terbukti
dengan berbagai hal, seperti dari penyertaan kutipan berbahasa Inggris, "Killing is
always an act", nominalisasi dalam kata "pembantaian", kata ganti "algojo", serta
metafora "relung-relung gelap" dan ekspresi "mimpi buruk".
Artikel ini juga mengajak para pembaca ikut menghayati dan membayangkan
betapa sadis dan kejamnya para pelaku pembunuhan massal pasca-G30S 1965 itu
dengan grafis tanda baca "titik" tiga (...) yang mengisyaratkan pembaca agar mereka
masing-masing menggunakan imajinasinya untuk "mengisi" kekosongan dari titik-titik
itu.
4.2.4 Analisis Teks Artikel Jalan Lain Penyelesaian Tragedi 1965
Tabel 4.4 Artikel 4
STRUKTUR WACANA
HAL YANG DIAMATI ELEMEN
Struktur Makro
Tematik Judul: Jalan Lain
Penyelesaian Tragedi 1965
Topik Berbagai solusi untuk
menyelesaikan tragedi 1965.
74
Superstruktur
Skematik Jalan Lain Penyelesaian Tragedi 1965
Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia menyimpulkan bahwa terdapat banyak bukti permulaan untuk menduga telah terjadi sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa 1965.
Pembunuhan massal.
Peristiwa ini dirancang dan digerakkan dengan garis komando yang jelas, ... . ... Garis komandonya melalui semua kementerian, Kejaksaan Agung, tentara nasional, dan kepolisian.
Komini Nasional Hak Asasi
Manusia merekomendasikan agar
Skema Ringkasan (summary)
Judul Judul tersebut
merepresentasikan bahwa ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tragedi pembunuhan massal pasca-G30S 1965. Teras berita (lead)
Dalam teras artikel ini terdapat rangkuman dari pelanggaran HAM berat apa saja yang terjadi pada saat peristiwa pembantaian massal pasca-G30S 1965.
Cerita (story) Artikel ini
menggunakan gaya paragraf campuran deduktif-infuktif. Hal tersebut dapat dilihat dari Isi artikel ini yang setidaknya dapat dibagi menjadi dua bagian besar.
Inti dari bagian pertama
adalah menjabarkan tentang bagaimana pelanggaran HAM berat itu terjadi dan terus berlanjut dari tahun 1965 hingga kini.
Sedangkan inti dari
bagian kedua adalah tawaran
75
Jaksa Agung dapat menindaklanjutinya temuan ini dengan penyidikan. ... . Tapi membiarkan masalah ini berlarut-larut akan membuatnya menjadi beban bangsa ini, dari generasi ke generasi.
dari solusi-solusi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan kasus tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965 tersebut.
Struktur Mikro
Semantik
Data ini belum dihapus sampai sekarang, dan pergerakan orang-orang ini tetap terpantau, walaupun sudah berpindah domisili.
Kejahatan kemanusiaan itu
meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran secara paksa, perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
Rantai komando sangat jelas,
yakni Kopkamtib sebagai wujud pelaksaan Surat Perintah 11 Maret.
Di sini terdapat perlakuan-
perlakuan dari aparat pelaksana yang di luar batas kemanusiaan. Penyiksaan, pemerkosaan, dan perendahan martabat manusia yang bentuknya bermacam-macam, sehingga para korban mengalami trauma psikologis dan
Latar
Latar yang diambil ialah latar waktu. Terbukti dengan premis "sampai sekarang" yang berarti ada hal yang belum terselesaikan dari dulu (sejak peristiwa G30S 1965) hingga sekarang.
Detail
Menjabarkan dengan detail kesembilan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dimaksud.
Memberi penjelasan
secara implisit siapa orang yang bertanggung jawab atas peristiwa mengenaskan tersebut.
Menjelaskan lebih lanjut
bentuk-bentuk perlakuan dari aparat pelaksana yang di luar batas kemanusiaan.
76
fisik yang luar biasa. Pembunuhan massal.
Peristiwa ini dirancang dan digerakkan dengan garis komando yang jelas, dan dilaksanakan dengan berbagai cara: pembunuhan dilakukan secara langsung oleh militer, atau dengan menggunakan tangan-tangan sipil yang terlatih sehingga terkesan terjadi konflik horizontal.
Garis komandonya juga dari
Kopkamtib. Kita harus menghormati
rekomendasi ini. Jumlah korbannya tentu
lebih banyak dari yang terbunuh ataupun yang ditangkap dan dipenjarakan.
Kita harus menghormati rekomendasi ini.
Maksud Menekankan bahwa
peristiwa pembunuhan massal ini bukan sebuah ketidaksengajaan, melainkan terencana dengan rapi dan dengan garis komando yang jelas.
Bermaksud untuk
menegaskan bahwa tragedi ini dilakukan secara sengaja dan terencana oleh pemegang kekuasaan waktu itu.
Penulis artikel ini, Imam
Aziz, mengajak pembacanya untuk mendukung Komnas HAM dalam upayanya menyelesaikan kasus tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini. Pra-anggapan
Meyakinkan pembaca bahwa dampak dari tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini sangat luas, lebih dari sekedar mati atau hilang.
Imam Aziz menganggap
bahwa semua pembaca setuju dan mendukung Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus ini.
77
Kejahatan kemanusiaan itu
meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran secara paksa, perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
Pembunuhan massal. Karena itu, menurut saya,
perlu diusulkan kemungkinan penyelesaian nonyudisial, yakni penyelesaian secara politik dan kultural.
Sintaksis
Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia menyimpulkan bahwa terdapat banyak bukti permulaan untuk menduga telah terjadi sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa 1965.
Peristiwa ini dirancang dan
digerakkan dengan garis komando yang jelas, dan dilaksanakan dengan berbagai cara: pembunuhan dilakukan secara langsung oleh militer, atau dengan menggunakan tangan-tangan sipil yang terlatih sehingga terkesan terjadi konflik horizontal.
Nominalisasi Terdapat imbuhan "pe-
an" dalam kesembilan kata yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut. Itu berarti adanya penekanan makna pada peristiwa-peristiwa mengenaskan yang terjadi saat itu.
Penekanan pada
peristiwa saat orang-orang yang dituduh sebagai PKI dibunuh secara besar-besaran pasca-G30S 1965.
Menekankan bahwa
kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini harus segera diselesaikan, dengan cara apapun.
Bentuk kalimat Kalimat aktif pada awal
teras artikel ini menunjukkan bahwa Komnas HAM berperan aktif dalam upaya menyelesaikan tragedi pembunuhan massal pasca-G30S 1965 ini.
Kalimat pasif yang
menekankan bahwa ada orang yang bertanggung jawab di balik peristiwa berdarah tersebut.
78
Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia merekomendasikan agar Jaksa Agung dapat menindaklanjutinya temuan ini dengan penyidikan.
Penyelesaian atas tragedi di
1965 masih akan menimbulkan kotroversi, baik dari institusi negara, khususnya TNI, maupun kelompok masyarakat yang belum bersedia membicarakan perlunya penyelesaian masalah masa lalu. Tapi membiarkan masalah ini berlarut-larut akan membuatnya menjadi beban bangsa ini, dari generasi ke generasi.
Prioritas penyelesaian
nonyudisial tragedi 1965, menurut saya, adalah pemulihan korban.
Pada akhirnya mereka dipenjarakan di penjara-penjara di kota masing-masing, yang lamanya berkisar satu hingga tiga tahun. Ini pun tidak melalui pengadilan. Garis komandonya juga dari Kopkamtib.
Kalimat aktif ini
menunjukkan bahwa Komnas HAM berperan aktif dalam upaya menyelesaikan tragedi pembunuhan massal pasca-G30S 1965 ini dengan memberi rekomendasi kepada Jaksa Agung.
Kalimat deduktif pada
akhir artikel ini menunjukkan bahwa artikel ini bergaya campuran deduktif-induktif. Dalam paragraf ini disampaikan bahwa masalah ini harus secepatnya diselesaikan, meski akan menimbulkan kontroversi.
Salah satu inti artikel
yang terdapat di tengah-tengah artikel, menunjukkan artikel ini menggunakan gaya campuran deduktif-induktif. Pada kalimat ini disampaikan bahwa yang terpenting dalam penyelesaian kasus tragedi 1965 itu adalah pemulihan korban.
Koherensi
Konjungsi "ini pun" menegaskan bahwa pemenjaraan itu dilakukan seenaknya, tanpa melalui proses pengadilan. Sedangkan kata hubung "juga" menegaskan bahwa semua rangkaian peristiwa tersebut direncanakan oleh pihak-
79
Ada pengawasan terus-
menerus, data pribadi serta keluarga mereka terdapat di semua kantor desa/kecamatan, dan terdapat kode-kode tertentu yang membedakan mereka dari warga biasa, yang tercantum dalam kartu tanda penduduk. Data ini belum dihapus sampai sekarang, dan pergerakan orang-orang ini tetap terpantau, walaupun sudah berpindah domisili.
Kedua, orang yang tidak
pernah mengalami pemenjaraan dan penyiksaan fisik tapi dikenai predikat "tidak bersih lingkungan", yang didefinisinya sangat longgar sehingga siapa saja yang diduga terkait secara darah, pertemanan, atasan-bawahan, dan sebagainya dengan orang-orang yang dikategorikan sebagai Golongan B dan C akan mendapat perlakuan khusus yang bisa menghilangkan hak-hak mereka, khususnya dalam jabatan pemerintahan, guru, karyawan di perusahaan milik negara, bahkan swasta. Akibatnya, banyak yang kehilangan jabatan dan pekerjaan atau kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, hak pilih, dan sebagainya. Jumlah korbannya tentu lebih banyak dari yang terbunuh ataupun yang ditangkap dan dipenjarakan.
Kita harus menghormati
pihak tertentu, dalam hal ini Kopkamtib yang memegang kekuasaan saat itu.
Frasa "data ini"
menghubungkan kalimat itu dengan kalimat sebelumnya, dengan memberi penjelasan yang lebih detail tentang hal tersebut.
Kata hubung
"akibatnya" menghubungkan sebab-akibat dari kalimat sebelumnya, di mana orang-orang yang tergolong "tidak bersih lingkungan" kehilangan hak-haknya sebagai warga negara karena mereka memiliki hubungan tidak langsung dengan orang-orang yang ditangkap dan dituduh PKI tersebut.
Kemudian kata "tentu" mengindikasikan bahwa dampak dari peristiwa tersebut begitu besar dan luas, jauh melebihi yang terbunuh ataupun yang ditangkap dan dipenjarakan.
Konjungsi "bagaimana-
80
rekomendasi ini. Bagaimanapun, penyelesaian atas pelanggaran HAM dalam tragedi 1965 merupakan tanggung jawab negara. Seyogianya presiden sebagai kepala negara menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.
Presiden dapat mewakili
"peran" itu dengan mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan mengakui terjadinya pelanggaran HAM. Dengan demikian, para korban akan kembali menjadi warga negara seutuhnya dan setara.
Penyelesaian atas tragedi di
1965 masih akan menimbulkan kotroversi, baik dari institusi negara, khususnya TNI, maupun kelompok masyarakat yang belum bersedia membicarakan perlunya penyelesaian masalah masa lalu. Tapi membiarkan masalah ini berlarut-larut akan membuatnya menjadi beban bangsa ini, dari generasi ke generasi.
Rantai komando sangat jelas,
yakni Kopkamtib sebagai wujud pelaksaan Surat Perintah 11 Maret.
Kita harus menghormati
pun" menguatkan pernyataan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus tragedi pembunuhan massal pasca-G30S 1965 ini. Kemudian kata "seyogianya" juga mendukung kalimat sebelumnya, di mana menyebutkan presiden sebagai wakil dari pemerintah untuk melaksanakan solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh Komnas HAM.
Frasa "dengan
demikian" mengantarkan kalimat sebelumnya kepada kesimpulan akan hasil yang akan diperoleh jika pemerintah melakukan apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM tersebut.
Konjungsi "tapi"
mempertentangkan antara resiko yang diambil jika menyelesaikan kasus tersebut dengan dampak negatif yang akan timbul jika kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini tidak diselesaikan.
Kata ganti Satu-satunya orang yang
menerima Surat Perintah 11 Maret (supersemar) adalah Soeharto.
Kata "kita" merujuk
81
rekomendasi ini. Seyogianya presiden sebagai
kepala negara menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.
Presiden dapat mewakili "peran" itu dengan mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan mengakui terjadinya pelanggaran HAM.
Penyelesaian atas tragedi di
1965 masih akan menimbulkan kotroversi, baik dari institusi negara, khususnya TNI, maupun kelompok masyarakat yang belum bersedia membicarakan perlunya penyelesaian masalah masa lalu.
Stilistik
Peristiwa ini dirancang dan digerakkan dengan garis komando yang jelas, dan dilaksanakan dengan berbagai cara: pembunuhan dilakukan secara langsung oleh militer, atau dengan menggunakan tangan-tangan sipil yang terlatih sehingga terkesan terjadi konflik horizontal.
Agar tragedi kemanusiaan itu
tidak terulang, pemerintah berkewajiban mengubah peraturan dan kebijakan yang selama ini menjadi alat legal untuk menyingkirkan warga yang berbeda pandangan politik.
pada ajakan Imam Aziz kepada para pembaca.
Saat artikel ini
dipublikasikan, yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono.
Kelompok masyarakat
yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam pembantaian massal pasca-G30S 1965 dan tokoh masyarakat atau pemuka agama yang organisasinya dahulu ikut terlibat dalam peristiwa itu.
Leksikon
Frasa "garis komando" dipakai untuk menggambarkan bahwa peristiwa pembantaian massal pasca-G30S ini merupakan sebuah kesengajaan yang direncanakan dan diatur oleh orang yang memegang kekuasaan.
"Alat legal" merujuk
kepada undang-undang, peraturan, ketetapan, kebijakan, dan sebagainya, yang justru mendiskrimi-nasikan warga negara yang dahulu dilabeli sebagai golongan B, C, atau "tidak
82
Retoris
Gambar kaki orang menginjak bayangan putih dengan latar belakang berwarna merah darah.
Pada sebelah kanan atas
dipaparkan biografi singkat penulis artikel tersebut:
M. IMAM AZIZ, ANGGOTA MAJELIS SYARIKAT INDONESIA, YOGYAKARTA, DAN AKTIF DALAM UPAYA REKONSILIASI TRAGEDI POLITIK 1965.
Seyogianya presiden sebagai
kepala negara menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.
Permintaan maaf secara
resmi itu menjadi tonggak bagi rekonsiliasi nasional, mengajak semua pihak untuk menatap ke depan, dan memulai hidup baru
bersih lingkungan".
Grafis Gambar tersebut
mengiaskan tentang seseorang yang memiliki kuasa (kaki orang) di atas orang lain (bayangan), sehingga orang yang berkuasa tersebut dapat melakukan apa saja terhadap orang yang tidak memiliki kuasa, yang dalam hal ini adalah pembantaian massal pasca-G30S 1965 (latar belakang berwarna merah darah).
Pada biografi singkat
ini, ditulis secara gamblang bahwa M. Imam Aziz adalah seorang yang aktif dalam upaya rekonsiliasi tragedi politik 1965, sehingga wajar jika Majalah Tempo memasukkan tulisannya ke dalam edisi khusus ini, karena sesuai dengan apa yang ingin diwacanakan oleh Majalah Tempo, yakni rekonsiliasi.
Metafora
Kata "seyogianya" melambangkan sudah sepatutnya presiden memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan hal tersebut.
"Tonggak" mengiaskan
suatu dasar, landasan, dan pondasi yang kokoh.
83
saling berdampingan dengan hak dan kewajiban yang sama.
Permintaan maaf dibarengi
dengan rencana tindak lanjut untuk mengakhiri jurang pemisah antara masyarakat asli dan non-asli Australia dalam membangun harapan baru, pendidikan, dan kesempatan yang sama dalam ekonomi serta politik.
Di sini terdapat perlakuan-
perlakuan dari aparat pelaksana yang di luar batas kemanusiaan.
Kita harus menghormati
rekomendasi ini.
Frasa "jurang pemisah"
ingin mengutarakan sesuatu yang sangat jauh atau tidak mungkin disatukan. Dalam hal ini, Imam Aziz ingin mengatakan bahwa jika ada niat dan kemauan, hal yang tidak mungkin pun dapat menjadi mungkin (rekonsiliasi).
Ekspresi
Premis "di luar batas kemanusiaan" mengekspresikan betapa tidak manusiawinya perlakuan penyiksaan yang dilakukan para aparat kepada para tahanan atau korban.
"Harus menghormati"
memberi kesan bahwa rekomendasi itu adalah sesuatu yang sangat penting sehingga harus didukung dan dihormati.
Majalah Tempo tentu saja tidak sembarangan dalam memilih tulisan siapa yang
akan dimuat dalam edisi khusus ini. Seperti yang disampaikan oleh Seno, bahwa orang-
orang yang tulisannya dimuat dalam edisi ini adalah orang-orang yang benar-benar
paham dengan masalah ini, sudah melakukan penelitian, dan memiliki misi yang sama
dengan Majalah Tempo, yaitu rekonsiliasi.
84
Dalam artikel bergaya campuran deduktif-induktif ini, terdapat dua pokok
bahasan, dari paragraf satu hingga enam membahas tentang kasus-kasus pelanggaran
HAM yang terjadi, kemudian mulai dari paragraf ketujuh hingga selesai membahas
tentang solusi-solusi yang ditawarkan atau direkomendasikan oleh Komnas HAM
kepada pemerintah untuk segera/secepatnya dilakukan.
Dari paragraf pertama hingga keenam, ditekankan kepada kejamnya pemerintah
dan pihak-pihak yang termasuk sebagai pelaku pada peristiwa pembantaian massal
pasca-G30S 1965. Hal tersebut dapat dilihat dari penjabaran secara detail kesembilan
pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi, leksikon "garis komando", serta
konjungsi atau hubungan antar kalimat yang menceritakan tentang penderitaan para
korban yang disebabkan oleh diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Sedangkan untuk pokok bahasan kedua, ditekankan pada pemerintah yang harus
meminta maaf secara resmi kepada masyarakat, terutama para korban, diikuti dengan
pengembalian hak-hak mereka sebagai warga negara secara utuh. Hal tersebut terbukti
dari kata "kita" yang merupakan ajakan Imam Aziz selaku penulis artikel tersebut
kepada para pembacanya untuk mendukung Komnas HAM dalam menuntaskan kasus
ini.
Selain itu, ada setidaknya empat kali repetisi kata "permintaan maaf" dalam
artikel tersebut, itu menandakan bahwa permintaan maaf itu sangat penting. Kemudian,
Imam Aziz juga mengutarakan pendapat pribadinya, di mana ia memprioritaskan
pemulihan para korban dalam penyelesaian kasus pembantaian massal pasca-G30S
1965 tersebut.
85
Artikel bergaya campuran deduktif-induktif ini ditutup dengan sebuah
kesimpulan pertentangan, di mana rekonsiliasi atau penyelesaian kasus pembunuhan
massal pasca-G30S 1965 ini harus tetap dituntaskan, meskipun masih ada pihak yang
menentang atau tidak mau mendukung upaya penyelesaian masalah ini.
Dari keempat artikel yang dianalisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan
secara garis besar sebagai berikut:
Tabel 4.5 Kesimpulan
STRUKTUR WACANA
HAL YANG DIAMATI
ELEMEN TERDAPAT DALAM
ARTIKEL Struktur Makro
Tematik
Topik Rekonsiliasi dimulai dari
pengakuan.
1, 2, 4
Superstruktur
Skematik
Skema Ringkasan (summary)
Judul Terdapat kata
"pengakuan" pada judul. Teras berita (lead)
Pentingnya pengakuan dari pelaku.
Peristiwa pembantaian
massal pasca-G30S 1965 tidak bisa dilupakan begitu saja.
Cerita (story)
Pentingnya rekonsiliasi.
1, 2 1, 2 3,4 1, 2, 3, 4
Struktur Mikro
Semantik
Latar
Mengesankan waktu yang
1, 3, 4
86
Sintaksis
cukup panjang dan lama.
Detail Tindak pelanggaran HAM
yang terjadi pada saat peristiwa pembantaian massal pasca-G30S 1965.
Siapa saja yang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965.
Maksud
Kurangnya niat pemerintah dan aparat untuk menyelesaikan kasus ini.
Pra-anggapan
Rekonsiliasi sangat penting.
Nominalisasi
"Pengakuan" atau "Permintaan maaf"
"Pembantaian" atau
"pembunuhan"
Bentuk kalimat
Deduktif berintikan rekonsiliasi atau pengakuan dan permintaan maaf dari pelaku.
Aktif mendukung
rekonsiliasi.
Koherensi Menghubungkan
pertentangan antara penolakan terhadap rekonsiliasi dengan
2, 3, 4 1, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 3, 4 1, 4 4 1, 2, 3, 4
87
Stilistik
Retoris
akibat jika rekonsiliasi tidak diwujudkan.
Kata ganti
Merujuk kepada pihak-pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965. Leksikon
Mengiaskan peristiwa dan para pelaku pembantaian massal pasca-G30S 1965 yang begitu kejam dan sadis.
Grafis Pentingnya rekonsiliasi. Betapa kelamnya peristiwa
pembantaian massal pasca-G30S 1965.
Metafora
Mengiaskan tindakan sadis yang dilakukan para pelaku pembantaian massal pasca-G30S 1965.
Ekspresi
Mendukung rekonsiliasi. Menentang peristiwa
pembantaian massal pasca-G30S 1965.
3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 4 3, 4
Dari tabel kesimpulan tersebut, dapat kita lihat bahwa Majalah Tempo ingin
menyampaikan bahwa kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965 sudah sangat lama
88
terlantar dan belum diselesaikan hingga sekarang. Hal tersebut terbukti dari latar waktu
yang diambil oleh Majalah Tempo, yang mengesankan waktu yang begitu lama /
panjang.
Kasus yang sudah terlantar begitu lama ini, bagi Majalah Tempo, tidak dapat
dilupakan atau diabaikan begitu saja karena tragedi pembantaian massal pasca-G30S
1965 ini merupakan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang begitu sadis dan
kejam. Hal tersebut terbukti dari, skema (teras), semantik (detail dan nominalisasi),
stilistik (leksikon), dan retoris (grafis, metafora, dan ekspresi) yang menggambarkan
betap kejam, sadis, dan tidak manusiawinya tindakan yang dilakukan oleh para pelaku
pembantaian massal pasca-G30S 1965 itu.
Para pelaku dan pihak-pihak yang seharusnya dapat dimintai
pertanggungjawaban pun sudah dipaparkan oleh Majalah Tempo dalam edisi ini.
Pemaparan tersebut dapat dilihat dari semantik (detail) dan sintaksis (kata ganti) yang
dengan cukup eksplisit menunjukkan pihak-pihak mana saja yang terlibat dan dapat
dimintai pertanggungjawabannya.
Majalah Tempo melihat bahwa pemerintah kurang serius dalam menyelesaikan
kasus ini. Hal tersebut disampaikan melalui semantik (maksud) dan sintaksis
(koherensi), yang memaparkan akibat-akibat yang akan muncul jika rekonsiliasi tidak
segera diwujudkan.
Rekonsiliasi sendiri, sebagai wacana utama dari edisi khusus Majalah Tempo
kali ini, disampaikan melalui hampir semua bagian, baik dari struktur makro,
superstruktur dan struktur mikro. Struktur makro berupa tematik, mengangkat topik
bahwa rekonsiliasi harus dimulai dari pengakuan para pelaku pembantaian massal
89
pasca-G30S 1965. Kemudian di tingkat superstruktur, pada judul, teras, dan cerita,
mengedepankan pentingnya rekonsiliasi. Dan pada tingkat struktur mikro, pada unsur
semantik (pra-anggapan dan nominalisasi), sintaksis (bentuk kalimat), dan retoris
(grafis dan ekspresi), berulang kali disampaikan dukungan, manfaat, serta pentingnya
rekonsiliasi.
Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam edisi khusus ini, Majalah
Tempo menyampaikan pentingnya rekonsiliasi dari kasus pembantaian massal pasca-
G30S 1965 yang merupakan tragedi pelanggaran berat hak asasi manusia itu dari
struktur makro yaitu tematik dan superstruktur yaitu skema, pada bagian cerita (story).
4.3 Pembahasan
Dari hasil analisis teks di atas, penulis mendapatkan dua tema besar yang ingin
disampaikan oleh Majalah Tempo. Pertama adalah Majalah Tempo ingin mengesankan
bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian massal
pasca-G30S 1965 itu, karena peristiwa itu adalah tragedi pelanggaran hak asasi
manusia yang luar biasa sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja. Kedua adalah
wacana rekonsiliasi yang ingin ditawarkan Majalah Tempo sebagai solusi dari
penyelesaian kasus ini.
Kesimpulan penulis bahwa Majalah Tempo mengesankan bahwa harus ada
pihak yang bertanggung jawab atas tragedi pembantaian pasca-G30S 1965 itu,
diperkuat oleh kesimpulan Randy Hernando (2013: 324) yang menyimpulkan,
"Dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa majalah Tempo menggambarkan tentara sebagai representasi negara menjadi pihak yang memiliki peranan besar dalam
90
pembantaian massal pascagerakan G-30-S. Pihak tentara melakukan propaganda dan pemanfaatan isu agama serta ancaman terhadap negara menjadi cara ampuh menggerakan massa untuk bersama menumpas PKI."
Kesan yang disampaikan Majalah Tempo bahwa peristiwa pembantaian massal
pasca-G30S 1965 itu adalah tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa
sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja juga dapat kita lihat dari beberapa hasil
analisis, seperti beberapa nominalisasi dari kata "pembunuhan" dan "pembantaian",
leksikon "bergajul", "dihabisi", dan "garis komando", metafora "relung-relung gelap",
serta ekspresi "mimpi buruk" dan "amat sangat menyakitkan".
Dari kesimpulan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam artikelnya, selain
mengesankan bahwa peristiwa pembantaian massal pasca-G30S 1965 itu adalah tragedi
pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa sehingga tidak dapat diabaikan begitu
saja, Majalah Tempo juga memaparkan bukti-bukti keterlibatan tentara dan pihak-pihak
lain yang terlibat, namun Majalah Tempo tidak mau menuduh atau memaksa pihak-
pihak tersebut untuk mengaku.
Selanjutnya adalah wacana rekonsiliasi yang ingin ditawarkan Majalah Tempo
sebagai solusi dari penyelesaian kasus ini. Wacana rekonsiliasi disampaikan oleh
Majalah Tempo dalam edisi ini dengan cukup terbuka / eksplisit. Dari hasil wawancara
penulis dengan Majalah Tempo, Seno Joko Suyono selaku penanggung jawab edisi
khusus tersebut mengatakan, "Dalam menerbitkan edisi itu memang terbayang
rekonsiliasi itu, menurut kami salah satu upaya rekonsiliasi diperlukan keterbukaan dari
kedua belah pihak." Berangkat dari pernyataan itu, dapat diketahui bahwa memang
Majalah Tempo mewacanakan Rekonsiliasi dalam edisi khusus 1-7 Oktober 2012
tersebut.
91
Wacana rekonsiliasi itu sendiri Majalah Tempo sajikan hampir dalam setiap
unsurnya, mulai dari struktur makro (tematik) yang mengangkat tema bahwa
rekonsiliasi harus dimulai dari pengakuan, superstruktur (judul, teras, dan cerita) yang
mengedepankan pentingnya rekonsiliasi, hingga tingkat struktur mikro, pada unsur
semantik (pra-anggapan dan nominalisasi), sintaksis (bentuk kalimat), dan retoris
(grafis dan ekspresi) yang memberikan dukungan terhadap wacana rekonsiliasi
tersebut.
Jadi, untuk tingkat analisis teks, Majalah Tempo menjabarkan pelanggaran berat
hak asasi manusia yang terjadi pada kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965 dan
mengedepankan unsur rekonsiliasinya melalui struktur makro (tematik) dan
superstruktur (cerita).
Dari segi kognisi sosial, Majalah Tempo mengaku kredibel dan tidak berpihak.
Majalah Tempo juga benar-benar menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Hal tersebut
diperkuat oleh Kurniawan, Kepala Proyek edisi khusus ini, yang menyatakan bahwa
Majalah Tempo menjunjung tinggi kebenaran secara jurnalistik. Lebih jauh Kurniawan
menjelaskan, semua artikel yang dipublikasikan sudah menjalani prosedur jurnalistik
yang benar, seperti memverifikasi kebenaran data, menghormati hak off the record
narasumber, dan lainnya. "Kebenaran secara jurnalistik ya. Kadang-kadang kita
dituntut juga untuk membuat sebuah kebenaran yang mutlak, saya kira bukan, jadi yang
bisa kita temukan ya sejauh yang bisa kita lakukan sebagai seorang jurnalis," tutur
Kurniawan.
92
Tentang Majalah Tempo, Asvi Warman Adam berpendapat,
"Saya melihat Tempo sudah menjaga kredibilitasnya, buktinya ketika pemimpinnya Wahyu Muryadi ada nuansa politik di dalamnya dan ia terlibat, ia diganti, digeser kedudukannya, sekarang Arif Zulkifli. Tempo cukup kritis terhadap kalangan mereka sendiri kalau tidak kredibel. Saya juga justru menghargai Tempo yang sangat berani karena Tempo-lah yang mencoba menampilkan kekhasannya itu dengan liputan khusus."
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Seno,
"Kita adalah majalah yang jelas-jelas tidak bertolak dari ideologi mana pun, apakah itu kiri, apakah itu Islam, yang jelas kita bekerja sebagaimana sebuah majalah bekerja, yang berada di antara kedua belah pihak, cover both side, saya kira kerja wartawan investigasi atau majalah pada umumnya begitu."
Seno menambahkan bahwa tim yang bekerja dalam proses pembuatan edisi ini,
semuanya adalah anak muda, lahir antara tahun 1970 hingga 1980, sehingga tidak ada
dari mereka yang terlibat dalam peristiwa pembantaian massal pasca-G30S 1965 itu,
dan itu menjadi keuntungan bagi mereka karena dapat menjaga jarak dengan
narasumber, sehingga berita yang dihasilkan tetap netral. "Seluruh wartawan yang
bekerja di dalam edisi khusus itu lahir tahun 70-80an, jadi kami sama sekali tidak
pernah terlibat dalam hal-hal itu dan menurut kami justru itu kekuatannya ya, kami
mengambil jarak dari peristiwa itu," jelas Seno.
Diawali dengan ketertarikan redaksi Majalah Tempo dengan resensi film Jagal
atau The Act of Killing buatan sutradara Joshua Oppenheimer, yang ditulis oleh Ariel
Heryanto, Majalah Tempo mengembangkannya menjadi edisi khusus dan mencoba
sudut pandang yang baru, yaitu dari sisi pelaku, di mana mereka mencari orang-orang
seperti Anwar yang mau mengakui perbuatannya.
93
Seno mengatakan, tim edisi khusus ini menemukan kejutan yang tidak mereka
duga. Dalam bayangan mereka, akan sangat sulit menemukan orang yang mau
mengakui perbuatannya, namun fakta di lapangan berkata lain.
"Kendalanya paling pembagian di lapangan, bahkan banyak menemukan surprise dengan menemukan betapa mudahnya orang mengaku. Justru dalam bayangan kami akan sulit sekali menemukan orang-orang yang mau mengaku, tapi ini malah ketemu, ngaku, dan dengan bangga bercerita mengalir, dan mau direkam, itu malah membuat kami surprise, dan menganggap perbuatan itu adalah suatu bentuk bela negara, mereka tetap tidak merasa bersalah, makanya dengan bangga mereka ceritakan, dan kita rekam mau, dan kita foto mau."
Selain wacana rekonsiliasi, Kurniawan mengatakan bahwa melalui edisi ini,
Majalah Tempo juga ingin mengungkapkan sejarah yang selama ini ditutup-tutupi.
Kendati demikian, rekonsiliasi tetaplah menjadi fokus utama mereka, karena menurut
Majalah Tempo, rekonsiliasi ini penting bagi Bangsa Indonesia, dari pelurusan sejarah,
pemulihan korban, serta nasib generasi penerusnya.
Meski mengaku netral dan tidak berpihak, penulis melihat Majalah Tempo tetap
memiliki kepentingan dan keberpihakan. Majalah Tempo memiliki kepentingan untuk
menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus
tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini. Majalah Tempo juga berpihak
kepada para korban yang telah dilanggar hak asasinya sebagai manusia. Majalah
Tempo mewujudkan keberpihakannya ini melalui wacana rekonsiliasi tersebut.
Kesungguhan Majalah Tempo dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di
Indonesia, serta kepedulian Majalah Tempo terhadap rekonsiliasi ini tidak hanya dapat
kita lihat dalam edisi khusus ini. Hal tersebut dapat kita lihat dengan diraihnya
penghargaan Yap Thiam Hien Award 2012 oleh Majalah Tempo. Ketua Yayasan Yap
94
Thiam Hien, Todung Mulya Lubis (dalam situs http://tinyurl.com/mqynwhj)
mengatakan,
"Tempo telah berada di garis depan dalam pemberitaan hak asasi manusia sepanjang sejarah terbitnya Tempo yang juga pernah dibredel oleh rejim Orde Baru. Tak satu pun berita pelanggaran hak asasi manusia yang luput dari pemberitaan Tempo, sehingga membuat rakyat mengetahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia ternyata tak pernah berhenti."
Untuk ke depannya, setelah edisi khusus ini, Majalah Tempo juga masih setia
dalam mewacanakan rekonsiliasi atau yang berkaitan dengan penegakan hak asasi
manusia, hal tersebut diungkapkan Kurniawan, "Sejauh ini kita masih memikirkan
terus, seperti yang barusan September (2013) lalu kita menerbitkan Lekra kan, itu
berkaitan juga dengan rangka rekonsiliasi."
Majalah Tempo menganggap rekonsiliasi penting untuk menyelesaikan kasus
pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini sehingga mengangkatnya sebagai wacana.
Wacana rekonsiliasi ini Majalah Tempo angkat dengan tetap menjunjung tinggi kode
etik jurnalistik, terbukti dengan para wartawan yang menjaga jarak dengan narasumber
dan menghargai hak-hak off the record narasumber.
Keterbatasan space dan halaman, tentu membuat semua media cetak, termasuk
Majalah Tempo, untuk sangat selektif dalam menentukan isi media mereka. Tidak
mungkin semua tulisan dari sembarang orang mereka muat dalam media cetak mereka.
Oleh karena itu, hanya tulisan dari orang-orang tertentu yang mempunyai akses lah
yang dapat dimuat oleh sebuah media cetak, termasuk Majalah Tempo.
Akses itu Majalah Tempo berikan kepada orang-orang yang mendukung
kepentingan mereka. Salah satunya adalah akses yang diberikan kepada M. Imam Aziz,
seorang yang aktif dalam upaya rekonsiliasi tragedi politik 1965. Akses tersebut
95
diwujudkan dengan dimuatnya buah pemikiran M. Imam Aziz berupa artikel Jalan
Lain Penyelesaian Tragedi 1965.
Jadi, untuk tingkat kognisi sosial, dapat disimpulkan bahwa meski Majalah
Tempo menyatakan mereka tidak memihak siapa pun, dalam praktiknya, Majalah
Tempo tetap berpihak dan memiliki kepentingan. Mereka berkepentingan untuk
menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, dan berpihak pada para korban yang telah
dilanggar hak asasinya.
Dengan power yang dimiliki Majalah Tempo untuk menentukan sendiri isi dari
majalahnya, mereka mewacanakan rekonsiliasi dalam edisi khusus ini. Majalah Tempo
juga mencari dukungan dengan memberikan akses kepada orang-orang yang juga
memiliki kepentingan dan keberpihakan yang sama dengan Majalah Tempo, berupa
memuat tulisan-tulisan dari orang-orang tersebut dalam edisi khususnya kali ini.
Pada tingkat analisis sosial, harus dimulai dari sosio-kultural masyarakat
Indonesia pada saat itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asvi Warman Adam,
seorang sejarawan Indonesia, diketahui bahwa pada saat itu awal permasalahannya
adalah masalah tanah. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendukung pemerintah yang
mengeluarkan peraturan tentang batas kepemilikan tanah seseorang.
PKI melakukan "aksi sepihak", di mana mereka mengambil paksa tanah-tanah
milik orang-orang kaya yang melebihi batas yang sudah ditentukan. Namun pemilik
tanah pun tidak tinggal diam, mereka menyumbangkan tanah itu kepada pesantren,
Kiai, dan sebagainya, sehingga seakan-akan PKI merampas tanah tersebut dari Kiai
atau pesantren, sehingga PKI dicap negatif oleh masyarakat, terutama kaum Muslim
yang merupakan agama mayoritas di Indonesia.
96
Sebenarnya, tidak ada hubungan antara komunisme dengan atheisme.
Komunisme sendiri hanyalah paham atau ideologi di mana menginginkan kondisi sosial
masyarakat yang setara atau tanpa kelas. Asvi mengatakan,
"Kalau kita bicara tentang ajaran apapun yang berkembang dari Eropa memang tidak dikaitkan dengan agama, apakah itu marxisme, liberalisme, tapi saya mengatakan bahwa tidak berarti mereka itu atheis, tidak berarti mereka tidak ber-Tuhan, atau anti Tuhan, mereka tidak mengaitkan ideologi itu dengan agama. Tetapi di sini ditafsirkan atau sengaja dibuat bahwa karena mereka tidak berkaitan dengan agama, mereka itu tidak beragama, mereka itu tidak ber-Tuhan, tidak mengakui Tuhan."
Menurut Asvi, secara kebetulan, mayoritas anggota PKI adalah kaum abangan
yang kurang taat beribadah, bukan kaum santri yang memang taat beribadah. Melihat
celah itu, menjelang pemilu tahun 1955, pada Bulan Desember 1954, Masyumi untuk
pertama kalinya mengeluarkan fatwah bahwa atheisme itu artinya orang yang tidak ber-
Tuhan, dan tidak ber-Tuhan itu sama dengan kafir, dan kafir itu orang yang boleh
diberangi. Dihembuskan pula bahwa orang-orang PKI yang tidak taat beragama itu
adalah atheis, tidak ber-Tuhan. Jadi, pemahaman masyarakat yang salah tentang PKI
dimulai dari sana.
Pemahaman yang salah itu terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia
hingga meletusnya tragedi G30S 1965. Menurut Asvi, setidaknya ada tiga pihak yang
terlibat dalam peristiwa mengenaskan tersebut, yaitu PKI, faktor asing seperti CIA dan
dinas rahasia Inggris, serta Angkatan Darat. Posisi yang diuntungkan adalah Angkatan
Darat, di mana situasi dan kondisi masyarakat sedang kacau, Angkatan Darat lah yang
muncul sebagai pahlawan dengan berusaha mengamankan keadaan.
Soeharto melihat celah itu, Ia segera menjadikan PKI-saingan beratnya untuk
mendapatkan kekuasaan sebagai kambing hitam, dengan menuduh PKI lah yang
97
melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh jenderal tersebut. Tuduhan
tersebut ia sampaikan kepada masyarakat melalui rekaman pidatonya di Radio
Republik Indonesia (RRI). Dengan tentara Angkatan Darat yang dimilikinya, Soeharto
mulai mengajak masyarakat untuk bergerak menumpas orang-orang yang terindikasi
sebagai PKI atau mempunyai hubungan dengan PKI (Lesmana, 2005: 8-10).
Penggunaan kekuatan Angkatan Darat ini, sebagai "alat" untuk menumpas
orang-orang yang terindikasi sebagai PKI atau mempunyai hubungan dengan PKI
tersebut, adalah suatu bentuk penggunaan Repressive State Apparatus oleh pemegang
kekuasaan (Soeharto).
Akumulasi dari kebencian soal masalah tanah yang dirampas oleh PKI,
pelarangan film-film barat oleh PKI yang membuat bioskop sepi sehingga
menghilangkan pencarian nafkah dari Anwar Congo dan teman-temannya, membuat
masyarakat membenci PKI, dan dengan didukung oleh fatwah Masyumi yang
menyatakan bahwa orang kafir itu orang yang boleh diberangi, masyarakat mulai turut
membantu Angkatan Darat membantai orang-orang yang dituduh PKI.
Tragedi berdarah pasca-G30S 1965 ini terus berlangsung hingga sekitar awal
tahun 1966, sampai Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret (supersemar) dari
Soekarno. Sehari setelah itu, pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto mengumumkan
pembubaran PKI serta ormas-ormasnya, disertai dengan unjuk kekuatan oleh Angkatan
Darat di Jakarta, sehingga masyarakat merasa aman dan mendukung Soeharto, hingga
akhirnya Soeharto berhasil naik ke puncak kekuasaan dengan menjadi Presiden
Republik Indonesia yang kedua.
98
Pasca-G30S 1965, stigma bahwa PKI adalah atheis terus dipelihara oleh
Soeharto demi kepentingan politiknya. Asvi menambahkan,
"Saya menganggap PKI ini bukan hanya dianggap sebagai lawan atau musuh politik, tetapi juga untuk kepentingan lain, sebagai alat pemukul politik. Ini dipelihara sehingga orang yang bukan PKI, yang kritis terhadap pemerintah, itu nanti kan gampang, di cap PKI gitu. Yang kedua ini untuk keperluan praktis, untuk membeli tanah dengan harga murah, kalau mereka tidak mau, nanti di cap PKI gitu."
Label itu berhasil merasuk ke dalam benak masyarakat sehingga mereka
membenci PKI. Selama orde baru, Soeharto berhasil mempertahankan stigma tersebut
dengan hanya boleh mengizinkan satu versi tentang peristiwa pembantaian massal
pasca-G30S, sekaligus melarang versi lain untuk dipublikasikan dalam bentuk apa pun.
Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pun masih sangat terbatas, sehingga
mereka mau tidak mau harus percaya dengan satu-satunya sumber yang mereka
dapatkan, yaitu pemerintah.
Soeharto menggunakan ideological state apparatuses untuk mempertahankan
stigma buruk terhadap PKI tersebut. Ideological state apparatuses yang turut berperan
di dalamnya pada saat itu cukup banyak, terutama sekolah, departemen-departemen
pemerintahan, peraturan dan undang-undang, serta media massa.
Kekuasaan penuh terus berada di tangan Soeharto hingga akhirnya pada tahun
1998 generasi muda melakukan aksi reformasi dan meruntuhkan rezim orde baru.
Indonesia telah kembali kepada ideologi demokratisnya di mana kekuasaan tertinggi
ada di tangan rakyat.
Runtuhnya rezim orde baru tidak membuat kasus pembantaian massal pasca-
G30S selesai begitu saja. Stigma yang terpelihara selama lebih dari 30 tahun ini sulit
dihilangkan dari masyarakat. Saat ini, masyarakat setidaknya dapat dibagi menjadi dua
99
kelompok, yaitu para pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam peristiwa
pembantaian massal pasca-G30S 1965 dan generasi muda. Untuk orang-orang yang
terlibat dalam tragedi berdarah itu, Asvi Warman Adam menjelaskan,
"Mereka yang dahulu terlibat dalam peristiwa itu sebagai pelaku, mereka tentu tidak berubah pandangannya, soalnya kalo mereka merubah pandangannya mereka akan disalahkan, jadi mereka tidak akan merubah pandangan atau perspektifnya, versinya kan yang memberontak PKI, karena mereka pemberontak maka bisa diperlakukan apa saja. Jadi ini untuk memberikan legitimasi, justifikasi terhadap apa yang mereka lakukan, jadi orang-orang itu tidak berubah pandangannya sampai sekarang."
Berbeda dengan generasi muda, saat ini akses informasi sudah begitu luas, mudah, dan
tidak terbatas, sehingga para generasi muda sudah mulai lepas dari doktrin ideological
state apparatuses yang mengatakan bahwa PKI itu adalah dalang tragedi pasca-G30S
1965 itu.
Sekalipun saat ini kekuasaan (power) memang masih ada di tangan pemerintah,
namun dengan kemudahan akses yang ada saat ini, masyarakat dapat dengan mudah
mengawasi dan mengkritik pemerintah. Namun, meski masyarakat dapat mengawasi
serta mengkritik pemerintah, hal tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah
tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965 secara tuntas.
Untuk menuntaskan masalah tersebut, harus diawali dari pengakuan. Selain
pengakuan dari para pelaku di tingkat mikro, pemerintah pada tingkat makro juga
seharusnya bisa memulainya dengan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam
kasus pembunuhan massal pasca-G30S 1965 tersebut, dan menyampaikan permintaan
maaf secara terbuka kepada keluarga para korban.
Sayangnya menurut Asvi, tidak ada niatan dari pemerintah untuk menyelesaikan
masalah ini hingga tuntas. Masalah ini hanya akan selesai dengan tuntas apabila semua
100
pihak yang terlibat mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada para korban,
terutama pemerintah.
Jadi, melihat pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan kasus pembantaian
massal pasca-G30S 1965 ini, Majalah Tempo merasa perlu mewacanakan rekonsiliasi
dengan mengesankan bahwa tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965 itu
bukanlah sekadar kasus biasa yang bisa dilupakan begitu saja, serta memaparkan bukti-
bukti adanya pihak-pihak yang terlibat yang seharusnya dapat dimintai
pertanggungjawaban-tanpa memihak, menuduh, atau merugikan mereka. Majalah
Tempo menyampaikan kepada pembacanya bahwa rekonsiliasi itu sangat penting,
karena kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini tidak akan selesai dengan tuntas
hanya dengan tumbangnya rezim orde baru serta kemudahan akses dan keterbukaan
informasi yang dinikmati oleh masyarakat sekarang ini.
4.3.1 Rekonsiliasi Mikro
Runtuhnya rezim orde baru, membuat tragedi pembantaian massal
pasca-G30S 1965 terangkat kembali. Banyak orang-orang baik korban, pelaku,
maupun saksi dari peristiwa itu yang mulai berani berbicara memberikan
kesaksiannya. Hal itu terbukti dari banyaknya buku-buku yang terbit untuk
menceritakan peristiwa pembantaian massal tersebut dari berbagai perspektif
yang berbeda. Munculnya berbagai versi tentang peristiwa naas tersebut
membuat banyak misteri sejarah Bangsa Indonesia yang mulai terungkap.
Meski lubang sejarah sudah tertutup, kasus ini tidak lantas selesai begitu
saja. "Sebenarnya terkadang dalam diriku tumbuh juga perasaan sedih, pedih,
101
perih, apalagi saat menghadiri acara ulang tahun teman. Aku merasa iri dan
sedih karena sejak kecil aku tidak merasakan akan betapa indahnya kasih
sayang bapak" (Proletariyati, 2002: 23). Ungkapan itu mewakili berjuta
kesedihan lain dari para keluarga korban tragedi pembantaian massal pasca-
G30S 1965.
Masih tersisanya begitu banyak luka bagi para korban, membuat kasus
pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini tidak dapat dilupakan begitu saja.
Masalah ini harus diselesaikan hingga tuntas. Langkah pertama yang dapat
dilakukan adalah dengan diadakannya rekonsiliasi pada tingkat mikro atau
horizontal, yaitu rekonsiliasi antara individu pelaku dan korban dari kasus
pembantaian massal pasca-G30S 1965.
Rekonsiliasi pada tingkat ini sudah mulai berjalan di Indonesia.
Contohnya adalah dari artikel kedua yang penulis teliti, grafis berupa kutipan
yang menuliskan kalimat pengakuan dari seorang yang terlibat dalam
pembunuhan orang-orang PKI, Ahmad Bantam, yang sudah bersedia mengakui
kesalahan dan perbuatannya kepada keluarga korban. Hal tersebut secara
langsung memberikan dampak positif bagi korban, di mana keluarga korban
menyatakan kelegaannya karena fakta kebenaran telah terungkap.
Kalangan pemuda Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi yang dahulu juga
ikut andil dalam membantai orang-orang yang dituduh PKI, juga sudah memulai
langkah rekonsiliasi dengan para korban. Dalam wawancaran,Asvi menjelaskan
bahwa rekonsiliasi kalangan muda NU itu dimulai dari kota Yogyakarta,
102
kemudian mereka melebarkannya ke Jawa Tengah, dan kemudian di seluruh
Pulau Jawa.
Langkah serius untuk mewujudkan rekonsiliasi di tingkat mikro ini, juga
ditunjukkan oleh anak-anak dari para tokoh yang terlibat dalam kasus
pembantaian massal pasca-G30S 1965, baik sebagai korban maupun pelaku.
Sejumlah nama, seperti Agus Widjojo, putra Mayjen Sutojo Siswomiharjo,
Amelia A. Yani, putri JenderaL TNI Ahmad Yani, Ilham Aidit, putra D. N.
Aidit, Salomo Pandjaitan, putra D.I. Pandjaitan, Jaya Senjaya, putra Senjaya,
Mantan Panglima DI/TII, Moh. Basyir, cucu H.O.S. Tjokroaminoto, dan
lainnya, sudah mulai menjalin silaturahmi dalam Forum Silaturahmi Anak
Bangsa (FSAB). (http://tinyurl.com/le3tfvr)
Forum Silaturahmi Anak Bangsa berdiri tanggal 25 Mei 2003, didirikan
dengan tujuan untuk mewujudkan rekonsiliasi di tingkat mikro antara korban
dan pelaku pembantaian massal pasca-G30S 1965. FSAB memiliki moto,
"berhenti mewariskan konflik, tidak membuat konflik baru!" Moto tersebut
merupakan keinginan mereka untuk menyudahi konflik yang terjadi pada para
generasi pendahulu mereka, serta semangat untuk memajukan Indonesia,
dengan tidak membuat konflik baru, atau dendam yang berkelanjutan.
Para anggota FSAB berpandangan bahwa mereka sebagai anak-anak
dari orang-orang yang berkonflik pada masa lalu, tidak harus mewarisi dendam
orangtua mereka. Selain itu, mereka sendiri pun juga tidak terlibat dalam
peristiwa berdarah itu, sehingga jika mereka tetap menyimpan dendam, mereka
pun mendendam kepada orang yang salah, yang sama sekali tidak terlibat dalam
103
peristiwa itu. Oleh karena itu, dari pihak anak-anak para korban, mereka
berusaha untuk bersedia membukakan pintu maaf bagi para pelaku yang terlibat
dalam tragedi tersebut, sebaliknya dari pihak anak-anak para pelaku, mereka
dengan besar hati, atas nama orangtua mereka, mengakui kesalahan orangtua
mereka dan meminta maaf.
Dalam edisi khusus ini, Majalah Tempo mewacanakan rekonsiliasi
tingkat mikro dengan memaparkan sejumlah contoh para pelaku dari berbagai
daerah yang bersedia untuk mengakui dan meminta maaf kepada para keluarga
korban yang dahulu mereka bunuh. Contoh tersebut dapat menjadi panutan bagi
para pelaku lain agar menyadari perbuatan sadis dan kejam yang telah mereka
lakukan, dan mau mengakui dan meminta maaf kepada para korban.
Rekonsiliasi yang sudah dan masih berjalan di masyarakat tingkat mikro
secara horizontal ini sudah cukup baik. Masyarakat secara perlahan sudah mulai
mau menerima kembali orang-orang yang dahulu pernah dituduh sebagai PKI
atau memiliki hubungan dengan PKI dalam masyarakat. Berangsur-angsur,
sinisme masyarakat terhadap orang-orang itu sudah tidak terasa lagi. Orang-
orang yang pernah menjadi korban dari tragedi pembantaian massal pasca-G30S
1965 itu sudah mulai dapat menjalani hidup normal dalam masyarakat, tanpa
perlu takut atau merasa dikucilkan.
4.3.2 Rekonsiliasi Makro
Selama rezim orde baru, stigma bahwa PKI itu adalah dalang dari G30S
1965 terus dipelihara oleh Soeharto dengan ideological state apparatuses
104
berupa sekolah, departemen-departemen pemerintahan, peraturan dan undang-
undang, serta media massa. Stigma tersebut digunakan untuk memukul
lawan politiknya dan untuk menekan masyarakat. Orang-orang yang menentang
atau mengkritik Soeharto akan dituduh PKI dan orang-orang yang tidak mau
menyerahkan tanahnya (atau harta lainnya) kepada negara, juga dituduh PKI.
Oleh sebab itu, rekonsiliasi adalah hal yang mustahil pada saat itu.
Stigma negatif yang melekat pada PKI selama itu, tentu tidak mudah
hilang dari masyarakat begitu saja, sehingga, meski rezim orde baru akhirnya
telah runtuh, pandangan masyarakat terhadap PKI masih sama, hingga akhirnya
banyak orang-orang baik dari pelaku, korban, maupun saksi dari peristiwa
pembantaian massal pasca-G30S 1965 itu yang mau bersuara dan mengutarakan
kesaksiannya, terutama melalui buku.
Banyaknya fakta-fakta baru tentang kasus pembantaian massal pasca-
G30S 1965 tersebut menguatkan bukti bahwa PKI hanyalah kambing hitam,
sedangkan yang seharusnya bertanggung jawab ialah Soeharto dan Angkatan
Daratnya (Repressive State Apparatus) saat itu. Oleh sebab itu, meski pemegang
kekuasaan telah berganti, pemerintah tetap memikul tanggung jawab penuh
untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.
Rekonsiliasi secara vertikal di tingkat makro ini berguna untuk
mengembalikan hak-hak para keluarga korban dari tragedi pembantaian massal
pasca-G30S 1965 ini sebagai warga Negara Indonesia yang seutuhnya. Hak-hak
tersebut antara lain, penghapusan tanda-tanda atau kode-kode khusus di Kartu
Tanda Penduduk (KTP) mereka (sudah dilakukan oleh MK pada tahun 2004),
105
memberikan mereka hak pilih dalam pemilu, memberi mereka kesempatan yang
sama dalam berkarya dalam bidang apapun (ekonomi, politik, dll),
mengembalikan hak pensiun mereka, serta mengembalikan nama baik mereka
dan keluarganya.
Ada dua usaha rekonsiliasi pada tingkat makro yang pernah diupayakan
oleh pemerintah, meski belum berhasil. Usaha pertama adalah Presiden
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang meminta maaf kepada para korban atas
pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Banser NU pasca-G30S 1965, namun
ditentang oleh sejumlah pihak. Salah satu pihak yang menentang adalah
Pramoedya Ananta Toer. Dalam wawancara, Asvi bercerita, "Pram mengatakan
bahwa Gus Dur tidak merasakan sakitnya sebagai korban." Sejumlah ulama NU
pun bahkan menyesalkan tindakan Gus Dur yang meminta maaf kepada para
korban tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965.
Usaha kedua adalah diusulkannya pembentukan Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2004. Memang KKR bukan hanya dikhususkan
untuk menyelesaikan kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965 saja, tetapi
kasus tersebut merupakan salah satu perhatian utama komisi itu. Namun sayang,
komisi itu sudah dibubarkan kembali oleh MK pada tahun 2006 dengan alasan
tidak ada rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
Orde baru sudah berakhir 16 tahun yang lalu, namun rekonsiliasi secara
vertikal di tingkat makro, belum juga terwujud. Tidak ada niat dari pemerintah
untuk menuntaskan kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini. Asvi
mengungkapkan,
106
"bukan kurang serius, tidak mau! Artinya, karena sudah berapa kali sudah disampaikan berkasnya yang 65 itu, demikian juga dengan Mahkamah Agung, keputusannya sudah ada, kenapa tidak di sahkan gitu. Mungkin mereka harus didemo dulu baru bisa."
Majalah Tempo juga mewacanakan rekonsiliasi di tingkat makro dengan
memaparkan berbagai cara yang dapat pemerintah lakukan untuk mewujudkan
rekonsiliasi dalam edisi khusus ini. Cara-cara yang dapat ditempuh antara lain,
pemerintah secara resmi meminta maaf dan mengakui terjadinya pelanggaran
berat hak asasi manusia, meratifikasi Statuta Roma, atau setidaknya, secara
formalitas melakukan pengadilan terhadap para pelaku namun memberi amnesti
kepada mereka.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Proyek Liputan Khusus edisi 1-7
Oktober 2012 ini, Kurniawan, yang menyampaikan,
"Dalam edisi ini kita sudah menyampaikan solusi-solusi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, tinggal kita lihat apakah pemerintah mau melakukannya atau tidak. Yang jelas rekonsiliasi ini penting bagi korban dan pelaku yang masih hidup, dan kita juga gak tau kan bagaimana nasib anak-anak mereka."
Berbeda dengan Majalah Tempo, Asvi Warman Adam lebih
menekankan pada pengadilan kepada para pelaku. Ia menegaskan, "Ini kan
kebijakan Negara, kebijakan pemerintah, jadi tidak ada rekonsiliasi menurut
saya, antara pelaku yang sifatnya vertikal. Menurut saya hanya memberikan
ganti rugi itu kan tidak menyelesaikan persoalan, hukum itu harus ditegakkan."
Asvi berpendapat bahwa rekonsiliasi pada tingkat mikro, secara horizontal,
sudah berjalan dengan cukup baik, namun untuk tingkat makro, secara vertikal,
ia lebih memprioritaskan jalur hukum atau pengadilan. Asvi mengakui, bahwa
sebenarnya pengadilan pun sudah tidak ada gunanya, para pelaku yang sudah
107
uzur pun akan meninggal sebelum waktu penahanannya habis, namun yang ia
utamakan adalah rasa keadilan bagi para korban.
Jadi, dalam edisi khusus 1-7 Oktober 2012 ini, Majalah Tempo mewacanakan
rekonsiliasi pada dua tingkat sekaligus, yaitu tingkat mikro dan makro. Pada tingkat
mikro (horizontal, sesama masyarakat), diperlukan agar tidak ada lagi konflik-konflik
dalam masyarakat, tidak ada lagi dendam, dan kejelasan bagi para keluarga korban
tentang kapan dan di mana keluarga mereka menginggal dan siapa yang membunuhnya.
Sedangkan untuk tingkat makro (vertikal, antara pemerintah dengan masyarakat),
diperlukan untuk mengembalikan hak-hak para korban sebagai warga Negara Indonesia
secara utuh, hak untuk berkarya dalam segala bidang, hak dalam pemilu, pemulihan
nama baik, hingga ganti rugi secara materi jika diperlukan.
108
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Meski sudah 48 tahun berlalu, tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965
masih menyisakan luka bagi Bangsa Indonesia hingga sekarang. Para korban dari
peristiwa naas itu masih belum dipulihkan haknya sebagai warga Negara Indonesia
secara utuh. Trauma masih menghantui pikiran dan perasaan mereka. Masih banyak
pula lubang-lubang sejarah yang masih gelap karena tidak adanya pengakuan dari para
pelaku, atau sudah tidak mungkin terungkap karena sudah tidak ada saksi yang masih
hidup.
Berbagai upaya penyelesaian kasus ini sudah dicoba untuk dilakukan, terutama
pada tingkat masyarakat kecil (mikro), namun hal itu tentu saja belum cukup, karena
harus disertai juga dengan adanya penyelesaian secara keseluruhan pada tingkat yang
lebih tinggi (makro) yaitu pemerintah. Penyelesaian pada tingkat mikro hanya
menyelesaikan masalah personal antara pelaku dan keluarga korban, tidak bisa
menyelesaikan masalah kerugian para keluarga korban yang telah kehilangan harta
benda, nama baik, dan haknya sebagai warga negara, untuk itu diperlukan penyelesaian
masalah secara utuh dari tingkat yang makro.
Penyelesaian masalah dari tragedi pembantaian massal pasca-G30S 1965 ini
adalah dengan cara rekonsiliasi, yaitu pengakuan serta permintaan maaf dari para
109
pelaku. Beberapa upaya yang pernah dilakukan untuk mencapai rekonsiliasi itu adalah
membentuk Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (KKR) dan Presiden Gus Dur yang
meminta maaf kepada para korban. Namun kedua upaya itu belum berhasil karena
KKR dibatalkan dan permintaan maaf Gus Dur tersebut mendapat banyak pertentangan.
Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana dan mengapa Majalah
Tempo mewacanakan rekonsiliasi dalam edisi khusus 1-7 Oktober 2012 berjudul
PENGAKUAN ALGOJO 1965 dengan menggunakan metode analisis wacana kritis
Teun A. van Dijk. Penelitian ini penulis batasi dengan meneliti empat artikel dalam
majalah tersebut yang mewakili empat sudut pandang berbeda, yaitu dari pihak Majalah
Tempo sendiri, pelaku yang mau mengaku dan minta maaf, Joshua Oppenheimer
sutradara film Jagal atau The Act of Killing, dan aktivis.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Majalah Tempo
mengemas wacana rekonsiliasi dalam edisi khususnya ini dengan mengedepankan hal-
hal yang berhubungan dengan rekonsiliasi, seperti kata "pengakuan", "permintaan
maaf", "penyelesaian masalah", dan kata "rekonsiliasi" sendiri dalam kolom Opini-nya
berjudul Dari Pengakuan Algojo 1965.
Majalah Tempo juga menyajikan wacana rekonsiliasinya dalam laporan
utamanya dengan menampilkan para pelaku yang mau mengakui perbuatan dan
kesalahan mereka. Seperti dari artikel Sebuah Pengakuan dari Kerumunan Pohon
Kapuk, kata "pengakuan", "mengaku", "minta maaf", dan "rekonsiliasi" dituliskan
dalam artikel tersebut. Kalimat pengakuan Ahmad Bantam, "Saya beri tahu bahwa
keluargamu bukan hilang, tapi sudah ditembak mati. Saya yang menggali kuburannya.
Sebentar lagi saya meninggal. Saya tidak mau rahasia ini tidak dibuka. Kasihan
keluarga korban" pun ditulis dengan huruf kapital semua dan dicetak besar di tengah-
110
tengah halaman, menunjukkan bahwa Majalah Tempo ingin menekankan pada
pentingnya pengakuan dari para pelaku.
Dari artikelnya yang merupakan hasil wawancara dengan Joshua Oppenheimer,
selain bertanya seputar film yang menjadi pemicu Majalah Tempo dalam membuat
edisi khusus ini, Majalah Tempo menyisipkan satu pertanyaan tentang rekonsiliasi,
yaitu pertanyaan, "setelah melihat bagaimana bangganya para jagal atas tindakan
mereka dulu itu, apakah ada kemungkinan rekonsiliasi antara pelaku dan korban?" Dari
pertanyaan itu penulis menyimpulkan bahwa Majalah Tempo benar-benar
mewacanakan rekonsiliasi dalam edisi khusus ini, dengan meminta pendapat Joshua
Oppenheimer mengenai rekonsiliasi itu.
Majalah Tempo juga mencari dukungan atas wacana rekonsiliasi yang mereka
munculkan di dalam edisi khusus ini dengan memberikan akses kepada para aktivis
yang juga memiliki kepentingan dan keberpihakan yang sama dengan Majalah Tempo,
yaitu mendukung atau mengupayakan terjadinya rekonsiliasi itu. Seperti biografi
singkat M. Imam Aziz yang dituliskan pada bagian kanan atas halaman sebagai orang
yang aktif dalam upaya rekonsiliasi tragedi politik 1965.
Majalah Tempo menganggap bahwa kasus pembantaian massal pasca-G30S 1965
ini merupakan kasus yang begitu sadis dan tragis sehingga tidak bisa diabaikan atau
dilupakan begitu saja. Terbukti, dalam artikel-artikel yang penulis teliti, ditemukan
sejumlah penekanan terhadap betapa mengerikannya peristiwa pembantaian massal
tersebut.
Selain itu, dalam artikel-artikel yang penulis teliti, dipaparkan pula oleh Majalah
Tempo bukti-bukti atau pernyataan-pernyataan tentang siapa yang terlibat atau
seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya tragedi pembantaian massal pasca-G30S
111
1965 itu. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan bahwa rekonsiliasi hanya bisa
dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat atau seharusnya bertanggung jawab mau
mengakui perbuatan dan kejahatan yang telah mereka lakukan.
Jadi, Majalah Tempo menonjolkan wacana rekonsiliasi dalam edisi khusus 1-7
Oktober 2012 ini dalam struktur makro (tematik) dan superstruktur (cerita). Meski
Majalah Tempo mengaku tidak berpihak kepada siapa pun, Majalah Tempo tetap
memiliki kepentingan dan keberpihakan, yaitu kepentingan untuk menuntaskan kasus
pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan berpihak kepada para korban yang
telah dilanggar hak asasinya. Rekonsiliasi di tingkat mikro berguna bagi para korban
agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya, sedangkan
rekonsiliasi di tingkat makro penting untuk mengembalikan hak-hak para korban
sebagai warga negara secara utuh serta meluruskan sejarah Bangsa Indonesia yang
masih gelap dan banyak ditutup-tutupi.
112
5.2 Saran
5.2.1 Saran Akademis
Melalui hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan adalah
penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin
menganalisis topik atau wacana lain dengan metode yang sama.
5.2.2 Saran Praktis
Berdasarkan hasil penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana suatu
media mewacakan suatu hal dalam tulisan-tulisannya. Dengan melihat hasil
penelitian ini, diharapkan dapat mempertajam kepekaan dan kekritisan kita
terhadap wacana-wacana yang dimasukkan suatu media di dalam tulisannya.
113
DAFTAR PUSTAKA
Abdulgani-Knapp, Retnowati. 2007. Soeharto: The Life and Legacy Of Indonesia's
Second President : An Authorised Biography. Singapore: Marshall Cavendish.
Adam, Asvi Warman. 2009. Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan
Peristiwa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
_______. 2010. Bung Karno Dibunuh Tiga Kali? Tragedi Bapak Bangsa Tragedi
Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Alwi, Hasan. 1993. Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
Anderson, Benedict dan Ruth T. McVey. 2009. A Preliminary Analysis of the October
1, 1965: Coup in Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing.
Arifin, E. Zaenal dan Junaiyah H.M. 2010. Keutuhan Wacana. Jakarta: Grasindo.
Aritonang, Jan S. 2004. Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Jakarta:
BPK Gunung Mulia.
Astuti, Tia Agnes.2011. Analisis Wacana Van Dijk Terhadap Berita "Sebuah Kegilaan
di Simpang Kraft". Jakarta: UIN.
Babbie, Earl R. 2008. The Basic Of Social Research, 4th Edition. California: Thomson
Wadsworth.
Bailey, Kenneth D. 2008. Methods of Social Research, 4th Edition. New York: Simon
and Schuster.
Bresnan, John. 2005. Indonesia: The Great Transition. Lanham: Rowman & Littlefield.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
114
Bungin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi. Jakarta: Kencana.
Creswell, J. W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Traditions (2nd Ed). Thousand Oaks: Sage.
Danusubroto, Sidarto. 2013. Hak Asasi Manusia dan Kehidupan Berbangsa. Jakarta:
ELSAM.
Daymon, Christine dan Immy Holloway. 2008. Metode Riset Kualitatif. Yogyakarta:
Bentang.
Dijk, Teun A. van. 1988. News as Discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates Publisher.
Djarot, Eros. 2006. Misteri Supersemar. Jakarta: Mediakita.
_______, dkk. 2006. Siapa Sebenarnya Soeharto: Fakta dan Kesaksian Para Pelaku
Sejarah G-30-S/PKI. Jakarta: Mediakita.
Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: PT
LKiS Pelangi Aksara.
Fairclough, Norman dan Clive Holes. 1995. Critical Discourse Analysis: The Critical
Study of Language. London: Longman.
Fatwa, Andi Mappetahang. 2009. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Foucault, Michael. 2002. Archaeology of Knowledge. London: Routledge.
Fic, Victor M. 2005. Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Fiske, John. 2010. Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling
Komprehensif. Yogyakarta: Jalasutra.
115
Geerken, Horst Henry. 2011. A Magic Gecko: Peran CIA di Balik Jatuhnya Soekarno.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Gulo, W. 2000. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.
Gultom, Binsar. 2010. Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di
Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hadi, Syamsul. 2007. Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan
Dinamika Internasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hamid, Usman dan Sri Suparyati. 2007. " Penghilangan Orang Secara Paksa". Dalam
http://kontras.org/index.php?hal=opini&id=27.
Hernando, Randy. 2013. Konstruksi Realitas Peranan Tentara dalam Pembantaian
Massal Pascagerakan 30 Semptember 1965 . Tangerang: UMN.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2013. Dalam http://kbbi.web.id.
Kasemin, Kasiyanto. 2004. Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan TAP
MPRS/XXV/1966. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.
Kennedy, Emmet. 1979. "Ideology" from Destutt De Tracy to Marx. Dalam Journal of
the History of Ideas. Vol. 40, No. 3. Pennsylvania.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2013. "Penantian Panjang Korban Pelanggaran
HAM". Dalam http://tinyurl.com/lcqcaq9.
Kuntoro. 2008. "Analisis Wacana Kritis (Teori Van Dijk Dalam Kajian Teks Media
Massa)". Dalam Leksika. Vol.2 No.2 –Agustus 2008. Purwokerto.
Latief, Abdul. 2000. Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G 30 S. Jakarta: Institut
Studi Arus Informasi.
Laughey, Dan. 2007. Key Themes in Media Theory. New York: McGraw-Hill.
116
Lesmana, Surya. 2005. Saksi dan Pelaku Gestapu: Pengakuan Para Saksi dan Pelaku
Sejarah Gerakan 30 September 1965. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Linawati, Mevi. 2009. "LIPI: CIA Diduga Dalangi Tragedi PKI". Dalam
http://nasional.inilah.com/read/detail/162856.
Lubis, T. Mulya. 2005. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Luhulima, James. 2006. Menyingkap Dua Hari Tergelap di Tahun 1965: Melihat
Peristiwa G30S Dari Perspektif Lain. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2004. Pulihnya Hak Politik Eks PKI.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Matanasi, Petrik. 2011. Untung, Cakrabirawa, dan G30S. Yogyakarta: Trompet.
McVey, Ruth T. 2006. The Rise of Indonesian Communism. Jakarta: Equinox
Publishing.
Pambudi, A. 2009. Supersemar Palsu. Yogyakarta: Media Pressindo.
Parse, Rosemarie Rizzo. 2001. Qualitative Inquiry: The Path of Sciencing.
Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers.
Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi
Aksara.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional
Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.
Pratama, Sandy Indra. 2006. "Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Dibatalkan". Dalam http://tinyurl.com/ks8wfhs.
117
Proletariyati, Ribka Tjiptaning. 2002. Aku Bangga Jadi Anak PKI. Jakarta: Cipta
Lestari.
Purnomo, Mulyadi Eko. 2011. "AWK Untuk Menemukan Ideologi yang Tersembunyi".
Dalam http://www.unsri.ac.id/?act=info_detil&id=263.
Renkema, Jan. 2004. Introduction to Discourse Studies. Amsterdam: John Benjamins
Publishing Company.
Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta
Suharto. Jakarta: Hasta Mitra.
Sahal, Akhmad. 2000. "Islam, Maaf, dan PKI". Dalam Tempo. 9 April. Jakarta.
Samsudin. 2004. Mengapa G30S/PKI Gagal?: Suatu Analisis. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Schiffrin, Deborah, D. Tannen, dan H. Hamilton. 2001. Handbook of Discourse
Analysis. Oxford: Blackwell.
Semiawan, Conny R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
Sobur, Alex. 2009. Analisis Teks Media. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sophiaan, Manai. 2008. Kehormatan Bagi yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat
G30S/PKI. Jakarta: Visi Media.
Steele, Janet E. 2005. Wars Within: The Story Of Tempo, An Independent Magazine In
Soeharto's Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing.
Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 1997. Grounded Theory in Practice. London: Sage
Publications.
Stubbs, Michael. 1983. Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural
Language. Chicago: The University of Chicago Press.
118
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung:
Alfabeta.
Sujatmoko, Adrey. 2005. Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM.
Jakarta: Grasindo
Sumarwan, Antonius. 2007. Menyeberangi Sungai Air Mata: Kisah Tragis Tapol '65
dan Upaya Rekonsiliasi. Yogyakarta: Kanisius.
Susanto, A. Budi. 2003. Politik dan Postkolonialitas di Indonesia. Yogyakarta:
Kanisius.
Suseno, Frans Magnis. 2005. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke
Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suwandi, Sarwiji. 2008. Serbalinguistik: Mengupas Pelbagai Praktik Berbahasa. Solo:
Universitas Sebelas Maret.
Tempo. 2013. "Sejarah Tempo 1971-2013". Dalam
http://korporat.tempo.co/tentang/sejarah.
Wardaya, F. X. Baskara Tulus. 2009. Membongkar Supersemar! Dari CIA Hingga
Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno. Yogyakarta: Galangpress.
Wengraf, Tom. 2001. Qualitative Research Interviewing. London: Sage Publications.
Wodak, Ruth dan Michael Meyer. 2001. Methods of Critical Discourse Analysis.
London: Sage Publications.
Yayasan Yap Thiam Hien. 2012. Majalah Tempo Raih Yap Thiam Hien Award 2012.
Dalam http://www.yapthiamhien.org/index.php?find=news_detail&id=2.
Zazuli, Mohammad. 2009. 60 Tokoh Dunia Sepanjang Masa. Yogyakarta: Narasi.
Zizeg, Slavoj. 2012. Mapping Ideology. London: Verso.
119
LAMPIRAN
1. ARTIKEL DARI PENGAKUAN ALGOJO 1965
2. ARTIKEL SEBUAH PENGAKUAN DARI KERUMUNAN
POHON KAPUK
3. ARTIKEL JOSHUA OPPENHEIMER: MEMBUNUH, BAGI
ANWAR, ADALAH SEBUAH AKTING
4. ARTIKEL JALAN LAIN PENYELESAIAN TRAGEDI 1965
5. TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN MAJALAH TEMPO
6. TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ASVI WARMAN
ADAM
127
TRANSKRIP WAWANCARA PENULIS DENGAN SENO
JOKO SUYONO DAN KURNIAWAN (REDAKSI
MAJALAH TEMPO)
Penulis (D) : Apakah Tempo memang mewacanakan rekonsiliasi
dalam edisi itu?
Seno (S) : Dalam menerbitkan edisi itu memang terbayang
rekonsiliasi itu, menurut kami salah satu upaya rekonsiliasi
diperlukan keterbukaan dari kedua belah pihak. Jika kita lihat
contoh di Jerman, Afrika, apartheid gitu kan, ada keterbukaan
dari kedua belah pihak. Dengan angle itu kita ingin memasuki
bukan dari sudut korban bagaimana biasa diberitakan, tapi kita
mencoba sedikit angle lain, tapi itu semua demi maksud baik lah,
kita sama-sama terbuka, bukan dengan kemudian ingin
menyudutkan orang, kaum tertentu, saya kira enggak, tapi
dengan niat baik bahwa rekonsiliasi itu diperlukan dan dasarnya
adalah keterbukaan kedua belah pihak.
D : Apa ideologi yang dianut oleh Tempo, atau Tempo
memihak siapa?
S : Kita tidak memihak mana-mana.
Kurniawan (K): Kita tidak punya ideologi deh.
S : Kita adalah majalah yang jelas-jelas tidak bertolak dari
ideologi mana pun, apakah itu kiri, apakah itu Islam, yang jelas
kita bekerja sebagaimana sebuah majalah bekerja, yang berada di
antara kedua belah pihak, cover both side, saya kira kerja
wartawan investigasi atau majalah pada umumnya begitu.
Berbeda kalau sebuah majalah atau media berpihak itu namanya
128
udah partisan, dan itu majalah-majalah atau koran-koran pada
tahun 50-60-an itu banyak yang media partisan, kita sama sekali
tidak. Coba kalau anda lihat laporan-laporan utama Tempo yang
menyikap korupsi itu, hampir semua partai diinvestigasi Tempo,
tidak pernah ada partai yang dilindungi, itu salah satu bukti
bahwa kita netral, kita tidak partisan, tidak mendukung satu
partai pun, bahkan orang dekat pun kalau menurut kami ada
keganjilan juga kami sikat, misalnya Dahlan Iskan, Dahlan Iskan
mantan wartawan Tempo juga, orang jadi cover.
D : Jadi Tempo berpihak pada kebenaran?
K : Kebenaran secara jurnalistik ya. Kadang-kadang kita
dituntut juga untuk membuat sebuah kebenaran yang mutlak,
saya kira bukan, jadi yang bisa kita temukan ya sejauh yang bisa
kita lakukan sebagai seorang jurnalis.
D : Tempo terbit pada tahun 71, sedangkan G30S terjadi
pada tahun 65, adakah hubungan "personal" antara Tempo
dengan peristiwa G30S ini?
S : Seluruh wartawan yang bekerja di dalam edisi khusus itu
lahir tahun 70-80an, jadi kami sama sekali tidak pernah terlibat
dalam hal-hal itu dan menurut kami justru itu kekuatannya ya,
kami mengambil jarak dari peristiwa itu. Jadi yang mengerjakan
edisi khusus itu anak-anak muda semua, yang paling tua
mungkin saya lahir tahun 70, yang lainnya angkatan dari tahun
80an.
D : Saat rapat redaksi, adakah pertentangan diantara internal
Tempo sendiri?
129
S : Kalau pertentangan sih enggak. Kami sudah terbiasa
membuat edisi khusus, rata-rata edisi khusus itu mengupas
sejarah Indonesia, atau tokoh-tokoh Indonesia yang
kontroversial, kami berusaha mencari sisi-sisi yang belum pernah
diungkap oleh media lain, seperti bukunya Aidit dan sebagainya,
itu sudah kami kerjakan selama lima tahun belakangan, dan kami
sudah terbiasa, jadi debat itu adalah bagian dari pencarian angle.
D : Mengapa dalam edisi ini, pendapat dari Adi Prasetyo dan
Imam Aziz yang dimuat?
S : Karena mereka telah melakukan penelitian. Adi Presetyo
dari HAM juga telah melakukan pendataan, misalnya kita dapat
informasi tentang yang di Sumatra, dia telah melakukan
pendataan itu. Sama halnya dia melakukan pendataan tentang
korban-korban petrus, penembakan misterius tahun 70-an, dia
sampai ke korban-korbannya, mewawancarai satu persatu korban
yang masih hidup, yang lolos dari petrus, diwawancarai satu-
persatu.
Jadi yang kami pilih untuk mengisi kolom adalah orang-
orang yang telah bekerja dengan data-data di lapangan. Imam
Aziz juga begitu, dia memiliki LSM NU yang memang misinya
adalah rekonsiliasi itu. Jadi kami dalam memilih penulis kolom
pun juga berusaha memilih orang yang tepat, yang menurut kami
telah melakukan penelitian terhadap tema yang kami angkat.
D : Adakah wacana lain selain rekonsiliasi dalam edisi itu?
K : Mungkin ada, misi pengungkapan sejarah yang selama ini
banyak ditutup-tutupi.
130
D : Selama setahun majalah ini terbit, apa saja dari
masyarakat atau oknum tertentu?
S : Sebenarnya banyak sekali, ada yang pro, ada yang kontra,
sebenarnya bukan hanya pada edisi ini, tapi setiap edisi juga
pasti begitu. Rata-rata komentar yang masuk, kami masukkan
sebagai surat pembaca, walaupun kami edit karena keterbatasan
halaman.
D : Adakah liputan yang sudah dibuat namun tidak
dimasukkan ke dalam edisi khusus ini?
S : Tidak ada, kita bekerja dengan perkiraan halaman, tidak
bekerja ngawur, kita punya outline, jadi sudah sejak awal kita
sudah ditetapkan akan terbit berapa halaman, kita sudah tahu
seperti apa, berapa jatah kita menulis itu sudah tahu.
D : Setelah edisi ini, sudahkah ada rencana untuk
menerbitkan edisi lain yang berkaitan dengan rekonsiliasi G30S
ini?
S : Sejauh ini kita masih memikirkan terus, seperti yang
barusan September lalu kita menerbitkan Lekra kan, itu
berkaitan juga dengan rangka rekonsiliasi. Untuk ke depannya
kita belum memikirkan, perencanaannya mungkin enam bulan
sebelum terbit.
Ide itu pertama-tama datang secara tidak langsung, waktu
itu Ariel Heryanto di Melbourne mengirim resensi film Act of
Killing, dia selama ini telah banyak meneliti film-film Indonesia
yang berkaitan dengan G30S dan PKI, menurut dia ini film yang
paling kontroversial, karena bukan dari sisi korban tapi dari sisi
pelaku. Setelah saya baca, loh ini menarik, kenapa tidak kita
kembangkan menjadi edisi khusus, film ini hanya menjadi satu
131
bagian tertentu, sementara kita mencari pelaku-pelaku dari
daerah-daerah lain, itu ide awalnya dari resensi film Ariel yang
kita kembangkan.
K : Sebelum memulai liputan, kita nonton dulu filmnya, kita
nonton yang versi director's cut, yang versi panjangnya.
D : Selama proses peliputan ini, ada kendala apa saja yang
ada dalam redaksi Tempo sendiri?
S : Kendalanya paling pembagian di lapangan, bahkan kami
banyak menemukan surprise dengan menemukan betapa
mudahnya orang mengaku. Justru dalam bayangan kami akan
sulit sekali menemukan orang-orang yang mau mengaku, tapi ini
malah ketemu, ngaku, dan dengan bangga bercerita mengalir,
dan mau direkam, itu malah membuat kami surprise, dan
menganggap perbuatan itu adalah suatu bentuk bela negara,
mereka tetap tidak merasa bersalah, makanya dengan bangga
mereka ceritakan, dan kita rekam mau, dan kita foto mau. Itu
malah surprise, padahal waktu kita rapat itu kita agak sangsi
apakah kita bisa mendapatkan orang seperti itu, orang yang mau
mengaku membunuh itu, ternyata semua orang yang kita temui
sama dengan yang ada di film itu, senang mengaku, bahkan
secara psikologis kita anak-anak muda yang berjarak dengan
peristiwa itu yang tidak terlibat langsung menjadi kaget. Rata-
rata tidak perlu membujuk susah payah.
K : Itu nama mereka cantumkan utuh-utuh juga gak apa-apa,
tempat tinggal di mana, ga masalah.
S : Kita sudah bekerja dengan prosedur jurnalistik, mana
yang on the record, mana yang off the record, rata-rata on the
record semua. Mereka kami munculkan fotonya, kami
munculkan namanya, kami munculkan lokasi rumahnya, dengan
persetujuan mereka.
132
D : Bagaimana harapan Tempo bagi pembacanya setelah
membaca edisi ini?
S : Kami mengandaikan pembaca Tempo adalah pembaca
yang kritis, pembaca yang mau menerima sejarah yang terbuka,
bukan pembaca yang konservatif, karena kami terbiasa setiap
edisi itu menyajikan hal-hal yang mengungkap sesuatu. Kami
percaya bahwa kelas menengah Indonesia mampu menerima hal-
hal yang dulunya disembunyikan dalam sejarah. Kami melihat
tipe-tipe pembaca Tempo seperti itu, sehingga kami berani
menerbitkan edisi seperti ini. Kami mengandaikan pembaca kami
adalah pembaca yang kritis, yang malah mencari-cari hal-hal
yang selama ini perlu diungkap, mungkin apakah itu korupsi atau
apa pun itu.
D : Menurut Tempo, apakah pemerintah sudah cukup serius
dalam menyelesaikan kasus ini?
K : Dalam edisi ini kita sudah menyampaikan solusi-solusi
yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, tinggal kita lihat
apakah pemerintah mau melakukannya atau tidak. Yang jelas
rekonsiliasi ini penting bagi korban dan pelaku yang masih
hidup, dan kita juga gak tau kan bagaimana nasib anak-anak
mereka.
133
TRANSKRIP WAWANCARA PENULIS DENGAN ASVI
WARMAN ADAM
Penulis (D): Apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu, hingga terjadi peristiwa G30S?
Asvi (A): Saat itu kekuasaan terpusat atas tiga kubu, Soekarno, Angkatan Darat,
dan PKI. Nah, Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara Angkatan
Darat dan PKI, sampai meletusnya gerakan 30 September yang menyebabkan
keseimbangan itu menjadi terganggu bahkan berantakan.
Di sisi lain, PKI sedang berada di atas angin, mereka sedang
melakukan upaya-upaya yang disebut aksi sepihak. Aksi sepihak itu di mana
waktu itu pemerintah sedang memberlakukan peraturan di mana ada ketentuan
batas kepemilikan luas tanah yang dimiliki oleh seseorang, jika melebihi,
tanah itu akan disita oleh Negara untuk dibagikan selanjutnya.
PKI bersemangat sekali di dalam merealisasikan undang-undang itu,
mereka melakukan apa yang disebut aksi sepihak itu. Mereka mengambil
tanah yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah yang memiliki tanah-tanah yang luas
itu. Nah, tuan-tuan tanah ini kan cerdik juga, ketika ada undang-undang ini
diberlakukan, mereka menghibahkan tanahnya kepada Kiai, kepada pesantren
gitu. Nah, di situ baru muncul konflik ketika di satu sisi PKI dengan ormasnya
mencoba mengambil tanah itu, padahal tanah itu sudah diberikan kepada Kiai
ato pesantren itu. Jadi konflik antara PKI dan NU mulanya di situ, pada
dasarnya di situ, jadi bukan persoalan keyakinan, itu kan yang ditampilkan
kemudian, jadi pada intinya itu kan persoalan tanah, dan persoalan tanah ini
sangat sangat krusial, persoalan yang sangat menentukan hidup mati
seseorang, di desa. Jadi konflik horizontal antara orang-orang PKI dan NU itu
karena masalah tanah.
Nah, ketika meletus gerakan 30 September, keseimbangan berubah,
mereka yang dulu disakiti karena persoalan tanah ini membalas, sehingga
terjadi pembunuhan dan lain-lain. Dengan catatan juga bahwa pembunuhan itu
dimulai baru ketika tentara datang ke daerah itu, Jawa Tengah dan Jawa
134
Timur, sebelumnya kan belum ada pembunuhan. Jadi ketika tentara datang,
mereka juga melatih pemuda, kemudian melakukan penumpasan, dan di sisi
yang lain mereka yang sebelumnya sudah terlibat konflik itu juga ingin
membalas dendam gitu, sehingga terjadi pembunuhan yang sangat besar.
Nah, jadi di dalam hal ini saya mengatakan bahwa kelompok NU
menjadi pelaku di tahun 65, tapi mereka juga menjadi korban tentara pada
tahun 71, ketika akan ada pemilihan umum, barisan NU ini juga diserang oleh
tentara, mereka di lemahkan dalam rangka pemenangan pemilu oleh
pemerintah.
Nah, itu yang terjadi pada tahun 65. Kemudian kita tahu bahwa
sepanjang orde baru kita tahu bahwa sejarah itu kan direkayasa. Jadi yang
diajarkan itu kan juga sejarah versi tentara, versi pemerintah yang boleh satu
versi saja, jadi masalah rekonsiliasi itu sesuatu yang tidak pernah disuarakan,
bahwa selalu dipelihara stigma terhadap orang-orang kiri itu. Rekonsiliasi itu
baru dimulai setelah reformasi, kalangan muda NU juga mulai rekonsiliasi
kepada orang-orang eks-PKI, itu di Yogyakarta, kemudian mereka melebarkan
ke Jawa Tengah, dan di seluruh Pulau Jawa, rekonsiliasi dengan anak-anak
PKI.
Gus Dur juga adalah tokoh yang sangat peduli terhadap rekonsiliasi
kemajemukan itu, dan dia pernah mengatakan minta maaf atas apa yang
dilakukan oleh banser NU itu. Yang jadi persoalan adalah orang selalu marah
ketika upaya Gus Dur itu tidak diterima oleh Pramoedya Ananta Toer.
Sebetulnya pendapat Pram itu adalah pendapat pribadi, bukan pendapat
korban yang lain. Pram mengatakan bahwa Gus Dur tidak merasakan sakitnya
sebagai korban. Justru pandangan atau pendapat Pram itu diserang oleh korban
65 yang lain, Pram disalahkan mengapa mengeluarkan suara seperti itu,
harusnya kan diterima dengan baik. Nah, di sisi yang lain dari kalangan NU
menganggap, loh, orang sudah minta maaf kok tidak diterima, gitu. Jadi sudah
mulai ada proses ketidaksenangan dalam proses rekonsiliasi.
Masalahnya kemudian menjadi berbeda ketika NU itu mulai dipimpin
oleh wakil ketua umumnya itu orang yang berasal dari BIN (Badan Intelijen
135
Negara), Pak As’ad, warna NU itu mulai berubah, walaupun saya tahu bahwa
anak-anak muda NU itu sebagian besar masih pengikut Gus Dur. Tapi di sisi
lain, ada faktor Pak As’ad ini, gitu.
Ketika muncul laporan Tempo ini kan sebetulnya dibuat untuk
membahas film itu, tapi tidak cukup hanya dengan membahas film itu saja
dalam laporan khusus ini. Nah, mereka juga melakukan wawancara dengan
pelaku itu, sayangnya yang bisa atau berhasil diwawancarai oleh Tempo
adalah pelaku dari kalangan NU, seharusnya menurut saya harus lebih banyak
dari tentara, tapi mereka tidak berhasil mendapatkan itu. Jadi terkesan
pelakunya hanya NU, jadi ini yang menimbulkan kegusaran di kalangan NU,
jadi mereka mengeluarkan buku putih ini. Mereka sudah panggil pemimpin
redaksi Tempo ke NU, tapi mungkin solusinya adalah mereka terbitkan sendiri
buku putih ini (Benturan NU-PKI 1948-1965) untuk menjelaskan bagaimana
peristiwa 65 itu dari kacamata NU. Tapi buku putihnya sendiri menurut saya
mempunyai kelemahan yang mencolok, yaitu menimbulkan pertanyaan NU
dan TNI seolah-olah bersatu, jadi ini buku putih NU atau TNI, walaupun bisa
dimaklumi karena adanya Pak As’ad di sana.
D: Jika pada saat itu tidak ada kasus tanah, paham masyarakat terhadap
PKI atau komunisme bagaimana?
A: Saya melihat bahwa pertama, faktor agama itu dijadikan label selalu
untuk yang di luar itu. Pertama NU sendiri ketika pertama dulu bergabung
dalam Masyumi, namun kemudian pecah pada tahun 52 karena persoalan
mereka di dalam partai mendapat kedudukan yang tidak strategis, hanya
sebagai dewan Syuro atau semacam penasihat, sedangkan kedudukan
eskekutif tidak NU, sehingga mereka keluar.
Selama ini NU selalu menjadi Menteri Agama atau bekerja di dalam
Kementerian Agama sebagai pejabat di situ, selalu menjadi persoalan ketika
ada rivalitas antara NU dan bukan NU dalam hal birokrasi. Di sisi lain pada
tingkat masyarakat, itu kan persoalan tanah itu yang menjadi sangat krusial.
136
Saya ingin mengatakan bahwa fatwah mengenai atheisme ini pertama
kali dikeluarkan oleh Masyumi pada Bulan Desember tahun 54, jadi Masyumi
itu mengeluarkan fatwah bahwa atheisme itu artinya orang yang tidak ber-
Tuhan, dan tidak ber-Tuhan itu sama dengan kafir, nah kafir itu orang yang
boleh diberangi. Fatwah itu disampaikan Bulan Desember tahun 54, beberapa
bulan sebelum pemilu tahun 55. Jadi saya melihat ini kan kepentingannya
adalah kepentingan politik, jadi dalam rangka pemilu itu untuk menghalangi
orang untuk memilih PKI, apalagi PKI membuat slogan partai orang komunis
dan orang tidak berpartai gitu, jadi orang protes orang tidak berpartai
masuknya ke PKI. Jadi itu yang selalu digunakan, label agama itu, padahal
menurut hemat saya masalah pokoknya adalah yang menyangkut hajat apakah
itu tanah, kursi, jadi persoalannya itu politik atau pertanahan.
Dalam buku ini juga persoalan tanah ini sedikit disinggung, padahal itu
yang sangat penting. Tapi persoalan ada Masjid dibakar, tapi itu saya
pertanyakan, betul dibakar gak? Atau bagaimana prosesnya sampai
terbakarnya Masjid itu, kan gitu? Seakan-akan kan ya memang dikesankan
seperti itu, masyarakat kan sangat sensitif soal itu, bahwa ada Al-Quran
diinjak, Kitab Suci diinjak, atau pun Masjid dibakar, ketimbang kalau
dikatakan ini soal tanah, kalau soal tanah mereka menganggap itu sesuatu
yang biasa orang yang berkonflik soal tanah, tapi kan memang itu masalahnya
sebetulnya, tapi diberi label agama.
D: Jadi sebenarnya komunisme sama sekali tidak ada hubungannya dengan
agama?
A: Ya, itu yang sebenarnya seperti itu, jadi di kalangan PKI sendiri kan
ada juga Haji, mereka Haji, tokoh Islam, tapi juga komunis. Bahwa seperti
yang saya katakan tadi, bahwa untuk kepentingan politik, fatwah itu bahwa
komunisme sama dengan tidak beragama, tidak ber-Tuhan dan kafir, itu kan
karena menghadapi pemilu itu disampaikan.
Memang sebagian besar orang PKI itu adalah orang abangan, bukan
santri yang melakukan ibadah teratur, misalnya sembahyang lima kali sehari.
137
Tapi kalau abangan, mereka mengaku beragama tapi tidak melakukan ibadah.
Tapi kan tidak berarti pula mereka tidak percaya kepada Tuhan dan
sebagainya, mereka hanya tidak melakukan ibadah.
D: Jadi, melihat celah itu di mana orang-orang PKI tidak taat beribadah,
maka dibilang anggota PKI itu tidak beragama?
A: Ya. Kalau kita bicara tentang ajaran apapun yang berkembang dari
Eropa memang tidak dikaitkan dengan agama, apakah itu marxisme,
liberalisme, tapi saya mengatakan bahwa tidak berarti mereka itu atheis, tidak
berarti mereka tidak ber-Tuhan, atau anti Tuhan, mereka tidak mengaitkan
ideologi itu dengan agama. Tetapi di sini ditafsirkan atau sengaja dibuat
bahwa karena mereka tidak berkaitan dengan agama, mereka itu tidak
beragama, mereka itu tidak ber-Tuhan, tidak mengakui Tuhan.
D: Setelah Soeharto turun, ada banyak versi cerita tentang G30S, menurut
bapak versi mana yang besar, dan di bagian mana masing-masing pihak
terlibat?
A: Saya menganggap, versi yang relatif lengkap adalah versi yang
disampaikan oleh Soekarno, yang berada di pusat kekuasaan. Dia di dalam
pidato Nawaksara itu mengatakan bahwa G30S itu adalah pertemuan dari tiga
sebab, ada pimpinan PKI yang keblinger (kebablasan) terlibat disitu,
kemudian yang kedua adanya subversi nekolim, ada faktor asing, CIA, dinas
rahasia Inggris dan lain-lain, dan ketiga adanya oknum yang tidak
bertanggung jawab, oknum itu bisa para jenderal seperti Soeharto, dan lain-
lain, jadi ketiganya itu bertemu sehingga terjadilah G30S.
D: berarti benar G30S ini adalah tahap pertama dari kudeta merangkak
yang dilakukan oleh Soeharto?
138
A: Kudeta merangkak ini jelas analisis post-factum, artinya analisis
setelah peristiwa itu terjadi. Saya kira tidak ada orang yang percaya jika
Soeharto merencanakan semuanya dari awal, dia mengikuti saja dari awal dan
memanfaatkan celah-celahnya. Jadi kalau kita lihat setelah peristiwa itu
terjadi, pertama pada tanggal 1 Oktober itu jenderal-jenderal yang lebih senior
dari Soeharto sudah tersingkir, jadi tahap pertama itu tersinggirnya jenderal-
jenderal yang lebih senior dari dia kecuali Nasution, tetapi Nasution kan juga
tidak punya pasukan, artinya di atas kertas dia paling berpeluang menjadi
orang nomor satu di tentara.
Lalu yang berikutnya dia mencoba mengurangi kekuasaan dari
Soekarno dengan keluarnya Supersemar, membubarkan PKI, menangkap 15
orang menteri, dan kemudian mengontrol pers, dan membubarkan
Cakrabirawa yang mengawal Bung Karno, nah ini semua kan yang kemudian
kita sebut sebagai kudeta merangkak sehingga kekuasaan diserahkan kepada
Soeharto.
D: Apakah petrus dan penghilangan paksa juga masih berhubungan
dengan PKI?
A: Oh tidak. Petrus itu kan muncul karena pada tahun 80-an muncul
keresahan, banyak preman dan lain-lain, nah shock therapy-nya Soeharto itu
kan penjahat itu ditembak, atau orang-orang yang pakai tato itu ditembak,
ditaruh di tengah pasar, dan kejadian ini dilakukan ratusan kali sehingga
orang-orang menjadi takut untuk melakukan kriminalitas, tapi itu kan jelas
pembunuhan.
D: Jadi apakah urusan Soeharto dengan PKI itu hanya pada tahun 65-
66?
A: Oh enggak. Kekuasaan itu kan diberikan secara penuh kepada
Soeharto kan tahun 68, tetapi stigma itu kan diawetkan. Saya menganggap
PKI ini bukan hanya dianggap sebagai lawan atau musuh politik, tetapi juga
139
untuk kepentingan lain, sebagai alat pemukul politik. Ini dipelihara sehingga
orang yang bukan PKI, yang kritis terhadap pemerintah, itu nanti kan
gampang, di cap PKI gitu. Yang kedua ini untuk keperluan praktis, untuk
membeli tanah dengan harga murah, kalau mereka tidak mau, nanti di cap PKI
gitu.
Jadi kan digunakan sepanjang kekuasaannya, bukan hanya tahun
65 saja, bahkan sampai tahun 98. Jadi untuk dua keperluan tadi, yaitu
memukul lawan politik, dan keperluan praktis membeli tanah dengan murah.
Dan itu diawetkan stigma itu dengan monumen-monumen yang dibangun
selama orde baru. Monumen Pancasila Sakti itu dibangun pada awal, tapi kita
tahu Museum Penghianatan PKI itu baru dibangun tahun 93 di Lubang Buaya
juga. Di Gatot Soebroto ini dibangun museum Waspada Purwawisesa
namanya, itu museum yang dibangun untuk mengingatkan tentang bahaya dari
kelompok Islam radikal. Jadi sepanjang orde baru diciptakan terus itu
monumen-monumen, jadi tidak berhenti tahun 66, tapi sepanjang itu ada saja
monumen, buku yang dikeluarkan gitu, buku putih setneg itu kan tidak
dikeluarkan tahun 65-66, 90-an malah itu, jadi artinya sepanjang
kekuasaannya selalu dilestarikan stigma itu.
D: Menurut Bapak, bagaimana pandangan masyarakat tentang PKI
dan komunisme saat ini, masih sama atau sudah mulai berubah?
A: Mereka yang dahulu terlibat dalam peristiwa itu sebagai pelaku,
mereka tentu tidak berubah pandangannya, soalnya kalo mereka merubah
pandangannya mereka akan disalahkan, jadi mereka tidak akan merubah
pandangan atau perspektifnya, versinya kan yang memberontak PKI, karena
mereka pemberontak maka bisa diperlakukan apa saja. Jadi ini untuk
memberikan legitimasi, justifikasi terhadap apa yang mereka lakukan, jadi
orang-orang itu tidak berubah pandangannya sampai sekarang.
Nah, untuk generasi muda itu ada dua hal, pertama kan mereka
melihat sekarang kebebasan pers di media, di tv, di internet, sudah banyak
informasi tentang G30S, tapi di sisi yang lain, di tingkat sekolah mereka
140
diajarkan hal yang sangat terbatas sekali dan hanya satu versi. Jadi ada dua hal
itu, di satu sisi mereka mengetahui cukup banyak, tapi untuk di sekolah
mereka hanya diajarkan aspek yang sangat terbatas. Tapi saya melihat bahwa
generasi muda lebih banyak pengetahuannya dari pada orang-orang yang
belajar pada masa orde baru.
Seiring dengan peralihan generasi, itu kan berubah, ambil saja
contoh mengenai versi-versi G30S, orang yang menulis dalangnya itu PKI
tidak bertambah, orangnya itu-itu juga dari dulu, tapi orang yang menulis ini
ada CIA, atau Soeharto itu banyak anak-anak muda yang menulisnya,
sedangkan versi PKI itu tidak bertambah, sudah tidak menarik lagi, atau orang
sudah tidak percaya, itu versi sudah kuno dan tidak ada yang memperkaya.
Sedangkan ada yang mempersoalkan keterlibatan Soeharto, itu cukup banyak
skripsi yang baru.
D: Untuk paham komunisme sendiri, bagaimana pandangan
masyarakat sekarang ini?
A: Jadi di sini ada kepentingan dari berbagai partai untuk status quo
gitu. Di dunia tidak ada yang 100% menganut paham komunisme, RRC sekali
pun mereka sekarang ekonominya kapitalis, walaupun di sana masih ada partai
komunis. Jadi saya melihat ini sengaja dipertahankan untuk kepentingan
partai-partai, untuk menjaga konstituen-nya, karena PKI ini sudah diidentikkan
dengan anti agama, mereka muncul sebagai pembela agama, pembela
pancasila, ke-Tuhan-an yang Maha Esa gitu.
Sentimen masyarakat terhadap PKI dan komunisme akan
berkurang-berkurang terus, karena yang memelihara sentimen itu kan cuma
masih itu-itu juga orangnya, dan makin lama makin berkurang, mati atau apa,
jadi orang yang memelihara sentimen itu akan menyusut jumlahnya.
D: Menurut Bapak tentang majalah Tempo?
141
A: Saya melihat Tempo sudah menjaga kredibilitasnya, buktinya
ketika pemimpinnya Wahyu Muryadi ada nuansa politik di dalamnya dan ia
terlibat, ia diganti, digeser kedudukannya, sekarang Arif Zulkifli. Tempo
cukup kritis terhadap kalangan mereka sendiri kalau tidak kredibel. Saya juga
justru menghargai Tempo yang sangat berani karena Tempo-lah yang
mencoba menampilkan kekhasannya itu dengan liputan khusus. Yang menarik
itu kan tentang tokoh-tokoh, bukan hanya tokoh Islam, tetapi juga tokoh kiri.
Tempo-lah yang berani menerbitkan buku tentang empat orang tokoh kiri,
Aidit, Musso, Sjam, dan Njoto. Nah, majalah lain kan tidak ada.
Selama ini saya melihat pemberitaan mereka cukup obyektif,
berimbang, dan menggali berbagai informasi. Saya juga dilibatkan dalam
beberapa nomor di Tempo, juga menulis beberapa kolom, saya melihat itu
dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan hanya Tempo yang berani seperti itu,
bahkan khusus untuk edisi ini, menurut saya ini merupakan suatu keberanian
yang luar biasa. Bahkan pemimpin Tempo sempat dipanggil ke PBNU,
mereka datang dan “diinterogasi” kenapa, tapi mereka bisa menjelaskan
bahwa bukan tujuannya untuk mendiskreditkan NU, tapi untuk menguak
kebenaran sejarah, selama ini kan yang kita wawancarai adalah korban, tidak
ada pelaku, justru yang sangat penting itu kan pelaku. Itu terbukti dengan film
Oppenheimer ketika ada pelaku yang berbicara. Tempo dalam hal ini mencoba
melakukan hal yang sama, tapi nampaknya mereka kurang berhasil
mewawancarai pihak tentara, jadi kesannya seperti NU saja yang menjadi
pelaku. Padahal NU kan konflik horizontal, sedangkan tentara vertikal, berupa
penugasan, berhubungan dengan penguasa.
D: Setelah setahun terbit, apa tanggapan masyarakat yang bapak lihat?
A: Kita tahu bahwa Tempo untuk kelas menengah, bukan kelas
bawah. Kelas menengah kan bisa melihat dengan lebih komperhensif, lebih
jelas. Yang menarik adalah tanggapan, seperti munculnya buku putih NU ini,
padahal orang-orang tidak pernah menyalahkan NU, ini kan cuma pengakuan
pribadi-pribadi yang mengakui melakukan pembunuhan dan lain-lain, tapi
142
tidak menyalahkan organisasinya. Yang disalahkan kan tentara yang
melakukan operasi militer dan kemudian terjadi pembunuhan massal itu.
D: Selain Soeharto, adakah orang lain yang mengomandoi operasi militer itu?
A: Komando jelas dari Soeharto, tapi pidato tentang itu bukan hanya
dari Soeharto, tapi juga dari Nasution. Nasution berpidato ketika pemakaman
anaknya, yaitu akan menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Menumpas
sampai ke akar-akarnya itu ya berarti menghilangkan orang-orangnya juga.
D: Apakah dalam Majalah Tempo edisi ini Bapak juga melihat
adanya wacana rekonsiliasi?
A: Majalah ini sebenarnya terbit untuk merespon film Oppenheimer
itu, saya tidak melihat yang ditonjolkan itu rekonsiliasi, tidak seperti itu, tapi
saya melihat ini sesuatu yang baru, pelaku yang bersaksi, yang mengaku, saya
kira ini yang dilakukan oleh Tempo, mengejar pelaku.
D: Sudah sampai mana tahap rekonsiliasi dalam kasus ini di Indonesia?
A: Rekonsiliasi itu menurut saya antar masyarakat horizontal, jadi
antara orang-orang NU dan masyarakat bisa dilakukan rekonsiliasi, tapi yang
sifatnya vertikal seperti antara tentara dan masyarakat tidak perlu dilakukan
rekonsiliasi, mereka harus diadili. Ini kan kebijakan Negara, kebijakan
pemerintah, jadi tidak ada rekonsiliasi menurut saya, antara pelaku yang
sifatnya vertikal. Menurut saya hanya memberikan ganti rugi itu kan tidak
menyelesaikan persoalan, hukum itu harus ditegakkan.
D: Bapak setuju atau tidak dengan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?
A: Saya setuju ada. Saya melihat di sini Mahkamah Konstitusi
menelikung (jika dalam sepakbola, ketika wasit tidak melihat, kaki lawan
143
disamber hingga jatuh gitu). Kelompok Islam yang garis keras juga menuntut
UU KKR ini dibatalkan, tuntutan mereka tidak disetujui oleh MK, tapi pada
hakikatnya keputusan MK itu menyetujui pendapat mereka, yang dikabulkan
adalah tuntutan LSM, tapi dengan cara seperti itu, karena dikabulkan,
dianggap tidak ada rekonsiliasi antara pelaku dan korban, sehingga UU itu
batal, jadi MK memutuskan lebih dari apa yang diminta.
D: Untuk rekonsiliasi di masyarakat secara horizontal apakah sudah cukup?
A: Sudah cukup, itu sudah berjalan, jadi artinya rekonsiliasi antara
orang-orang NU dengan orang-orang eks-PKI sudah berjalan di masyarakat,
bahkan ada Forum Silaturahmi Anak Bangsa, di situ ada anak dari ketua PKI,
anak dari DI/TII, anak dari pahlawan revolusi, mereka sudah berkumpul dan
membuat organisasi. Jadi rekonsiliasi itu sudah terjadi, nah sekarang
persoalannya bagaimana menyelesaikan masalah ini supaya tuntas, apakah
dibentuk lagi KKR, atau presiden memberikan amnesti secara umum kepada
korban orde baru.
D: Bagaimana agar masalah G30S secara vertikal ini bisa tuntas?
A: Supaya tuntas itu jika presiden memberikan rehabilitasi kepada
korban tidak hanya korban 65 saja, tapi korban selama orde baru paling tidak,
supaya mereka dipulihkan nama baiknya, itu yang utama menurut saya, soal
ganti rugi uang itu persoalan belakangan.
Kemudian ada juga keputusan-keputusan pengadilan yang harus
dijalankan, misalnya Mahkamah Agung yang sudah memeriksa judicial
review, yang terkait kepada mereka yang tapol golongan C, yang pegawai
negeri dan ABRI, mereka kan dicabut hak pensiunnya. Nah Mahkamah Agung
sudah melakuan judicial review dan dalam website nya mereka menyatakan
putus dan Kabul. Putus itu artinya perkara itu sudah diputuskan oleh
144
Mahkamah Agung, dan sudah dikabulkan, tapi sudah setahun, mereka belum
menerima salinannya.
D: Bagaimana penyelesaian untuk pelaku?
A: Dari pelaku sendiri, pemerintah supaya menuntaskan kasus ini,
seperti pelanggaran HAM berat tahun 65, itu kan sudah dikaji dan diselidiki
oleh Komnas HAM, jika diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan bisa dilakukan
pengadilan HAM berat, kan bisa, Soeharto jelas sudah meninggal, tapi kan ada
di bawah-bawahnya yang masih hidup, jadi pengadilan itu harus dilakukan
walaupun yang bisa diadili cuma segelintir orang, tidak masalah menurut
hemat saya, selama keputusannya nanti menghukum mereka yang terlibat. Itu
sangat penting untuk sejarah, bahwa mereka dinyatakan bersalah, walaupun
satu-dua tahun lagi mereka juga akan meninggal.
D: Menurut Bapak apakah pemerintah kurang serius dalam menangani kasus ini?
A: Bukan kurang serius, tidak mau! Artinya, karena sudah berapa kali sudah
disampaikan berkasnya yang 65 itu, demikian juga dengan Mahkamah Agung,
keputusannya sudah ada, kenapa tidak di sahkan gitu. Mungkin mereka harus
didemo dulu baru bisa.
Related Documents