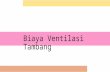Ventilasi Paru-Paru Ventilasi Paru-Paru dr. Simon Marpaung, M.Kes Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia 1

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Ventilasi Paru-ParuVentilasi Paru-Paru
dr. Simon Marpaung, M.Kes
Departemen Fisiologi
Fakultas Kedokteran
Universitas Methodist Indonesia11

22
Mekanisme PernafasanMekanisme Pernafasan
Dalam rongga toraks terdapat : Dua buah paru → perubahan volume paru
ditimbulkan oleh perubahan dimensi toraks.
Jantung dan pembuluh darah terkait. Esofagus. Timus. Beberapa saraf.

33
Terdapat kantong pleura yang memisahkan
paru dari dinding dada.
Kantong pleura dibentuk oleh 2 lapisan, yaitu
pleura-visceral dan pleura-parietal. Di antara
keduanya ada cairan sebagai pelicin.

44
Hubungan timbal balik antara tekanan
atmosfer, tekanan intra-alveolus, dan tekanan
intra-pleura penting dalam mekanika
pernafasan.
Akibat aktivitas siklik otot-otot pernafasan →
penurunan gradien tekanan yang berubah
antara alveolus dan atmosfer → udara masuk
dan keluar paru.

55
Ada 3 tekanan berbeda pada ventilasi, yaitu :
1. Tekanan atmosfer (barometrik).
2. Tekanan intra-alveolus = tekanan intra-pulmonalis. Setiap perbedaan antara tekanan intra-alveolus dengan tekanan atmosfer → udara mengalir → tercapai kesetimbangan (equilibrium).
3. Tekanan intra-pleura = tekanan intra-toraks, adalah tekanan di luar paru di dalam rongga toraks.

66
Tekanan intra-pleura lebih kecil daripada
tekanan atmosfer, rata-rata 756 mmHg saat
istirahat.
Tekanan yang penting pada ventilasi.
Tekanan intra-pleura = 756 mmHg ≠ tekanan
intra-alveolus (intra-toraks) = 760 mmHg ↔
tekanan atmosfer (barometriks) = 760 mmHg

77
Kohesivitas cairan intra-pleura dan gradien tekanan transmural menjaga dinding toraks dan paru berhadapan erat walaupun paru berukuran lebih kecil daripada toraks.Ketika toraks mengembang, paru juga
mengembang.Adanya gradien tekanan transmural.Mendorong paru ke arah luar, meregangkan
atau mengembangkan paru → mengisi rongga toraks.

88
Dinding dada cenderung “menciut” atau terkompressi. Adanya gradien tekanan transmural dan kohesivitas cairan intra-pleura mencegah paru dan dinding toraks tersebut saling menjauhi.

99
Proses InspirasiProses Inspirasi
Aktif akibat kontraksi otot-otot inspirasi. Pada
inspirasi tenang, pembesaran rongga dada
disebabkan oleh kontraksi :Diafragma (otot inspirasi utama).M.interkostalis ekstenus.
Pada pernafasan kuat, misalnya waktu
olahraga atau sesak nafas → otot inspirasi
tambahan turut kontraksi.

1010
m.levator kostarum.
m.skelanus.
m.seratus postukus superior.
Selama inspirasi : diafragma turun mendatar
sejauh ± 1,5 cm – 7 cm, mengakibatkan
pembesaran dimensi vertikal rongga dada
sekitar 75%.

1111
Dikenal 2 jenis pernafasan, yaitu :
1. Pernafasan dada (umumnya pada wanita).
2. Pernafasan perut (terutama pada pria), disebabkan oleh kontraksi diafragma.

1212
Proses EkspirasiProses Ekspirasi
• Pada pernafasan (euproe), ekspirasi merupakan proses aktif → akibat relaksasi otot inspirasi → paru teregang pada inspirasi → kontraksi otot inspirasi berhenti → ada daya rekoil paru dan dinding → relaksasi otot inspirasi → awal ekspirasi.
• Pada pernafasan kuat → kontraksi otot inspirasi lebih diperlambat → peralihan inspirasi → ekspirasi berjalan lancar (smooth).

1313
Pada ekspirasi kuat → kontraksi otot-otot
ekspirasi, yaitu :
m.rektus abdominalis
m.transversus abdominis
Keduanya untuk meningkatkan tekanan intra-
abdominal → mendorong diafragma

1414
Otot ekspirasi mulai berkontraksi menjelang
akhir proses ekspirasi.
Pada ekspirasi paksa (force expiration) →
kontraksi otot ekspirasi sejak awal ekspirasi.
Otot ekspirasi tambahan adalah
m.interkostalis internus.
Kontraksi otot ini → memperkecil dimensi
transversal rongga dada.

1515
Fungsi Saluran PernafasanFungsi Saluran Pernafasan
Sistem pernafasan tidak berpartisipasi dalam
semua langkah respirasi. Fungsi utama
pernafasan adalah untuk memperoleh O2,
digunakan oleh sel-sel tubuh dan
mengeliminasi CO2 yang dihasilkan oleh sel.
Dalam fisiologi, ada 2 jenis respirasi, yaitu :
1. Respirasi internal atau seluler.
2. Respirasi eksternal.

1616
Respirasi InternalRespirasi InternalRespirasi internal atau seluler adalah proses
metabolisme intrasel di dalam mitokondria,
menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 +
energi (nutrisi). Kuosien pernafasan
(respiratory quotient, RQ), yaitu perbandingan
(rasio) CO2 yang dihasilkan terhadap O2 yang
dikonsumsi, bervariasi bergantung jenis
makanan.
Jika karbohidrat → RQ = 1 → setiap molekul
O2 yang dikonsumsi, dihasilkan 1 mol CO2

1717
Jika karbohidrat → RQ = 1 → setiap molekul
O2 yang dikonsumsi, dihasilkan 1 mol CO2
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + ATP
Lemak → RQ = 0,7Protein → RQ = 0,8
Di Amerika Serikat → makanan campuran O2
yang dikonsumsi = 250 ml/menit
CO2 yang dihasilkan = 200 ml/menit
RQ rata-rata = CO2 yang dihasilkan
O2 yang dikonsumsi
= 200 ml/menit = 0,8
250 ml/menit

1818
Respirasi EksternalRespirasi Eksternal
Pertukaran O2 dan CO2 antara lingkungan
Esternal dan sel tubuh meliputi 4 langkah,
yaitu :
1. Udara masuk-keluar paru → pertukaran antara atmosfer (lingkungan eksternal) dan kantong udara (alveolus) paru → oleh kerja mekanis pernafasan atau ventilasi → sesuai dengan kebutuhan tubuh.

1919
2. O2 dan CO2 dipertukarkan antara dialveolus dengan darah → melalui proses difusi.
3. O2 dan CO2 diangkut oleh darah antara paru dan jaringan.
4. Pertukaran O2 dan CO2 antara jaringan dan darah melalui proses difusi.

2020
Udara (atmosfer) ↔ alveolus O2 dan CO2
difusi
darah paru O2 dan CO2 jaringan O2 dan CO2
difusi
darah

2121
Alveolus tempat pertukaran gas adalah suatu
kantong udara kecil, berdinding tipis, dan
dapat mengembang yang dikelilingi oleh
kapiler paru.
Di paru : 300 juta alveolus, garis tengah
sekitar 300 µm (⅓ mm) → luas permukaan
total = 1/100 m2

2222
Alveolus terdiri dari :Satu lapisan sel alveolus tipe I yang
gepeng, tipis, untuk mempermudah pertukaran gas.
Sel epitel lain adalah sel alveolus tipe II yang mengeluarkan surfaktan paru (kompleks fosfolipoprotein) → mempermudah pengembangan (ekspansi) paru.
Dinding alveolus ada pori-pori kohn → memungkinkan aliran udara antar alveolus → ventilasi kolateral.

2323
Volume dan Kapasitas ParuVolume dan Kapasitas Paru
Volume dan kapasitas paru dipengaruhi oleh :Bentuk/anatomi tubuh.Usia.Tinggi badan.Posisi tubuh.Daya regang paru.Ada tidaknya penyakit paru.

2424
Berbagai volume dan kapasitas paru adalah :
1. Tidal Volume (TV).
2. Volume Cadangan Inspirasi (VCI).
3. Kapasitas Inspirasi (KI).
4. Volume Cadangan Ekspirasi (VCE).
5. Volume Residual (VR).
6. Kapasitas Residual Fungsional (KRF).
7. Kapasitas Vital (KV).
8. Kapasitas Paru Total (KPT).
9. Volume Ekspirasi Paksa Dalam Satu Detik (Forced Expiratory Volume, FEV).

2525
Kapasitas Paru Total (KPT).
Volume udara maksimum yang dapat
ditampung oleh paru (KPT = KV + VR). Nilai
rata-ratanya = 5700 ml.
Volume ekspirasi paksa dalam satu detik
(Forced Expiratory Volume, FEV).

2626
Manfaat pengukuran volume dan kapasitas
paru adalah :
1. Pengetahuan akademik.
2. Petunjuk berbagai penyakit saluran pernafasan.
Ada 2 kategori, yaitu :
1. Obstruktif.
2. Restriktif.

2727
Penyakit lain :
1. Penyakit gangguan difusi O2 dan CO2
menembus membran paru.
2. Penurunan ventilasi akibat :
a. Kegagalan mekanis akibat penyakit neuronumkulus otot-otot pernafasan.
b. Penekanan pusat kontrol pernafasan oleh alkohol, obat, atau zat kimia lain.
3. Gangguan aliran paru.
4. Kelainan ventilasi/perfusi → udara tidak cocok dengan darah.

2828
Pertukaran GasPertukaran Gas
Gas berpindah mengikuti penurunan gradien
tekanan. Udara atmosfer normal yang kering
adalah 79% N2. 21% O2, CO2, uap H2O, gas
lain diabaikan. Secara bersama → gas-gas ini
tekanan atmosfer total = 760 mmHg (tekanan
parsial).
79%N2 → PN2 = 79% x 760mmHg = 600mmHg
21%O2 → PO2 = 21% x 760mmHg = 160mmHg
PCO2 = 0,3 mmHg → dapat diabaikan

2929
Oksigen masuk dan CO2 keluar dari darah di
paru secara pasif mengikuti penurunan
gradien tekanan parsial. Pertukaran O2 dan
CO2 menembus kapiler paru dan sistemik
yang disebabkan oleh gradien tekanan
parsial.
PO2 dan PCO2 arteri sistemik biasanya
relatif konstan setelah melakukan
keseimbangan dengan tekanan parsial
alveolus.

3030
PO2 dan PCO2 vena sistemik berubah-ubah,
bergantung pada tingkat aktivitas
metabolisme.
Melintasi kapiler paru :
Gradien tekanan parsial O2 dari alveolus ke
darah = 60 mmHg (100 → 40)
Gradien tekanan parsial CO2 dari darah ke
alveolus = 6 mmHg (46 → 40)

3131
Melintasi kapiler sistemik :
Gradien tekanan parsial O2 dari darah ke sel
jaringan = 60 mmHg (100 → 40)
Gradien tekanan parsial CO2 dari sel jaringan
ke darah = 6 mmHg (46 → 40)

3232
Fisiologi Pernafasan Transport Gas Fisiologi Pernafasan Transport Gas Darah dan Imbangan Asam-BasaDarah dan Imbangan Asam-Basa
Pengangkutan OksigenKemampuan Hb dalam fungsinya sebagai sarana
transport O2 berhubungan dengan 2 sifat penting, yaitu :a. Kemampuan Hb berubah menjadi bentuk
‘oxygenated’ sewaktu mengikat O2. Proses ini disebut oksigenasi, dan hasil akhirnya terbentuk oksihemoglobin : Hb + O2 → HbO2
b. Kemampuan Hb untuk melepas kembali O2 di kapiler jaringan menjadi bentuk ‘deoxygenated’ (deoksihemoglobin) :
HbO2 → Hb + O2

3333
Faktor terpenting dalam menentukan %
saturasi HbO2 adalah PO2 darah. Pada reaksi
reversibel antara Hb dan O2 (Hb + O2 ↔ HbO2),
maka peningkatan PO2 darah (misalnya di
kapiler paru) akan mendorong reaksi ke arah
kanan, sehingga pembentukan HbO2
ditingkatkan (% saturasi HbO2 meningkat).
Sebaliknya, penurunan PO2 darah (misalnya
di kapiler sistemik) menyebabkan reaksi
bergeser ke kiri. O2 akan dilepaskan dari Hb,
sehingga dapat diambil oleh jaringan.

3434
Kurva Disosiasi (Saturasi) Oksigen
Hemoglobin (O2-Hb)
Hubungan antara kedua variabel tersebut
digambarkan oleh kurva berbentuk huruf S
dengan bagian mendatar terletak antara PO2
60 mmHg dan 100 mm Hg dan bagian curam
antara PO2 0 mmHg dan 60 mmHg

3535
Kurva disosiasi HbO2 standar yang lazim
digunakan berlaku pada suhu dan pH tubuh
normal suhu 37 oC dan pH 7,4). Afinitas Hb
terhadap O2 dipengaruhi oleh beberapa faktor
yang dapat menyebabkan pergeseran kurva
disosiasi adalah :
a. pH dan PCO2
Penurunan pH/peningkatan PCO2 darah menyebabkan pergeseran kurva disosiasi HbO2 ke kanan.

3636
Artinya, pada PO2 yang sama, lebih banyak O2 yang dibebaskan. Keadaan ini berlangsung di kapiler pembuluh sistemik.
b. Suhu
Efek peningkatan suhu terhadap kurva disosiasi HbO2 serupa dengan efek peningkatan keasaman, kurva bergeser ke kanan.
c. 2-3-difosfogliserat (2.3-DPG)
2.3-DPG terdapat di dalam sel darah merah. Peningkatan 2.3-DPG akan menggeser kurva disosiasi HbO2 ke kanan.

3737
Kurva Disosiasi HbO2 Pada Janin
Afinitas Hb fetus terhadap O2 lebih besar
dibandingkan pada orang dewasa (kurva
disosiasi HbO2 fetus lebih curam/bergeser ke
kiri).

3838
Afinitas Hb Terhadap COAfinitas Hb Terhadap CO
Karbon monoksida (CO) berkompetisi dengan
O2 dalam mengikat Hb. Adanya sejumlah kecil
CO dalam darah sedah sukup untuk
mengurangi tersedianya Hb untuk transport
O2. HbCO akan menyebabkan pergeseran
kurva disosiasi HbO2 ke kiri. Keracunan CO
dapat terjadi tanpa disadari oleh korban.
Keracunan CO tidak mengalami sensasi sesak
nafas (‘breathlessness’).

3939
Pengangkutan COPengangkutan CO22
Diangkut dalam 3 bentuk, yaitu terlarut, terikat
dengan Hb/protein plasma, dan sebagai ion
bikarbonat.
a. CO2 terlarut
Daya larut CO2 dalam darah jauh lebih besar dibandingkan O2. Pada PCO2 normal, hanya ± 10% dari total CO2 dalam darah ditransport dalam bentuk terlarut.

4040
b. Ikatan dengan Hb dan protein plasma.
Sekitar 30% CO2 berikatan dengan bagian globin dari Hb, membentuk HbCO2 (karbaminohemoglobin). Sejumlah kecil CO2 juga berikatan dengan protein plasma (ikatan karbamino). Baik HbCO2 maupun ikatan karbamino merupakan reaksi longgar dan reversibel.
c. Ion HCO3
Ion HCO3 terbentuk dalam sel darah merah melalui reaksi :
CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3-

4141
Kurva Disosiasi COKurva Disosiasi CO22
Kandungan CO2 total dalam darah bergantung
pada besar PCO2. Hubungan antara
konsentrasi CO2 dan PCO2 dinyatakan sebagai
kurva disosiasi CO2. Kurva disosiasi CO2 juga
dipengaruhi oleh pH darah. Kurva ini pada
darah arteri (darah teroksigenasi) lebih ke
kanan dibandingkan dalam darah vena (darah
terdeoksigenasi).

4242
Efek Peningkatan PCOEfek Peningkatan PCO22, H, H++, suhu 2,3-, suhu 2,3-
Difosfogliserat dan Karbon Monoksida Difosfogliserat dan Karbon Monoksida Pada Kurva OPada Kurva O22-Hb-HbPeningkatan PCO2, asam, suhu, dan 2,3-
difosfogliserat menggeser kurva O2-Hb ke
kanan. Lebih banyak O2 dibebaskan dari Hb
untuk digunakan oleh jaringan. Keracunan
karbon monoksida, menggeser kurva O2-Hb
ke kiri. Lebih sedikit O2 yang dibebaskan dari
Hb pada PO2 tertentu di tingkat jaringan.

4343
Gradien Difusi Netto untuk OGradien Difusi Netto untuk O22 dan dan
COCO22 antara Paru dan Jaringan antara Paru dan Jaringan
Gradien netto untuk difusi O2 mula-mula dari
alveolus ke darah dan kemudian dari darah ke
jaringan. Dalam arah yang berlawanan
terbentuk gradien netto untuk difusi CO2
mula-mula dari sel jaringan ke darah dan
kemudian dari darah ke alveolus.

4444
Transportasi Karbon Dioksida Transportasi Karbon Dioksida Di Dalam DarahDi Dalam Darah
Karbon dioksida (CO2) yang diserap di tingkat
jaringan diangkut dalam darah ke paru
dengan 3 cara, yaitu :
1. Secara fisik terlarut.
2. Terikat ke hemoglobin (Hb).
3. Sebagai ion bikarbonat (HCO3-).

4545
Bikarbonat berpindah mengikuti penurunan
gradien konsentrasinya ke luar sel darah
merah masuk ke dalam plasma dan klorida
(Cl-) berpindah melalui pembawa pasif yang
sama ke dalam sel darah merah mengikuti
gradien listrik yang tercipta oleh difusi ke luar
HCO3-.

4646
Pengaturan Imbangan Pengaturan Imbangan Asam-Basa DarahAsam-Basa Darah
pH darah arteri normal berkisar antara 7,37 –
7,43 (rata-rata 7,4). Faktor-faktor yang
berperan dalam mempertahankan pH darah
yang konstan adalah buffer dalam darah,
pertukaran gas dalam paru dan mekanisme
ekskresi oleh ginjal.

4747
Sifat-Sifat Buffer Dalam DarahSifat-Sifat Buffer Dalam Darah
a. Ion bikarbonat.
Kemampuan sistem respirasi untuk mengatur besar PCO2 darah menjamin tersedianya konsentrasi buffer bikarbonat yang tinggi di dalam darah.
b. Fosfat.
Efek buffernya kecil.

4848
c. Proteinat.
Merupakan buffer darah yang cukup penting terutama karena dapat mengubah keasamannya melalui reaksi oksigenasi dan deoksigenasi.

4949
Pengaturan PernafasanPengaturan Pernafasan
Otot pernafasan yang secara ritmik harus
mengisi dan mengeluarkan udara dalam paru.
Otot-otot pernafasan (yang merupakan otot
skelet) melalui persarafan dapat berkontraksi.
Spontan berirama oleh lepas muatan teratur
(‘rhytmic discharge’) dari pusat pernafasan di
batang otak. Di samping itu, dapat
dimodifikasi dan diatur secara volunter (di
bawah kemauan).

5050
Pusat PernafasanPusat Pernafasan
Pusat mekanisme pengaturan pernafasan ada
2, yaitu pusat pengaturan pernafasan volunter
(di bawah kemauan) dan pusat pengaturan
pernafasan otomatis (spontan). Pusat
pernafasan volunter terletak di korteks serebri
dan impulsnya disalurkan melalui traktus
kortikospinalis menuju motor neuron saraf-
saraf pernafasan.

5151
Di batang otak bertanggung jawab dalam
membentuk pola pernafasan ritmik. Terdiri
dari 3 bagian, yaitu pusat respirasi (inspirasi-
ekspirasi), pusat apneustik, dan pusat
pneumotaksik.
a. Pusat respirasi.
Terletak di formasio retikularis medula oblongata, menyebabkan terjadinya pernafasan spontan. Secara anatomis, pusat respirasi dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok dorsal (‘dorsal respiratory group’ = DRG) dan kelompok ventral

5252
(‘ventral respiratory group’ = VRG). Kelompok dorsal terutama terdiri dari neuron I. Kelompok ventral terdiri dari neuron I dan neuron E. Apabila kebutuhan ventilasi meningkat, neuron I pada kelompok ventral diaktifkan melalui rangsang dari kelompok dorsal. Neuron E akan dirangsang untuk mengeluarkan impuls yang akan menyebabkan kontraksi otot-otot ekspirasi, sehingga terjadi ekspirasi aktif. Terdapat pula suatu mekanisme “feed-back’ negatif antara neuron I kelompok dorsal dan neuron E kelompok ventral.

5353
b. Impuls dari neuron I-DRG, selain merangsang motor neuron otot inspirasi, juga akan merangsang neuron E-VRG. Neuron E-VRG sebaliknya akan mengeluarkan impuls yang menghambat neuron I-DRG. Dengan demikian, neuron I-DRG akan menghentikan aktivitasnya sendiri melalui pelepasan rangsang inhibisi.
c. Pusat apneustik.Pusat ini terletak di formasio retikularis pons bagian bawah, mempunyai pengaruh tonik terhadap pusat respirasi. Pusat ini dihambat oleh impuls aferen melalui n.vagus.

5454
d. Pusat pneumotaksik.
Pusat ini terletak di pons bagian atas, menghambat aktivitas neuron I, sehingga rangsang inspirasi dihentikan. Kedua pusat tersebut menyebabkan impuls spontan dan berirama pada pusat respirasi menjadi lebih halus dan teratur, sehingga proses inspirasi dan ekspirasi berjalan dengan mulus (‘smooth’).

5555
Pengaturan Pusat PernafasanPengaturan Pusat Pernafasan
1. Rangsang kimia.
PO2 dan PCO2 darah yang meninggalkan paru dipertahankan konstan. Dilakukan melalui variasi irama dan amplitudo pernafasan. Rangsang yang akan meningkatkan ventilasi adalah penurunan PO2, peningkatan PCO2, respirasi melalui perangsangan reseptor kimia (kemoreseptor) di perifer dan di pusat.

5656
Kemoreseptor perifer.Glomus karotikum yang terletak pada percabangan a.karotis komunis, dan glomus aortikum pada arkus aorta adalah reseptor kimia perifer yang peka terhadap peningkatan PCO2 dan penurun PO2/pH darah. Rangsang pada glomus karotikum diteruskan ke pusat respirasi melalui cabang n.glossofaringeus, sedangkan rangsang dari glomus aortikum disalurkan melalui cabang asendens n.vagus. Akibat perangsangan reseptor kimia ini, ventilasi akan meningkat. Penurunan PCO2 dan peningkatan PO2/pH darah menyebabkan kemoreseptor kurang terangsang, sehingga

5757
mmHg. Penurunan PO2 arteri (hipoksia) akan merangsang kemoreseptor perifer dan meningkatkan impuls ke pusat respirasi. Respons peningkatan ventilasi baru akan tampak jelas apabila PO2 arteri turun lebih rendah dari 60 mmHg. Respons ventilasi akan tampak lebih nyata apabila kekurangan O2 terjadi bersama-sama dengan peningkatan PCO2 arteri.
Respons ventilasi terhadap peningkatan PCO2 arteri
Pada keadaan istirahat, PCO2 arteri memegang peranan penting sebagai

5858
pemberi informasi ke pusat respirasi dalam mengatur besar ventilasi. Peningkatan metabolisme jaringan menyebabkan peningkatan PCO2 arteri, menimbulkan refleks perangsangan ke pusat respirasi, dengan akibat meningkatnya ventilasi, akan berhenti. Sebaliknya, penurunan PCO2 arteri menurunkan refleks perangsangan ke pusat respirasi, sehingga ventilasi menurun.
c. Sistem limbik dan hipotalamus diduga menyalurkan impuls aferen menuju pusat pernafasan, karena rangsang nyeri dan emosi mempengaruhi pola pernafasan.

5959
d. Proprioseptor di otot, tendo, dan sendi mengirimkan impuls melalui serat aferen menuju ke medula oblongata untuk menggiatkan pernafasan sewaktu melakukan olahraga.
e. Baroreseptor di sinus karotikus, arkus aorta, atrium, ventrikel, dan pembuluh darah besar, selain menyalurkan impulsnya melalui serat aferen menuju ke pusat respirasi, menimbulkan inhibisi ke pusat respirasi. Apabila terjadi peningkatan tekanan darah, secara refleks terjadi penurunan frekuensi denyut jantung, penurunan ventilasi, dan vasodilatasi pembuluh darah.

6060
f. Peningkatan suhu tubuh akan menggiatkan pernafasan, ventilasi meningkat.
g. Hormon epinefrin akan merangsang pusat respirasi, sehingga ventilasi meningkat.
h. Berbagai iritasi pada mukosa, menimbulkan refleks bersin, batuk, menelan, muntah, menguap, tampak perubahan pola pernafasan.
i. Refleks Hering-Breuer, yaitu refleks hambatan inspirasi-ekspirasi. Pada saat inspirasi mencapai batas tertentu, reseptor regang yang terdapat pada parenkim paru, serta otot polos saluran pernafasan akan

6161
terangsang, disalurkan melalui serat aferen n.vagus menuju DRG di medula oblongata, dan menghambat aktivitas neuron I (‘inflation reflex’). Demikian pula pada saat ekspirasi mencapai batas tertentu, terjadi perangsangan reseptor kompresi yang terletak pada septum alveol. Impuls dari reseptor kompresi akan menghambat terjadinya ekspirasi lebih lanjut (‘deflation reflex’).

6262
Tahan NafasTahan Nafas
Pusat pengaturan pernafasan volunter
memungkinkan seseorang dengan sengaja
menahan nafas sampai batas tertentu. Saat di
mana nafas tidak dapat ditahan lagi disebut
sebagai titik lepas (‘breaking point’).
Hilangnya kemampuan menahan nafas
disebabkan oleh peningkatan PCO2 dan
penurunan PO2 darah arteri.

6363
Faal Pernafasan Sewaktu OlahragaFaal Pernafasan Sewaktu Olahraga
Pada waktu melakukan kerja fisik berat,
ventilasi alveolar dapat meningkat sampai 20x
lebih besar dibandingkan keadaan istirahat,
untuk memenuhi kebutuhan O2 jaringan yang
meningkat, serta pengeluaran CO2 yang
berlebih dari dalam tubuh.

6464
Peningkatan ventilasi pada awal gerak badan
terjadi secara mendadak, diikuti kenaikan
yang bertahap. Peningkatan ventilasi
mendadak pada awal kerja fisik mungkin
disebabkan oleh :
1. Sebagian impuls dari korteks serebri menuju otot skelet ke formasio retilularis batang otak dan merangsang pusat respirasi.
2. Gerakan otot rangka, melalui proprioseptor di otot, tendo, dan sendi akan merangsang pusat respirasi.

6565
3. Peningkatan rangsang simpatis akan meningkatkan kadar hormon epinefrin.
Peningkatan ventilasi selanjutnya (bertahap)
mungkin disebabkan oleh faktor humoral
(CO2, O2, pH), serta peningkatan suhu tubuh.
Penurunan ventilasi yang tiba-tiba pada akhir
kerja fisik disebabkan oleh hilangnya
rangsang korteks serebri dan proprioseptor.
Rangsang ventilasi pada akhir kerja fisik oleh
kadar ion H darah arteri yang masih tinggi
akibat ‘lactic acidemia’.

6666
Perubahan di paru-paru sewaktu olahraga :Aliran darah yang masuk ke dalam paru
akan meningkat.PO2 darah vena sistemik yang masuk ke
dalam paru turun dari 40 mmHg sampai 25 mmHg.
Peningkatan jumlah aliran paru dan beda PO2 alveol-kapiler.
Peningkatan ambilan O2 darah sebanding dengan berat kerja yang dilakukan.
Jumlah CO2 yang dikeluarkan paru meningkat.
Perbedaan perfusi antara bagian apeks dan basis paru akibat pengaruh gravitasi akan

6767
hilang waktu gerak badan.Volume pernafasan semenit meningkat dari
6 L/menit waktu istirahat menjadi 100 – 150 L/menit (mencapai 200 L/menit) saat gerak badan.
Perubahan di jaringan sewaktu olahraga :Penggunaan O2 oleh otot yang melakukan
kerja akan meningkat.Pembuluh kapiler otot bervasodilatasi dan
jumlah kapiler yang aktif juga meningkat.Pada PO2 darah di bawah 60 mmHg,
kemampuan Hb mengikat O2 makin lemah.

6868
Peningkatan CO2 darah (penurunan pH) dan kenaikan temperatur tubuh juga menyebabkan kemampuan Hb mengikat O2 melemah, sehingga lebih banyak lagi O2 yang dibebaskan untuk dikonsumsi oleh jaringan.

6969
Fisiologi PernafasanFisiologi PernafasanFaal Pernafasan Pada Sakit Faal Pernafasan Pada Sakit
dan Sehatdan Sehat
Terpenuhinya kebutuhan jaringan akan O2
bergantung pada kerja sama erat antara
sistem pernafasan, jantung, pembuluh darah,
serta kondisi jaringan lokal.
PendahuluanPendahuluan

7070
Hipoksia adalah kekurangan O2 di tingkat seluler. Hipoksia dibagi atas 4 golongan, yaitu:a. Hipoksia hipoksik, yaitu hipoksia akibat
kekurangan O2 di dalam darah, ditandai dengan rendahnya PO2 darah disertai saturasi HbO2 yang tidak adekuat. Penyebabnya adalah :
HipoksiaHipoksia

7171
Penyebabnya adalah : Gangguan pada pertukaran gas di paru. Terpapar pada ‘high altitude’, lingkungan
dengan kadar oksigen rendah atau akibat hipoventilasi.
b. Hipoksia anemik, yaitu kurangnya O2 di jaringan akibat menurunnya kapasitas transport O2 oleh darah. Hal ini dapat disebabkan oleh :
Kurangnya jumlah sel darah merah (anemia).
Kurangnya jumlah Hb dalam sel darah merah (eritrosit abnormal).

7272
Terdapatnya Hb abnormal yang kurang efektif mengikat O2 (methemoglobin).
Keracunan CO.
c. Hipoksia sirkulatorik, yaitu hipoksia karena menurunnya jumlah darah teroksigenasi yang sampai di jaringan. Hipoksia sirkulatorik dapat terjadi setempat akibat spasme pembuluh darah lokal atau sumbatan lokal. Secara umum sebagai akibat gagal jantung kongestif atau syok sistemik.

7373
d. Hipoksia histotoksik, yaitu hipoksia yang terjadi akibat ketidakmampuan jaringan untuk mengambil atau menggunakan oksigen.
Pada beberapa jenis hipoksia (tidak semua),
terjadinya kekurangan O2 disertai pula dengan
hiperkapnia, yaitu meningkatnya jumlah CO2
dalam darah.

7474
Urutan kepekaan berbagai jaringan terhadap
hipoksia adalah sebagai berikut :Susunan saraf pusat.Otot jantung.Hati, ginjal, dan saluran pencernaan.Otot rangka.Kulit.

7575
Hipoksia ringan ditandai dengan menurunnya
kemampuan melihat malam. Pada keadaan
lebih berat terjadi rasa mengantuk, lemah,
mual, sakit kepala, kadang-kadang eforia.
Pada keadaan lebih berat lagi, terjadi
penurunan kemampuan menilai (‘judgement’)
dan daya ingat, diikuti ‘muscle twitch’, kejang-
kejang, koma, dan akhirnya kematian.

7676
Pengobatan dengan O2 dimaksudkan untuk
memperbaiki hipoksia jaringan. Beberapa
keadaan yang membutuhkan pemberian
oksigen adalah : Kegagalan pernafasan. Kehilangan darah. Serangan jantung dan gagal ginjal. Penyakit paru atau trauma. Sumbatan jalan nafas.
Terapi OksigenTerapi Oksigen

7777
Stroke : jaringan otak memerlukan suplai O2 terus menerus.
Syok : kegagalan sistem kardiovaskuler untuk menyediakan cukup darah ke jaringan vital.
Trauma kepala berat : sumbatan jalan nafas dan trauma sistem kardiovaskuler dapat menurunkan suplai O2 ke otak.

7878
Pemberian oksigen berlebih menimbulkan
keadaan membahayakan hidup. Kecepatan
aliran harus diatur sedemikian rupa, sehingga
konsentrasi O2 yang diberikan pada penderita
sesuai dengan tujuan terapi. Hasil
pengobatan O2 terbaik didapatkan pada terapi
hipoksia hipoksik. Sedangkan pada hipoksia
hostotoksik, terapi O2 tidak akan memberikan
perbaikan apa-apa.
Bahaya Terapi OksigenBahaya Terapi Oksigen

7979
A. Bahaya terapi oksigen non medis adalah :
1. Kerusakan pada dinding tabung atau katup akan menyebabkan tabung meledak.
2. Oksigen memperbesar penyebaran kebakaran.
3. Oksigen di bawah tekanan tidak dapat bercampur dengan minyak. Kontak antara keduanya akan menimbulkan ledakan.

8080
B. Bahaya medis pemberian oksigen adalah :
1. Keracunan oksigen : pemberian O2 konsentrasi tinggi untuk jangka waktu lama akan menyebabkan kerusakan jaringan paru, dengan gejala hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, dan rasa tidak nyaman di bawah sternum.
2. Kolaps alveol : kadar O2 rendah akan menyebabkan alveol mengembang, kadar yang tinggi akan menyebabkan alveol berkerut. Pemberian O2 konsentrasi tinggi untuk waktu lama dapat menyebabkan kolaps alveol yang irreversibel (atelektasis).

8181
3. ‘Retrolental fibroplasia’ : pembentukan jaringan parut di belakang lensa pada bayi akibat pemberian O2 kadar tinggi.
4. Henti nafas : terutama pada penderita COPD (‘chronic obstructive pulmonary disease’), termasuk emfisema, bronkitis kronis, dan ‘black lung’. Pemberian O2 di atas 28% dapat menimbulkan henti nafas.
5. Depresi pernafasan : dijumpai pada sebagian penderita penyakit paru kronik pada keadaan asidosis respiratorik, diikuti penurunan kesadaran.

8282
6. ‘Bronchopulmonary dysplacia’ : terbentuknya kista dan pemadatan jaringan parenkim paru. Sindroma ini merupakan manifestasi keracunan oksigen dan sering timbul pada bayi dengan ‘respiratory distress syndrome’ yang diobati dengan O2.

8383
a. Penurunan tekanan atmosfer.Makin tinggi dari permukaan laut, tekanan atmosfer makin rendah, namun komposisi (kadar) berbagai gas di udara tetap sama. Makin tinggi dari permukaan laut, makin kuat pula rangsang hiperventilasi, sehingga timbul alkalosis respiratorik.
b. Peningkatan tekanan atmosfer.Menyelam sedalam 10 m di air laut atau 10,4 m di air tawar, akan meningkatkan tekanan pada tubuh sebesar 1 atmosfer.
Pengaruh Perubahan Tekanan Pengaruh Perubahan Tekanan Atmosfer Pada PernafasanAtmosfer Pada Pernafasan

8484
Seorang penyelam harus bernafas dengan udara bertekanan sama besar dengan lingkungannya. Dengan sendirinya, tekanan dan jumlah gas yang larut dalam cairan tubuh meningkat sesuai dengan peningkatan tekanan udara tersebut.
c. Penyakit dekompresi.Apabila seorang penyelam yang telah cukup lama berada di kedalaman 20 m, menggunakan udara yang mengandung 78% N2, mendadak naik ke permukaan laut, atau seorang penerbang pesawat (tanpa penambahan tekanan dalam kabin) mendadak naik ke ketinggian 8.550 m (tekanan udara ⅓ atm), timbul gangguan

8585
yang disebut penyakit dekompresi, menyebabkan nitrogen yang larut dalam darah dan jaringan berubah bentuk menjadi gelembung udara. Gelembung udara di jaringan menyebabkan rasa nyeri, terutama di sekitar sendi, serta gejala gangguan saraf, seperti rasa kesemutan (parestesia), dan gatal. Gelembung udara di dalam darah dapat menyebabkan penyumbatan arteri di otak, paru, dan lain-lain (emboli udara) dengan gejala yang lebih berat.

8686
d. Emboli udara.
Emboli udara dapat pula terjadi apabila penyelam naik mendadak ke permukaan sambil menahan nafas (terutama pada akhir inspirasi) sehingga alveol dan pembuluh paru pecah, dan udara masuk ke dalam aliran darah.
Related Documents